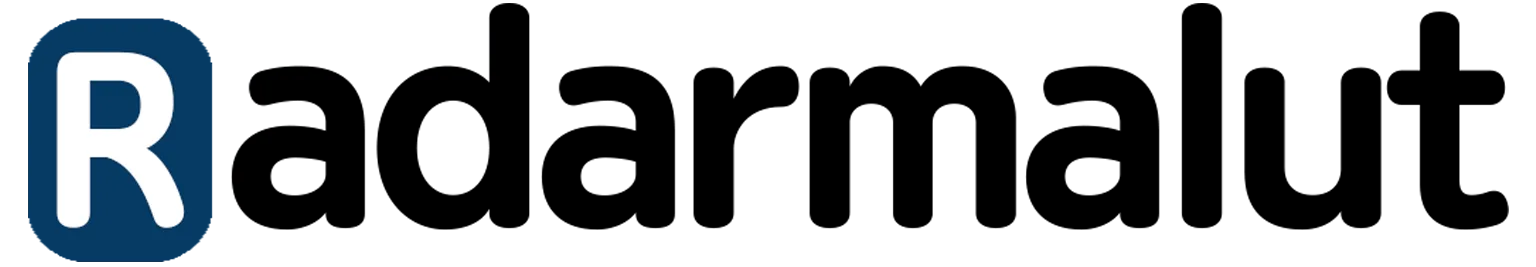Berbagai kekuatan muncul di daerah pada awal revolusi. Di Sumatera Timur, kaum bangsawan dibabat. Mengapa pihak republik bisa bertahan di Sumatera Barat? Mengapa Ambon berontak?
Bagi orang asing yang ingin mengerti sejarah masyarakat Indonesia abad ke-20, periode revolusi masih mempunyai daya tarik yang kuat. Penyusun buku, Audrey Kahin, dari Cornell Modern Indonesia Project, Amerika Serikat, berhasil mengumpulkan delapan orang yang mampu menulis ciri-ciri khas sejarah revolusi di berbagai daerah di Indonesia dari Aceh sampai Ambon.
Mereka hampir semuanya adalah sejarawan muda dari AS, Australia, dan Inggris yang menaruh perhatian khusus pada masa revolusi. Studi kasus di bukunya disusun Kahin dalam tiga bagian, atas dasar peranan yang dimainkan pada bulan-bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan oleh kekuatan luar daerah, yaitu Belanda dan pemerintah pusat RI.
Bagian pertama, yang diberi judul Daerah-Daerah yang Bebas dari Kekuasaan Luar, mengandung tiga kasus: Tiga Daerah (kabupaten-kabupaten Brebes, Pemalang, dan Tegal), Banten, dan Aceh. Bagian kedua, Medan Perang untuk Negara-Negara yang Bersaing, berisi dua bab tentang Sumatera Timur dan Sumatera Barat.
Dan, bagian ketiga, Daerah-Daerah yang Dikuasai Belanda, menggambarkan jalannya revolusi di Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon. Menurut penyusun, faktor kekuasaan luar ini sangat mempengaruhi kejadian-kejadian di setiap daerah, khususnya pada awal revolusi.
Dilihat dengan kaca mata lokal, delapan kasus ini merupakan (meminjam kalimat Kahin) “sederetan revolusi-revolusi daerah yang sebagian besar bersifat otonom tetapi mempunyai tujuan formal bersama–negara Indonesia yang merdeka” (halaman 282).
Pemimpin-pemimpin revolusi dan pengikut mereka di daerah menganut berbagai ideologi, serta cita-cita mengenai bentuk bangsa dan negara Indonesia, yang menjadi impian mereka. Variasi-variasi ini disebabkan oleh perbedaan struktur sosial, ekonomi, hubungan historis dengan penjajah, dan pola kebudayaan, khususnya agama.
Satu-satunya revolusi lokal yang berhasil mencapai cita-citanya adalah gerakan Islam modernis di Aceh, yang dipimpin oleh PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Ketika mengambil alih kekuasaan sebagai akibat pergolakan revolusioner.
PUSA “mempunyai pandangan yang jelas tentang Orde Baru yang diinginkannya dan berhasil menciptakan suatu negara yang pro-republik dan sekaligus otonom dan konsisten dengan ajaran-ajaran Islam” (halaman 268 ‘ 69).
Yang membedakan Aceh dari daerah lain adalah keterpaduan yang tercapai antara kekuatan-kekuatan revolusioner di bawah kepemimpinan PUSA. Di tiga daerah dan Banten sebuah koalisi terdiri dari ulama, orang-orang nasionalis radikal, dan bandit-bandit (di tiga daerah disebut lenggaong, di Banten jawara) berhasil menggulingkan pangreh praja pada awal revolusi.
Tapi koalisi ini tidak bertahan lama. Pemimpin-pemimpin radikal ikut terguling dan setelah itu jabatan-jabatan penting dipegang oleh para ulama. Namun, mereka pun diancam terus-menerus oleh berbagai lawan, dan tidak pernah bisa menguasai pemerintahan daerah.
Yang menonjol di Sumatera Timur dan Sumatera Barat adalah persaingan yang terjadi, dari awal sampai akhir revolusi, antara Belanda dan republik dan antara golongan-golongan pro-kemerdekaan.
Di Sumatera Timur, perpecahan dan perlawanan berdasarkan suku, agama, dan kedudukan sosial-ekonomi dimanfaatkan bekas penjajah untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan revolusioner dan mendirikan pemerintahan boneka Negara Sumatera Timur.
Di Sumatera Barat, pihak republik bisa bertahan karena: keadaan suku dan agama yang relatif homogen; kepercayaan masyarakat kepada pejabat-pejabat republik (konon disebabkan kebijaksanaan lama Belanda dan Jepang yang merekrut pegawai-pegawai dari banyak lapisan masyarakat).
Hubungan akrab dengan tokoh-tokoh Minangkabau di pusat seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir; dan dukungan dari TNI setempat serta laskar-laskar yang kuat dan bisa bekerja sama.
Golongan-golongan daerah yang pro-kemerdekaan tidak dapat menandingi kekuatan Belanda di Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon. Jakarta digambarkan sebagai daerah yang tidak mempunyai elite asli tradisional ataupun pemimpin-pemimpin baru dengan visi lokal tentang bentuk negara merdeka yang mereka perjuangkan.
Pejabat-pejabat republik di PNKD (Pemerintah Nasional Kota Djakarta) didatangkan dari daerah-daerah lain, dan tidak punya basis politik di Jakarta.
Di Sulawesi Selatan, daerah yang sultan-sultannya berpihak pada republik, dikontraskan dengan Sumatera Timur, tempat kaum bangsawan dibabat habis oleh pemuda-pemuda radikal. Pemimpin-pemimpin revolusioner di Sulawesi Selatan, moderat dan radikal, terpaksa bersatu karena mereka menghadapi pasukan penjajah yang kuat dan kejam.
Kasus Ambon diberi judul: Bukan Revolusi Melainkan Kontra-Revolusi. Yang dimaksudkan adalah gerakan sekelompok orang Ambon, yang beragama Kristen dan berkebudayaan Belanda, yang pada akhir revolusi menolak hasil Konferensi Meja Bundar, dan menyatakan kemerdekaan Republik Maluku Selatan.
Mereka dilawan oleh orang-orang Islam dan Kristen pro-republik, yang, waktu itu, diperkirakan merupakan mayoritas penduduk Ambon. Oleh Kahin dan Richard Chauvel, penulis bab ini, RMS dianggap mewakili sikap pegawai-pegawai kolonial di seluruh Indonesia.
Bedanya, di Ambon mereka cukup kuat untuk memaksakan kehendaknya, meskipun untuk sementara saja. Di dalam kehidupan sosial, yang biasanya gelap dapat dijadikan terang oleh sorotan cahaya gejolak sosial yang dahsyat seperti revolusi.
Dari delapan kasus revolusi lokal yang telah saya ringkaskan, jelas sekali bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari banyak golongan dengan aspirasi, cita-cita, dan tuntutan masing-masing. Lebih dari itu, kejadian-kejadian di daerah umumnya bersifat otonom, tidak banyak digiring dari luar.
Sebagai ilmuwan politik, saya tertarik juga oleh reaksi pemerintah kepada kenyataan ini. Kalau sinar laser revolusi diarahkan kepada perilaku pemerintah terhadap golongan-golongan lokal tadi, apa yang akan kita temukan?
Jawaban Kahin dan kawan-kawan cukup jelas. Pemimpin-pemimpin pemerintahan nasional bersikap dan bertindak konservatif. Di hampir setiap daerah mereka berusaha bekerja sama dengan pegawai-pegawai eks kolonial, dan sering juga dengan raja-raja dan sultan-sultan.
Di Sumatera Barat, kebijaksanaan ini berhasil karena korps pegawai di sana mendapat dukungan luas dari masyarakat. Tetapi pemerintah pusat tidak bisa menguasai Aceh setelah uleebalang-uleebalang dibunuh, dan di Tiga Daerah, Banten, dan Sumatera Timur golongan elite kolonial dihanyutkan oleh aliran radikal.
Di Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon, pemerintah RI secara de facto mengakui kekuasaan Belanda. Tindakan ini lebih konservatif lagi, dalam pengertian bantuan tidak dapat diberikan kepada golongan apa pun.
Apa yang menyebabkan reaksi konservatif ini? Kahin menekankan lemahnya pemerintah pusat ketimbang golongan-golongan agama dan radikal di daerah. Juga penting: keperluan akan dukungan dari luar negeri, khususnya negara-negara Barat yang antikomunis; dan keperluan untuk mendirikan birokrasi negara, yang sejauh mungkin dapat menguasai seluruh wilayah republik.
Analisa keadaan politik zaman dulu itu tentu mengundang pertanyaan lebih lanjut. Apakah buku ini membekali kita untuk menelaah perkembangan-perkembangan pada masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Orde Baru?.
Sudah jelas bahwa pemerintah pasca-revolusi sering bergumul dengan kekuatan-kekuatan daerah yang terkadang cukup kuat. Sementara itu, keperluan-keperluan akan dukungan luar dan pengukuhan birokrasi tetap mendesak. Bagaimana dengan pemerintah Orde Baru?.
Pemerintah sekarang kelihatan lebih kuat, dan masyarakat tidak lagi terpecah-pecah seperti empat puluh tahun silam. Kenyataan ini mungkin merupakan suatu pertanda bahwa di samping model lama, kerangka konsepsi yang baru perlu juga dirumuskan.
***
R. William Liddle Peneliti Ahli pada Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.