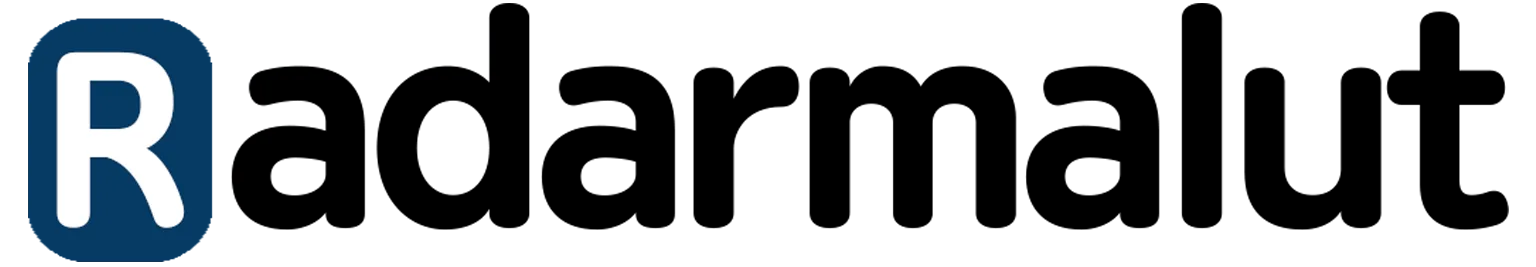Menarik mencermati opini berjudul “Simfoni Ruang di Pulau Gebe: Meluruskan Nalar Hukum Tabolabale” yang ditulis oleh Hamdan Halil. Saat membaca tulisan tersebut, terus terang saya merasa tergelitik–bukan karena kekuatan argumennya.
Melainkan karena cara narasi itu dibalut dengan rujukan Undang-Undang, Perda, dan berbagai regulasi formal seolah-olah hukum positif sudah cukup untuk menutup seluruh persoalan sosial yang terjadi di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.
Sambil menyeruput kopi hitam, saya kembali teringat pada pemikiran Hannah Arendt, filsuf Jerman yang sejak lama menaruh kecurigaan pada peran intelektual. Arendt mengkritik bagaimana kaum intelektual kerap terasing dari realitas konkret dan mudah terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai logically coherent fictions.
Fiksi yang tampak logis secara internal, tetapi justru berfungsi membenarkan ketidakadilan, bahkan kejahatan. Ia mencontohkan keterlibatan Martin Heidegger, filsuf besar Jerman, dalam proyek ideologis Nazisme yang menopang kepentingan Hitler.
Semoga saja posisi intelektual Hamdan Halil tidak bergerak ke arah yang pernah diperingatkan Arendt tersebut. Bagi saya, tulisan Hamdan lebih tampak sebagai upaya menutupi polemik pertambangan di Pulau Gebe dengan mengandalkan logika positivistik semata.
Logika ini dijadikan klaim utama untuk membenarkan bahwa ruang sosial di Pulau Gebe tidak bermasalah sebagaimana yang disuarakan para aktivis dan masyarakat sipil. Menurut Hamdan, tata ruang wilayah telah diatur melalui Perda yang berpijak pada regulasi nasional; karenanya, aktivitas pertambangan dianggap sah dan memperoleh legitimasi hukum.
Dari titik ini, kritik publik tidak lagi dibaca sebagai ekspresi kegelisahan sosial atau pembelaan hak masyarakat lokal, melainkan direduksi menjadi persoalan kognitif. Para pengkritik bahkan dilabeli mengalami ‘anemia nalar’, istilah yang dipinjam dari ranah psikologi untuk menggambarkan gangguan fungsi berpikir.
Penurunan konsentrasi, daya ingat, lambannya pemrosesan informasi, hingga kebingungan emosional. Dalam kerangka ini, kritik dianggap lahir dari emosi semata dan menghasilkan apa yang disebut Hamdan sebagai ‘nalar hukum tabolabale’ (terbalik-balik).
Dangkal dan Problematis
Pendekatan semacam ini, alih-alih ilmiah, justru terkesan dangkal dan problematis. Istilah ‘nalar hukum tabolabale’ tidak dijelaskan secara konseptual maupun diuji secara argumentatif; ia hanya berfungsi sebagai label peyoratif untuk mendiskreditkan lawan kritik.
Dalam kajian ilmiah dan logika argumentasi, pola semacam ini dikenal sebagai ad hominem–atau lebih spesifik, fallacy of dismissal: menolak kritik dengan menyerang pribadi, kondisi psikologis, atau kapasitas kognitif pengkritik, tanpa pernah menyentuh substansi persoalan yang dikritik.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan adanya dampak nyata dari aktivitas pertambangan: ketimpangan penguasaan ruang, kerusakan ekologis, serta perampasan hak-hak masyarakat lokal.
Namun, alih-alih membahas persoalan-persoalan material tersebut secara jujur dan terbuka, yang diserang justru psikologi dan nalar para pengkritik. Inilah yang membuat argumentasi Hamdan bukan hanya lemah secara akademik, tetapi juga berbahaya secara etis–karena berpotensi membungkam kritik sah atas nama legalitas formal.
Hukum dan Relasi Kuasa
Dalam diskursus teori kritis, hukum tidak pernah bersifat netral. Ia selalu bekerja di dalam dan melalui relasi kuasa tertentu. Karena itu, klaim Hamdan yang mendasarkan pembenarannya pada tata ruang, undang-undang, peraturan daerah, dan berbagai regulasi lainnya tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai representasi ‘suara jernih’ konstitusi.
Legalitas formal tidak otomatis identik dengan keadilan sosial maupun keadilan ekologis. Hukum formal–seperti undang-undang, perda, maupun RTRW; tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai praktik sosial-politik.
Ia dijalankan, ditafsirkan, dan dioperasikan dalam konteks kepentingan, kekuasaan, dan struktur ekonomi tertentu. Oleh sebab itu, menjadikan regulasi sebagai argumen final justru berpotensi menutup ruang kritik terhadap ketimpangan, eksklusi sosial, dan kerusakan ekologis yang lahir dari penerapannya.
Kalau pun benar seluruh proses telah harmonis, mengapa justru mencul sorotan publik, pemberitaan media, serta protes warga lokal yang khawatir terjadi kerusakan di wilayah pesisir, hutan dan terancamnya ruang hidup. Ini membuktikan bahwa adanya kesenjangan antara narasi hukum dan realitas sosial.
Simfoni atau Disonansi?
Jika benar tata ruang, Perda, dan sejumlah regulasi lainnya menjadi legal hukum di Pulau Gebe adalah sebuah simfoni, demi terselenggaranya kepentingan yang strategis.
Maka, seharusnya tidak menghasilkan nada sumbang berupa penolakan warga, protes mahasiswa, ketakutan akan dampak lingkungan, dan bahkan menjadi sorotan nasional. Ini membuktikan yang terjadi bukanlah harmoni, melainkan disonansi antara hukum, data, dan keadilan sosial.
Maka protes serta kritik terhadap eksploitasi tambang di Pulau Gebe bukan bentuk tabolabale. Melainkan upaya meluruskan hukum agar kembali pada tujuan dasarnya: keadilan sosial dan keadilan atas lingkungan, bukan melayani kepentingan modal.
Dan pada titik ini, Hamdan selaku intelektual harus berada di garda terdepan membangun kesadaran publik, menjelaskan bagaimana hukum diproduksi, ditafsirkan, dan dijalankan.
***
Firmansyah Usman Jurnalis dan Pegiat Lingkungan