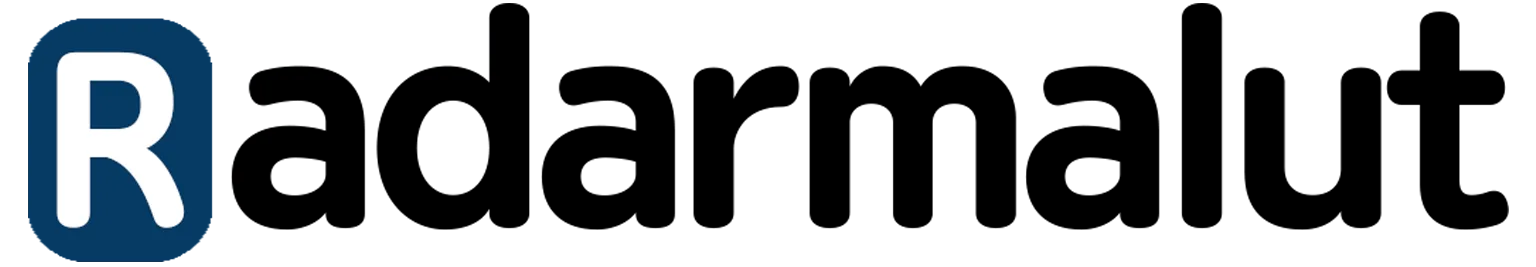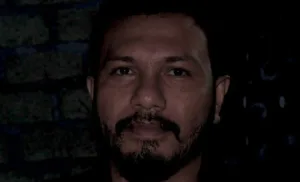Hilirisasi industri, transisi energi, ekonomi hijau, energi terbarukan, dan beragam istilah yang dilabeli “hijau” secara struktural merupakan penanda. Ia terdiri dari beragam kegiatan bisnis berbasis lingkungan yang diklaim berkelanjutan.
Sketsa semiotika atas istilah ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara sebuah bahasa dikenali dan dipergunakan dalam semua kegiatan, yang sesungguhnya mengarah pada praktik-praktik ekstraktivisme.
Bahasa bukan sekadar kumpulan kata-kata. Karena saat kata dipergunakan untuk tujuan representasi, ia memungkinkan setiap orang untuk membuat pesan dengan cara-cara yang kuat. Karena pesan verbal secara semiotik tidak berbeda dengan teks non-verbal.
Verbal sendiri hanyalah salah satu modal semiotika yang digunakan manusia untuk membuat pesan. Itulah kenapa, istilah ekonomi hijau, misalnya, jauh lebih dari sekadar fungsi komunikasi yang sederhana.
Ekonomi hijau menekankan siapa mengatakan apa pada orang yang mana, di mana dan bagaimana harus dikatakan, serta kapan dan mengapa dikatakan. Artinya, istilah ini dimotivasi dan dibentuk dengan latar belakang dan tujuan pesan tersebut disampaikan.
Istilah ini bukan sekadar menciptakan pandangan baru atas sebuah industri, tapi mengukuhkan apa yang sedang dipraktikkan. Karena istilah ekonomi hijau sendiri merupakan hasil konstruksi dari serangkaian aktivitas dengan cara paling ekonomis. Orang awam akan tetap menerima, tanpa memikirkan konsekuensi dari metafora semacam ini.
Ekonomi hijau tidak dapat dipandang sebagai alat retorika belaka. Metafora ekonomi hijau menjadi ringkasan dan substansi dari cara pemikiran abstrak yang berkembang. Ini relevan dengan hipotesa pakar linguistik antropologi, Benjamin Lee Whorf, yang mengusulkan bahwa dengan mengubah bahasa, kita akan mengubah perilaku sosial yang menyertainya.
Perbandingan antara kata “kebakaran hebat” dengan “dilalap si jago merah” jelas memiliki kesan yang berbeda, meskipun bersumber dari satu peristiwa yang sama: kebakaran. Tapi kata “si jago merah” memberikan efek puitis, emosional, atau deskriptif yang lebih kuat daripada perbandingan harfiah yang terkesan kaku.
Begitu juga dengan ekonomi hijau. Ekonomi sendiri adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana orang membuat pilihan tentang alokasi sumber daya dari segi uang, waktu, dan tenaga yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas.
Perekonomian bukan hal yang konkret. Perekonomian bersifat abstrak yang kerap digunakan untuk mempermudah pemikiran terhadap data finansial yang beragam jenis. Termasuk soal tingkat inflasi, ketenagakerjaan, serta pengeluaran dan pendapatan masyarakat.
Sedangkan hijau adalah warna sekunder dari spektrum cahaya tampak. Hijau sendiri sering dikaitkan dengan alam, pertumbuhan, kehidupan, dan kesegaran. Karena pigmen klorofil pada tumbuhan menyerap cahaya biru dan merah yang kemudian memantulkan cahaya hijau tersebut.
Itu berarti, istilah ekonomi hijau adalah sebuah metafora untuk mendukung apa yang disebut dengan prinsip “saling terkait.” Ia seakan mendapat kesamaan untuk mengaitkannya secara semiotis.
Sebab, dengan pelabelan “hijau” tadi, maka pendengar seakan diminta untuk membayangkan perekonomian berbasis lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan. Sementara, industri pertambangan seperti nikel tidak pernah berbicara soal “pemulihan”.
Tapi dengan cara ini, pendengar tentu tidak sekadar mendapat gambaran tentang daftar angka atau grafik. Tapi lebih dari itu, dan pada akhirnya membuat maknanya menjadi kabur dan tidak jelas. Tapi toh, siapa yang mau menanyakan pesan di balik istilah “ekonomi hijau” tadi.
Orang lebih terpicu untuk bereaksi terhadap daya tarik bahasa, tanpa memikirkan secara saksama tentang apa makna, pesan, atau siasat apa yang sedang dibangun.
Menjadi jelas bahwa jika kekuasaan politik dan ekonomi dikonsentrasikan di tangan segelintir elit, maka definisi apapun mengenai pembangunan yang dibuat akan sejalan dengan peluang dan kepentingan mereka sendiri.
Dan istilah “ekonomi hijau” hanyalah jargon negara-korporasi untuk menyamarkan praktik perampasan ruang hidup rakyat. Fakta hari ini, menyalahkan orang-orang yang dikorbankan dapat dipandang sebagai sebuah proses ideologis.
Setidaknya, itu yang sedang berlangsung di daratan Pulau Halmahera. Ini kemudian mengakibatkan efek-efek psikologis atas pemiskinan yang telah melekat kuat dalam benak pikiran masyarakat.
Pendekatan ini tidak mempertimbangkan tentang keadilan dalam aspek distribusi keuntungan yang paling fundamental. Kelompok-kelompok yang berkepentingan telah mencari legitimasi lewat tekanan dan kesengsaraan manusia, yang diakibatkan oleh ketidakadilan ekstrem melalui penjelasan rasional dan ilmiah.
Dengan kata lain, upaya tersebut telah mempertahankan status ketidakadilan dan oleh karena itu mengakibatkan tertundanya perubahan.
Terutama kemiskinan, dipandang sebagai sebuah status ekonomi yang secara etimologi berhubungan dengan akses. Dari sini, dibuatlah konsep dan strategi dalam menanggulangi kemiskinan melalui transfer sumber daya yang hanya dapat dicapai melalui kata “industrialisasi dan hilirisasi.”
Kita semua tahu, bahwa model pembangunan hari ini hanya diukur berdasarkan pendapatan per kapita. Sementara, yang tidak ada dalam definisi ini adalah pembangunan secara mental, sosial, budaya, dan spiritual dari individu maupun komunitas dalam sebuah keadaan yang bebas dari tekanan dan paksaan.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara teori, pembangunan dalam bentuk apa pun nyaris tidak ada perubahan. Justru pola pendekatan, mekanisme, dan sistem ekonomi yang dibangun lebih berwatak eksploitatif. Secara politik bersifat represif dan dalam aspek budaya lebih terkesan hegemonik.
Dengan demikian, istilah-istilah “hijau” sesungguhnya tidak punya kaitan dengan kesejahteraan rakyat maupun keadilan sosial. Tapi didorong motif kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global.
Meskipun istilah seperti itu menjanjikan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi masyarakat secara luas, tapi semua itu sesungguhnya adalah kelanjutan dari kolonialisme berbasis sumber daya alam berlabel “hijau”.
***
Nurkholis Lamaau adalah seorang Jurnalis dan Pegiat Lingkungan