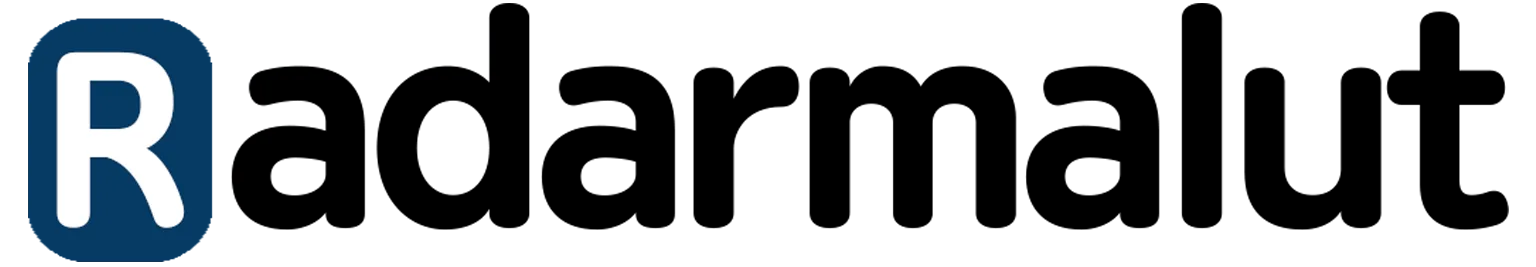Seperti menonton film horor, mungkin itu reaksi saya saat membaca bantahan Hamdan Halil atas opini saya “Ketika Simfoni Tata Ruang Menjadi Alibi Kekuasaan”. Sayangnya dua hantu yang disebut itu salah alamat. Kok bisa, saya nulis tata ruang Pulau Gebe, lah yang muncul Marx dan Faucoult.
Dua hantu ini pasti akan linglung, keduanya akan saling bercakap: “ini bukan Eropa abad 19 dan 20? Ini sebuah pulau. Mengapa kita tiba-tiba diasingkan di sini?”
Padahal, saya tidak menyalakan bara, tidak membakar kemenyan, tidak berkomat-kamit merapal mantra memanggil arwah orang-orang kiri dari kuburan teorinya. Tapi ya sudahlah, mungkin begitulah cara kerja nalar hukum tabobale.
Masalahnya, dalam tulisan saya, Marx dan Foucault itu nihil alias Nol besar. Tidak ada mode of production, surplus value, konflik kelas, revolusi sosialis, kaum buruh. Tidak pula Foucault: genealogi kekuasaan, discourse formation, dan biopolitics.
Justru Hannah Arendt di sana menggelengkan kepalanya kepada Heidegger, ada ilmu pengetahuan logika ad hominem fallacy of dismissal, dan Gustav Radbruch pemikir hukum yang pandangannya sering dipakai orang-orang yang masih percaya hukum seharusnya adil, bukan sekadar sah secara administrasi.
Tapi ya sudahlah, di negeri ini mereka yang berbeda secara pikiran pasti dicurigai penyembah dua hantu di atas.
Ketika Produk Hukum Dianggap Wahyu
Ada kebiasaan aneh di sebagian kalangan: mereka memperlakukan produk hukum seperti Perda, UU Cipta Kerja, dan regulasi lainnya layaknya sebagai wahyu. Tidak boleh dikritik, tidak boleh dipertanyakan, apalagi diuji materil. Kalau ada yang berani bersuara, langsung dituduh sesat ideologis.
Secara teori hukum dan kebijakan publik, produk hukum itu bukan benda sakral, bukan benda yang turun dari langit. Produk hukum lahir dari proses politik melalui kompromi-kompromi kepentingan, dan tentu saja ada potensi cacat. Justru karena itu, kritik dibutuhkan.
Lucunya lagi, dalam perencanaan wilayah modern, tata ruang hanya dipahami sebagai dokumen saja, bukan melalui proses sosial yakni partisipasi masyarakat. Kalau tata ruang Pulau Gebe benar-benar lahir dari proses partisipatif, mestinya warga tidak ribut, mahasiswa tidak turun aksi, dan media tidak penuh polemik.
Hukum Itu Alat, Bukan Kitab Suci
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia mempertanyakan hukum berkeadilan sosial atau tidak, itu menjadi hak warga. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Namun ketika hukum diposisikan sebagai kitab suci, yang boleh menafsir hanya segelintir orang, maka keadilan berubah menjadi hafalan ayat untuk membungkam mereka yang kafir.
Dan jika setiap kritik tata ruang harus dibalas dengan memanggil Marx dan Foucault, mungkin masalahnya bukan pada teori kritis. Masalahnya: ada yang terlalu nyaman hidup tanpa kritik.
***
Firmansyah Usman Jurnalis dan Pegiat Lingkungan