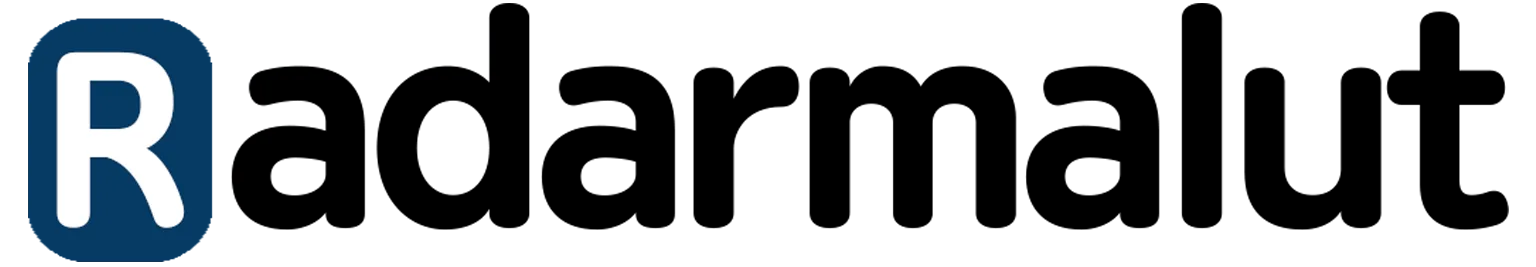Pungutan liar sejak akhir tahun lalu (1977,red) dan sampai kini, jadi persoalan dominan dalam kehidupan negara kita. Mungkin ia selanjutnya akan merupakan hal utama dari pembaruan-pembaruan tata susunan ekonomi-sosial dan politik Indonesia.
Ada baiknya kalau kita menyadari apa arti dari pada kampanye-kampanye anti pungli ini dan apa sebenarnya persoalan di sekitar pungli.
Pungutan liar (istilahnya bukan itu dahulu) punya akar mendalam di sejarah. Asal mula darinya adalah dalam sestim pembiayaan negara tradisionil, yakni kerajaan-kerajaan Indonesia dari Majapahit sampai ke Mataram dan kesultanan-kesultanan lain di kepulauan ini.
Jabatan dari kerajaan-kerajaan tradisionil itu tidak dibiayai dari pusat. Mereka harus berdikari dalam hal keuangan. Raja hanya memberikan pada pejabat tanah dan sejumlah petani, atau hak-hak untuk memungut bea cukai, meminta denda dan upeti dari rakyat yang berhubungan dengan si pejabat.
Dan dari sumber keuangan tersebut dibiayai urusan jabatan. Jabatan menteri di kraton, bupati di daerah, pengawas pengairan, jagal, pencatat penduduk, penarik pajak, kepala desa dan lain-lain, berdiri sendiri dalam keuangan.
Selain lungguh, yakni “gaji tetap” yang berupa tanah dan petani, pejabat menarik biaya bagi kelancaran urusannya dari rakyat yang bersangkutan. Makin banyak aktivitas dari seorang penduduk biasa, makin banyak urusannya dengan para pejabat. Maka semakin banyak pula beban “pajak” atau upetinya.
Staf atau pegawai dari para pejabat itu juga sedikit banyak otonom dalam keuangan. Mereka harus mencari nafkah sendiri dari kedudukannya itu. Gaji resmi tidak diterima atau tidak mencukupi.
Gejala ini sampai terlihat di kalangan rumah tangga seorang bupati. Pelayan seorang bupati misalnya, yang harus menyampaikan surat padanya dari seorang pemohon atau pegawai rendah, pun untuk urusan jabatan, sering menerima persen.
Sampai pertengahan abad ke-19 koki di suatu keluarga bupati hampir tidak menerima gaji tetapi persen dari para penjual di pasar.
Raja sendiri sebenarnya termasuk dalam sistim ini. Raja menerima sebagian dari upeti rakyat yang diberikan pada para pejabat. Dengan singkat para pejabat, terutama para pejabat tinggi, berkewajiban memberikan upeti pada raja, di samping membiayai urusan jabatannya.
Sering juga upeti dari para pejabat ini diperoleh dengan cara menjual jabatan itu pada para penawar yang tertinggi. Si pembeli kemudian bisa menarik sebanyak mungkin keuntungan materiil dari wewenang yang didapatnya.
Kedudukan bupati pesisir misalnya sering dijual secara demikian, sehingga pedagang asing sering dapat membelinya. Ia bisa jadi bupati atau penarik pajak.
Ada suatu hal yang agak menarik dari sistim ini. Raja sendiri sebagai penguasa tertinggi mungkin hanya menikmati sedikit dari upeti dan pajak dari rakyat ini. Sebagian besar dibayarkan pada para pejabat rendahan.
Sebenarnya raja sendiri sebagai penguasa tertinggi agak lemah kedudukannya, sebab kontrol keuangan terhadap bawahannya sama sekali tidak ada. Para bawahan raja sebenarnya otonom dan tidak mudah dipecat.
Di lain pihak, karena mengangkat pejabat dan pegawai baru baik bagi sang Raja maupun bagi para pejabat sering tidak merugikan (karena tak perlu menggaji mereka)–malahan bisa menguntungkan kalau kedudukan-kedudukan di jual.
Maka ada kecenderungan untuk mengangkat semakin banyak pejabat dan pegawai atau memperbesar pengikut. Yang merasakan beban beban adalah rakyat biasa dengan diperbanyaknya perantara atau calo antara yang diperintah dan yang memerintah.
Ini tidak menambah efisiensi urusan-urusan negara. Lebih sering membikin kabur batas wewenang, sampai pada akhirnya hanya yang tertinggi dapat menentukan segala sesuatu, sementara para bawahannya berusaha supaya ketetapan dari yang teratas itu gagal.
Dalam keadaan tradisionil ini orang dapat mengatakan bahwa setiap pejabat adalah penarik pajak. Sestim otonomi keuangan para pejabat sebenarnya mengaburkan hierarki dalam tata susunan masyarakat tradisionil.
Seorang pejabat rendahan yang efisien dapat mengumpulkan kekayaan atau upeti lebih besar dari pada atasannya yang tidak efisien. Dalam sejarah kita ada contoh di mana seorang bawahan dapat menjamu rajanya sendiri secara lebih mewah daripada raja itu sendiri dapat menjamu para tamunya.
Atau si penarik pajak dapat meremehkan para abdi-dalam kraton tertinggi, juga para menteri, bahkan para pangeran, sebab penghasilannya jauh melebihi penghasilan mereka dan mereka semua berhutang padanya.
Namun seorang raja kuat dan juga seorang pejabat kuat mempunyai satu senjata ampuh terhadap bawahan yang serakah, yakni para orang kaya-baru. Raja dan pejabat tertinggi yang dalam kedudukan kuat selalu dapat memaksakan apa yang disebut denda.
Rupanya apa yang disebut denda dalam abad-abad yang lalu itu dapat dipaksakan pada setiap orang dengan alasan apapun. Seorang dapat didenda karena hadir dalam suatu jamuan dan juga dapat didenda karena tidak hadir dalam jamuan yang sama.
Denda ini dapat merupakan semacam pungutan liar yang sak banyak dalam zaman dahulu. Seorang raja Jawa pada akhir abad ke-18 umpamanya diketahui telah mengumpulkan uang denda sebanyak jutaan rijksdaelders selama masa pemerintahannya. Bila dihitung dalam zaman sekarang itu dapat dibandingkan dengan ratusan-juta dolar Amerika
Namun ada satu perbedaan besar antara “denda” dan “pungli”. Istilah “denda” menunjukkan bahwa para penguasa tertinggi pada masa lampau dapat melegalisir “pungli” yang pada masa sekarang merupakan korupsi, sesuatu yang terhina. Sebab menurut norma-norma sekarang para pejabat adalah untuk rakyat dan tidak sebaliknya.
Mudah-mudahan para pembaca jangan sampai menyimpulkan bahwa “pungli” ternoda karena salahnya demokrasi dan modernisasi zaman sekarang. Tapi bagaimana dengan persoalan hari kini? Pungli jelas merupakan gejala dalam Republik Indonesia.
Persoalannya di sini adalah bahwa bukan tidak ada usaha dari pemerintah pusat untuk menggaji pegawainya, tetapi gaji itu dan kebutuhan lainnya (perumahan, transport) tidak cukup. Jadi juga tidak diatur secara sentral.
Republik Indonesia bukan satu-satunya contoh yang demikian. VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-XVIII adalah perseroan perdagangan yang rugi biarpun pegawainya menjadi kaya raya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini kita lihat negara melimpahkan sebagian kekuasaannya pada segolongan masyarakat, yang dinamakan pejabat atau klas pemerintah, tanpa menjamin tingkatan dan taraf hidup mereka.
Baik pemerintah maupun masyarakat akan hidup dalam khayalan bila mereka mengira bahwa klas-pemerintahan itu dapat menahan diri sendiri untuk hidup dalam serba kekurangan. Atau bahwa mereka tidak akan “menyalah-gunakan” kekuasaan yang diberikan pada mereka.
Dengan singkat para pejabat yang tidak dijamin secara cukup, akan mengadakan pungli, dan seperti dalam sistim pemerintahan tradisionil akan membiayai diri sendiri secara cukup, atau berlebih-lebihan, menurut kesempatan masing- masing.
Gejala pungli dapat dijelaskan secara sosiologis. Tapi secara politis dan dari sudut hierarki sosial masalah pungli sebenarnya mengacaukan. Dengan sistim pungli sebagai sistim pembiayaan para pejabat, maka pejabat dalam jabatan tertentu dapat memiliki penghasilan lebih besar dari pada atasannya.
Misalnya seorang camat yang harus mendaftarkan setiap jual beli tanah warisan dapat memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar daripada seorang bupati yang hanya mendaftarkan apa yang dilaporkan camat.
Biarpun pungli erat sekali hubungannya dengan sistim penggajian para pejabat negara, pada suatu waktu baik dari pemerintah maupun dari khalayak ramai bisa timbul kekesalan terhadapnya. Pungli lalu benar-benar menjadi sesuatu yang liar, sesuatu yang melanggar hukum dan ternoda dan bukan lagi upeti atau denda.
Itu biasanya timbul pada saat dirasakan perlu adanya rasionalisasi dalam birokrasi. Artinya perbedaan tingkatan di antara para pejabat akan dipertegas. baik menurut wewenang ataupun menurut penghasilan.
Maka sesuatu yang kelihatan ganjil bisa timbul dalam kampanye anti-pungli meskipun sebernya itu wajar dalam proses rasionalisasi, yakni bahwa yang diganyang biasanya pungli kecil-kecilan atau yang dari pejabat rendahan.
Ini bukan saja karena terhadap pungli rendahan pemerintah cukup berkuasa untuk memberantasnya (sedangkan yang besar secara politis agak sukar) tetapi juga karena yang kecil lebih mengacaukan hierarki birokrakrasi.
Jadi bukan keadilan yang terutama ingin dicapai dengan pemberantasan pungli, tetapi rasionalisasi–dengan segala akibatnya bagi makin hierarkisya susunan masyarakat kita. Namun, kegiatan memberantas pungli ini tentu saja biasa dan perlu diadakan dalam perkembangan masyarakat.
***
Ong Hok Ham biasa disapa Hans adalah seorang Sejarawan berlatar belakang Tionghoa-Indonesia, yang wafat pada 30 Agustus 2007 di Jakarta. Ia meninggal dunia di usianya ke-74 tahun.