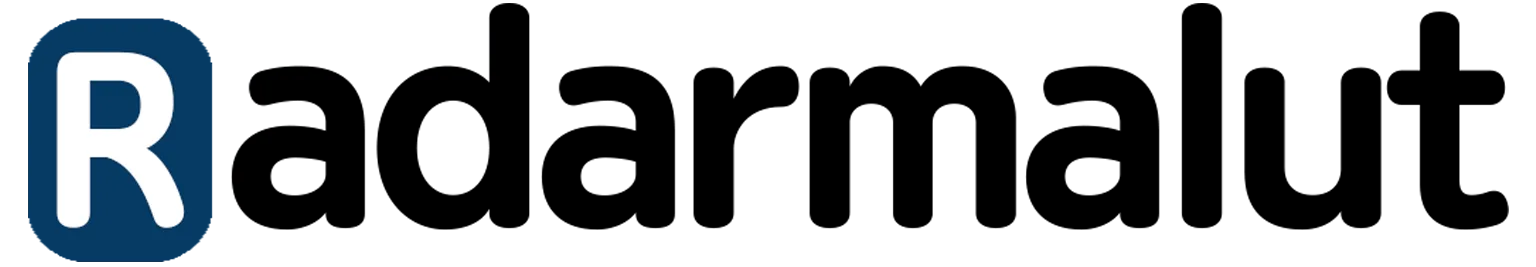Di laut Morotai, tidak semua suara ditujukan untuk didengar dengan telinga. Ada bisikan yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk pembangunan dan belajar mendengar dengan batin.
Bisikan itu datang dari tuna yang berenang jauh melintasi samudra dan dari hiu yang berputar tenang di kedalaman, menjaga keseimbangan laut tanpa pernah meminta pengakuan.
Tuna adalah simbol perjalanan panjang, disiplin dan ketekunan. Ia tidak berenang tanpa arah, tidak bergerak karena tergesa-gesa. Ia mengenal musim, membaca arus dan memahami jarak. Ribuan mil ia tempuh bukan demi ambisi, melainkan demi keberlanjutan hidup.
Dalam bisikannya, tuna mengajarkan bahwa masa depan hanya bisa diraih oleh mereka yang sabar dan teratur, bukan oleh mereka yang rakus dan tergesa. Hiu kerap disalahpahami. Ia ditakuti, dicurigai, bahkan dimusnahkan atas nama rasa aman dan keuntungan.
Padahal, hiu adalah penjaga ekosistem. Ia bukan perusak, melainkan penyeimbang. Tanpa hiu, laut kehilangan struktur, dan kehidupan menjadi timpang. Dalam diamnya, hiu mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ramah di permukaan, tetapi adil dalam perannya.
Morotai tumbuh dan berdenyut di antara dua bisikan itu. Ia membutuhkan ketekunan tuna untuk bergerak maju, dan ketegasan hiu untuk menjaga batas. Namun dalam praktik pembangunan, yang sering terdengar justru suara mesin, proposal, dan angka-angka. Bisikan laut perlahan tenggelam oleh logika investasi jangka pendek.
Selama berabad-abad, masyarakat pesisir Morotai membaca laut tanpa buku dan tanpa gelar. Mereka tahu kapan harus melaut dan kapan harus menepi. Pengetahuan itu bukan mitos, melainkan hasil dialog panjang antara manusia dan alam. Tuna dan hiu bagi mereka bukan sekadar ikan, tetapi penanda etika hidup.
Zaman modern mengubah relasi itu. Laut tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup, melainkan ruang eksploitasi. Kapal-kapal besar datang membawa teknologi dan modal, sering tanpa kepekaan. Tuna dihitung tonasenya, hiu dihitung risikonya, tetapi keseimbangan laut jarang dihitung nilainya.
Di sinilah Morotai diuji. Apakah ia akan menjadi pulau yang mendengar bisikan laut, atau pulau yang tuli oleh gemuruh pembangunan. Pertanyaan ini bukan romantisme, melainkan soal pilihan peradaban.
Bisikan tuna berbicara tentang pentingnya pengetahuan lintas generasi. Laut tidak bisa dikelola dengan naluri sesaat. Ia membutuhkan riset, kebijakan berbasis data, dan kearifan lokal yang saling menguatkan. Pendidikan kelautan menjadi kunci, bukan hanya bagi nelayan, tetapi juga bagi birokrat dan pengambil keputusan.
Sementara itu, bisikan hiu mengingatkan tentang kedaulatan. Laut Morotai bukan ruang kosong yang bisa diperebutkan tanpa batas. Ia adalah wilayah hidup yang harus dijaga dengan hukum, etika dan keberanian politik. Tanpa ketegasan, laut akan menjadi korban dari kompromi yang salah arah.
Dalam kerangka ekonomi biru, tuna adalah komoditas unggulan, tetapi hiu adalah indikator kesehatan ekosistem. Mengorbankan hiu demi keuntungan tuna adalah kesalahan fatal. Alam tidak mengenal transaksi sepihak; ia selalu menuntut keseimbangan.
Morotai masa depan tidak cukup diukur dari volume ekspor atau grafik pertumbuhan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah lautnya masih hidup, atau hanya tersisa sebagai data dalam laporan. Bisikan laut juga mengajarkan kepemimpinan.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu membaca arus seperti tuna dan menjaga batas seperti hiu. Kepemimpinan tanpa visi hanya akan hanyut, sementara kekuasaan tanpa etika akan memangsa dirinya sendiri.
Di desa-desa pesisir, masih ada keyakinan bahwa laut punya ingatan. Ia mencatat siapa yang tamak dan siapa yang tahu batas. Kepercayaan ini mungkin tak tercantum dalam jurnal ilmiah, tetapi sering terbukti dalam kenyataan ekologis.
Modernitas sering datang dengan janji efisiensi, tetapi lupa pada relasi. Laut diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Padahal tanpa relasi yang adil, pembangunan hanya memindahkan kerusakan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bisikan tuna dan hiu adalah kritik sunyi terhadap cara manusia memahami kemajuan. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi menolak keserakahan. Mereka tidak menentang teknologi, tetapi menuntut kebijaksanaan.
Morotai yang dewasa adalah Morotai yang berdamai dengan lautnya. Di mana kebijakan tidak hanya lahir dari ruang rapat, tetapi juga dari pengetahuan nelayan, ilmuwan, dan suara alam itu sendiri.
Di masa itu, laut bukan lagi halaman belakang pembangunan, melainkan halaman depan peradaban. Sekolah mengajarkan etika laut, kampus meneliti arus dan biodiversitas, dan negara berdiri sebagai penjaga, bukan pedagang ruang hidup.
Bisikan tuna menjadi narasi tentang kesabaran dan visi jangka panjang. Bisikan hiu menjadi peringatan tentang batas dan keberanian. Keduanya saling melengkapi, seperti rasio dan nurani dalam kehidupan manusia.
Jika suatu hari Morotai dikenang, semoga bukan hanya karena kekayaan lautnya yang pernah ada, tetapi karena kebijaksanaannya dalam menjaga. Karena ia memilih mendengar bisikan, bukan hanya mengejar suara keuntungan.
Karena itu,, laut tidak meminta manusia untuk menyembahnya. Ia hanya meminta untuk dipahami. Dan siapa pun yang mampu memahami laut, sesungguhnya sedang belajar memahami dirinya sendiri.
Di antara tuna yang terus berenang dan hiu yang setia menjaga, Morotai menemukan cermin masa depannya: sebuah pulau yang besar bukan karena eksploitasi, tetapi karena kebijaksanaan dalam hidup berdampingan dengan alam.
“Peradaban tidak diukur dari seberapa cepat kita mengambil dari alam, melainkan dari seberapa bijak kita menjaga apa yang bukan kita ciptakan.”
***