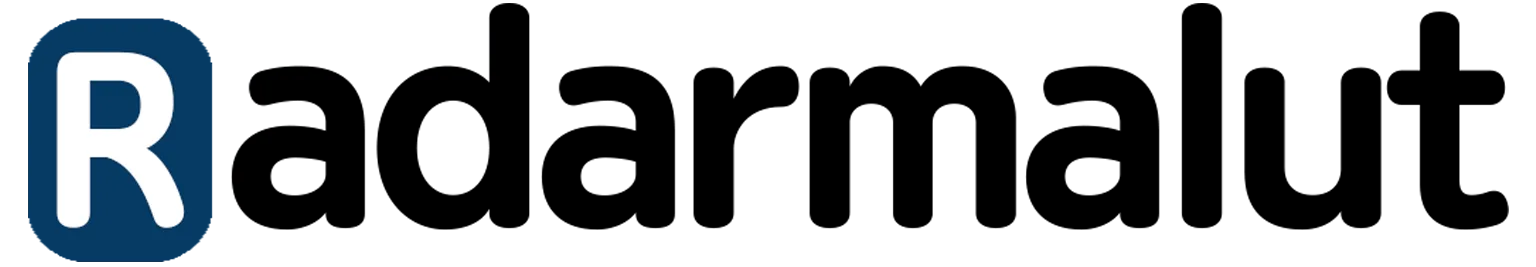Di tengah kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), menjulang sebuah gedung megah. Thingshan Tower namanya. Kehadiran bangunan 23 lantai itu seakan menandai lanscap Teluk Weda sebagai sebuah arena baru perebutan modal dan sumber daya alam. Tentu dengan jangka waktu yang lama.
Sebelumnya, perusahaan lebih dulu mendirikan sebuah hotel mewah di kawasan Tanjung Uli. Hotel 5 lantai itu terdapat sejumlah fasilitas seperti atrium, kolam renang, hingga helipad.
Narasi positif yang diproduksi sejumlah influencer seakan meneguhkan bahwa industri nikel di Halmahera akan terus berdenyut, melahirkan pekerjaan, dan memberi harapan. Padahal di balik kilau kaca dan besi gedung, kita sedang diperlihatkan strategi komunikasi korporasi yang lihai: menutup realitas keras industri dengan fantasi optimistis.
Dalam periklanan, bahasa adalah sarana yang dirancang untuk menegaskan substekstual. Ada banyak teknik verbal yang digunakan para pendengung dalam mewujudkan tujuannya.
Secara umum, narasi periklanan adalah memasukan produk pemikiran ke dalam kesadaran sosial, menciptakan efek dari sebuah nasihat yang datang dari sumber berwenang yang tidak tampak.
Faktanya, setiap kelompok sosial atau sebuah koorporasi dalam merancang bangunan dengan bentuk-bentuk yang khas merupakan indikasi yang gamblang, bahwa bangunan tersebut juga merupakan sistem tanda yang mengacu pada sebuah lingkup makna yang spesifik pada tujuan dari berdirinya bangunan tersebut.
Saya sendiri melihat Thingshan Tower semacam penanda teritorial, yang memungkinkan perusahaan mengakses atau mempertahankan kendali atas sumber daya di seluruh wilayah garapannya. Ini terbukti dengan perluasan kawasan industri yang sudah disahkan dalam RTRW Halmahera Tengah.
Istilah teritorial ini dalam konteks koorporasi tentu memperoleh banyak dukungan, terutama negara yang tak pernah jauh dari kepentingan modal.
Thingshan Tower kemudian menjadi jauh lebih dari sekadar perkantoran. Ia seakan menghadirkan atmosfer modal dan kekuasaan dengan menyodorkan rasa aman dan terlindung dari dunia yang penuh kendaraan, alat berat, kebisingan mesin, hingga polusi.
Lambat laun, gedung tersebut berevolusi menjadi dunia fantasi. Seolah hiruk-pikuk industri yang berbarengan dengan kritik publik atas dampak lingkungan dapat dijedah, bahkan terlindungi.
Dalam lingkungan industri seperti IWIP yang dipertegas dalam kata “Park” yang berarti “Taman”, segalanya serba bersih, mengkilap, ceria, dan penuh optimistis. IWIP didandani dan disederhanakan bentuknya sedemikian rupa untuk menjaga realitas yang sebenarnya sangat mengerikan.
Subteks “Park” atau “Taman” di sebuah kawasan industri pengolahan nikel pada dasarnya adalah pergulatan antara skill dan kerja fisik yang melelahkan, yang hampir semuanya tidak lepas dari kontrol dan pengendalian.
Thingshan Tower kemudian hadir sebagai jeda imajiner. Ia menjadi ruang aman yang terlindung dari kritik publik atas dampak lingkungan. Ia menciptakan dunia fantasi, dimana hiruk-pikuk industri bisa ditanggalkan, diganti dengan citra kemegahan atau “stabilitas” dalam istilah yang dipakai negara.
Seperti yang kita tahu, rumah adalah tempat berlindung dari cuaca dan penganggu. Suku Korowai di Papua membuat rumah di pohon untuk berlindung dari bahaya seperti banjir, binatang buas, serta menghindari roh jahat sekaligus meneguhkan kehidupan sosial-spiritual mereka dengan alam dan komunitas.
Berbeda dengan Thingshan Tower. Ia mencerminkan sebuah tipe persepsi lain yang sama sekali berlawanan dengan bentuk atau tujuan orang-orang Korowai membangun rumah pohon. Sebab, Thingshan Tower tidak tumbuh dari lingkungan alaminya.
Arsitektur dalam sependek pengetahuan saya berarti menerapkan keteraturan pada ruang. Saat mengikuti kegiatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Bali, sopir grab kepada saya menjelaskan bahwa bangunan di Bali umumnya tidak boleh lebih tinggi dari 15 meter–sekitar 4 lantai atau setara tingginya pohon kelapa, kecuali bangunan khusus seperti menara telekomunikasi atau rumah sakit.
Alasannya, kata Bli — sapaan khas masyarakat Bali bagi kakak laki-laki; tujuan dari aturan itu untuk menjaga harmonisasi dengan alam sekaligus kesucian Pura. Hal ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023.
Dari sini dapat dipahami, bahwa kode ruang yang terkait dengan tempat memiliki kekuatan emosional dan spiritual, sekaligus menandakan bahwa revolusi industri merupakan titik balik cara kita melihat apa yang hilang di Halmahera hari ini.
Thingshan Tower, bagi saya, lahir dari logika yang berlawanan. Ia tidak tumbuh dari lingkungan, melainkan dari kapital. Ia menegaskan jarak antara modernitas industri dan tradisi lokal, sekaligus memperlihatkan bagaimana arsitektur bisa menjadi bahasa kekuasaan dan kekayaan.
Pada akhirnya, konfigurasi baru tersebut mendorong adanya batas pemisah antara moderintas dan tradisional. Ini mencerminkan fakta yang sebenarnya, bahwa sesuatu yang kuat menguasai diri kita saat kita mendongak untuk melihat bangunan tinggi.
Melihat Thingshan Tower, kita seakan dibuat merasa kecil dan tidak penting dibanding bangunan tersebut. Bahkan nyaris tidak memberikan kesan keseimbangan bagi penduduk dan lingkungan sekitar, dibanding kekuasaan yang menghuni setiap lantainya.
Di dalam gedung, terdapat struktur arsitektur yang mencerminkan hierarkis sosial. Pekerjaan dan jabatan dengan nilai terendah ada di dasar bangunan, bahkan di luar gedung. Sedangkan para eksekutif seperti dewa-dewa di Gunung Olympus yang berada di lantai atas. Mereka seakan mengenggam dan menentukan arah masa depan industri dan masyarakat Halmahera.
Pada akhirnya, Thingshan Tower bukan hanya arsitektur, melainkan simbol hegemonik. Ia mengatur bagaimana masyarakat melihat masa depan, pekerjaan, bahkan identitas mereka. Ia adalah menara kekuasaan yang berdiri di atas tanah Halmahera.
Ia menegaskan bahwa revolusi industri bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga soal siapa yang berhak menentukan arah hidup banyak orang. Dan setiap kali mendongak, kita diingatkan, bahwa: “kekuasaan selalu memilih berdiri di atas”.
***