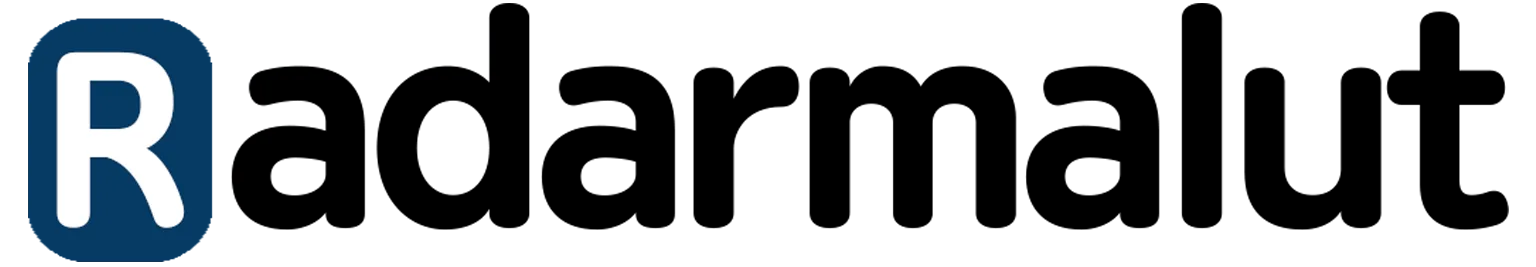Radarmalut.com – Wilayah Maluku Utara merupakan suatu wilayah kebahasaan yang memiliki ciri-ciri yang khas yang tidak terdapat di daerah lain di Nusantara. Sebab itu, tidak mengherankan kalau sejumlah ahli linguistik pernah mengadakan penelitian yang mendalam atas struktur kebahasaan wilayah ini.
Pada umumnya bahasa-bahasa di Nusantara ini tergolong bahasa Austronesia. Keadaan di Maluku Utara pun demikian. Tetapi disamping bahasa-bahasa yang tergolong Austronesia itu terdapat pula bahasa-bahasa yang memillki ciri-ciri yang lain samasekali sehingga disebut bahasa-bahasa Non-Austronesia.
Di Indonesia bahasa-bahasa yang tergolong Non-Austronesia itu lebih banyak terdapat di sekitar Kepala Burung (Irian Jaya), sehingga para ahli bahasa menamakan bahasa Non-Austronesia yang terdapat di Indonesia itu sebagai bahasa Non-Austronesia dari kelompok West Papua Phylum.
Kalau dikaji lebih teliti lagi, maka temyata di antara bahasa-bahasa West Papua Phylum itu terdapat perbedaan-perbedaan yang penting. Pertama adalah jenis bahasa tersebut yang terdapat di kalangan orang-orang Halmahera Utara seperti yang digunakan di Sahu, Galela, Loloda, Tobelo, Pagu, Modole dan Tobaru.
Termasuk di sini adalah bahasa-bahasa di Kepulauan Ternate, Tidore. Kedua adalah bahasa-bahasa Non-Austronesia yang digunakan oleh penduduk pulau Makian Barat yang jelas merupakan suatu variasi tersendiri pula. (Voorhoeve, 1984).
Penduduk Halmahera Timur (Maba, Weda, Patani) teryata menggunakan campuran dari bahasa-bahasa Austronesia dan Non-Austronesia. Keadaan yang khas ini pemah dipelajari oleh Prof. Masinambouw yang menyebutnya sebagai wilayah “konvergensi bahasa” atau wilayah dimana terdapat percampuran antara dua jenis bahasa. (E.M.K. Masinambouw, 1976).
Bahasa yang digunakan penduduk di wilayah Halmahera Timur, seperti di seluruh Maluku, (dan seluruh Indonesia) pada umumnya tergolong bahasa Austronesia. Namun, di masa lampau wilayah Halmahera Timur tergolong dalam wilayah kekuasaan kerajaan Tidore yang penduduknya menggunakan bahasa Non-Austronesia. (Leirissa, 1996).
Nampaknya pengaruh keraton-keraton Maluku itu demikian besarnya sehingga terjadilah percampuran atau perpaduan itu. Bahasa-bahasa Austronesia di Halmahera Timur yang tergolong bahasa-bahasa Austronesian Phylum itu sama dengan bahasa-bahasa yang digunakan di seluruh Indonesia yang oleh para ahli bahasa sering dinamakan bahasa-bahasa Malayo-Polinesia. (Grimes & Grimes, 1984).
Kelompok bahasa terakhir itu bisa dibagi tiga pula, yaitu kelompok Malayo-Polinesia Barat, Tengah dan Timur. Bahasa-bahasa yang termasuk kelompok Malayo-Polinesia Barat yang terdapat di Indonesia bagian barat. Namun, anehnya bahasa Melayu yang digunakan di Maluku Utara sejak paling kurang abad ke-16, termasuk kelompok bahasa Malayo-Polinesia Barat itu.
Malayo-Polinesia Tengah terutama terdapat di Maluku Tengah dan Tenggara, sedangkan bahasa-bahasa Malayo-Polinesia Timur terdapat di Halmahera Selatan dan Irian Barat serta Oseania.
Keadaan menjadi lebih rumit lagi, karena sekalipun kelompok bahasa Malayo-Polinesia Tengah terutama terdapat di Maluku Tengah dan Tenggara, namun di Maluku Utara terdapat beberapa pulau dimana bahasanya termasuk dalam kelompok ini pula.
Seperti di Kepulauan Sula, Mangole, Taliabu, dan di Pulau Bacan. Sedangkan yang termasuk bahasa Malayo-Polinesia Timur yang terdapat di Halmahera Selatan itu dapat dibagi pula antara bahasa-bahasa Halmahera Barat Daya (Gebe dan Makian Timur, Weda dan Sawai), Halmahera Tenggara (Patani, Maba, Buli) dan di Pulau Gebe. (Grimes & Grimes, Zoe.cit.).
Bahasa Melayu
Seperti dikemukakan di atas, selain bahasa-bahasa yang tergolong rumpun bahasa Non-Austronesia, di Maluku Utara terdapat pula penutur bahasa Austronesia (Malayo-Polinesia). Para penutur bahasa ini justru terdapat di wilayah-wilayah yang bukan menjadi inti kerajaan-kerajaan besar (Temate dan Tidore), misal Kepulauan Banggai, Kepulauan Sula, Pulau Bacan, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, dan Pulau Gebe.
Namun, suatu hal yang menarik pula bahwa bahasa Melayu juga digunakan di kedaton-kedaton untuk berinteraksi dengan dunia luar. VOC jelas menggunakan bahasa ini dalam berkomunikasi dengan para sultan, seperti yang bisa dibuktikan dalam dokumen-dokumennya yang masih tersimpan di Arsip Nasional R.I. Jakarta.
Biasanya korespondensi antara pihak kedaton dan pihak VOC dilakukan dalam bahasa Melayu serta aksara Arab Gundul atau Jawi. Untuk menerjemahkan surat-surat itu, atau untuk menulis surat balasan VOC mempekerjakan sejumlah translatuer (penerjemah) yang biasanya berasal dari kaum pedagang asing yang telah bermukim lama atau bergenerasi di Ternate. Dapat diperkirakan bahwa dalam komunikasi lisan pun digunakan bahasa Melayu.
Keadaan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya budaya pedagang tersebut di atas dalam kedaton-kedaton di Maluku Utara. Tetapi di antara kedaton-kedaton itu, Ternate-lah yang paling banyak menerima unsur-unsur tersebut.
Dalam mengkisahkan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, Valentijn menemukan kenyataan bahwa sastra pesisir yang berasal dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara juga terdapat di Temate. (Valentijn, Jilid I, bagian A, 1734).
Namun kenyataan bahwa bahasa lokal (Non-Austronesia) samasekali tidak terdesak dibuktikan dalam sebuah kitab sejarah yang ditulis oleh Naidah (orang Temate) di abad ke-19. (Van der Crab, 1878). Hikayat Ternate tersebut jelas mengikuti tradisi penulisan sejarah pesisiran yang mekar di zaman Kurun Niaga tersebut di atas.
Dalam hal gaya dan isinya jelas nampak bahwa Naidah berupaya keras untuk mengikuti pola yang telah lazim itu. Namun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ternate, walau diberi terjemahan bahasa Melayunya. Dualisme ini nampaknya merupakan pola utama dalam kedaton Ternate sejak masa VOC, bahkan mungkin juga sebelum itu.
Budaya lokal mengikat kedaton dan warganya, tetapi budaya pesisiran mengikat seluruh wilayah kerajaan dengan wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Budaya lokal mewujudkan Maluku Kie Raha, sedangkan budaya pesisiran mengikat Maluku Kie Raha dengan bagian-bagian lainnya dari dunia sekitarnya.
Dalam abad ke-19 kedua unsur itu nampaknya, telah memadu secara serasi dan menjadi ciri khas dari budaya kedaton, paling kurang di Ternate.
Maluku Kie Raha
Perpaduan antara unsur-unsur budaya lokal dan budaya pesisiran yang datang dari luar melalui perdagangan itu nampak sangat jelas dalam budaya politik kedaton-kedaton di Maluku Utara, terutama di Ternate.
Budaya politik di Maluku Kie Raha paling jelas terekam dalam mitos-mitos tentang asal-usul raja-raja Maluku yang dipertahankan pihak-pihak kedaton. Tetapi selain itu, dalam kehidupan sehari-hari terdapat pandangan hidup serupa sehingga mewujudkan suatu masyarakat Maluku Kie Raha yang terintegrasi.
Sebagai mitos mengenai asal-usul keempat raja di Maluku Utara mitos itu bisa disebut sebagai Maluku Kie Raha, atau Maluku empat gunung yang menunjukkan keempat kerajaan itu (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo). Salah satu versi dari mitos itu yang berasal dari abad ke-17 menceritakan mengenai seorang yang menemukan empat buah telur naga di bawah serumpun bambu.
Lalu terdengar suara bahwa orang itu harus memelihara telur-telur itu dengan baik hingga menetas. Ketika menetas maka muncullah empat pria yang gagah yang kemudian menjadi raja di Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. (Valentijn, Jilid I, 1724).
Hikayat Ternate dari Naidah yang ditulis dalam abad ke-19 itu membuktikan bahwa mitos-mitos asal-usul yang berasal dari budaya lokal itu telah terintegrasi dengan sempurna dengan budaya pesisiran yang muncul berabad-abad sebelumnya.
Versi Naidah mengemukakan, pada suatu ketika (tidak dikemukakan kapan) seorang ulama dari timur yang bernama Jafar Sadek datang ke Ternate melalui Jawa. Di Ternate ulama itu menikah dengan seorang bidadari, Nurus Safa, dan menurunkan raja-raja Maluku. Lengkapnya versi itu adalah sebagai berikut (dikutip dari Van Fraassen 1978, II: 11–12):
Pernah seorang Arab datang ke Temate; namanya Jafar Sadek. Ia memanjat gunung dan melihat tujuh bidadari yang sedang mandi di sebuah danau. Ia berhasil menyembunyikan sayap dari salah seorang bidadari itu.
Ketika para bidadari itu selesai mandi dan hendak terbang kembali ke kayangan, bidadari yang bungsu tidak dapat menemukan sayapnya sehingga terpaksa tinggal di bumi. Bidadari yang bemama Nurus Safa itu lalu hidup bersama Jafar Sadek.
Nurus Safa dan Jafar Sadek mendapat tiga orang putra. Putra tertua bemama Buka, yang kedua bernama Darajat, dan yang ketiga bernama Sahadat. Kemudian, ketika Nurus Safa sedang memandikan putranya yang termuda, ia melihat sayapnya yang disembunyikan suaminya itu tersangkut di atap.
Ia mengambil sayapnya dan sampai tiga kali ia mencoba terbang. Tetapi tidak berhasil. Ia mendengar putranya yang paling bungsu itu menangis dan untuk terakhir kali ia kembali lagi. Ia memeras susunya dalam sebuah mangkok dan berkata pada putranya yang sulung.
“Kalau si bungsu menangis, berikan susu ini. Dan bila ayahmu kembali, katakan padanya bahwa aku telah kembali ke tempat asalku.” Setelah itu ia terbang menghilang. Ketika Jafar Sadek pulang dan mendengar pesan dari istrinya itu, ia menangis.
Seekor elang (guheba) mendengar tangisannya dan bertanya padanya mengapa ia menangis. Setelah Jafar Sadek menceritakan mengapa ia sedih, maka elang itu menawarkan padanya untuk membawanya ke kayangan dengan menaiki punggungnya untuk mencari istrinya.
Dengan bantuan elang itu Jafar Sadek tiba di kayangan. Ketika penguasa kayangan bertanya padanya apa yang dicarinya, Jafar Sadek menjawab: “Istriku; yang adalah putrimu.” Penguasa kayangan itu lalu memanggil ketujuh putrinya yang wajahnya sama semua.
Dikatakan pada Jafar Sadek, bahwa bila ia bisa menunjuk mana istrinya, maka ia boleh membawanya pulang. Namun kalau gagal, ia akan dibunuh. Ketika Jafar Sadek sedang putus asa, datanglah seekor lalat biru (gufu sang) yang mengatakan bisa menolong Jafar Sadek bila diberi imbalan.
Jafar Sadek menjawab, bahwa apa saja yang bau tidak enak di bumi akan menjadi miliknya. Lalat itu menerima usul itu, dan berhasil melakukan apa yang ia janji karena Nurus Safa pernah menyusui anak sehingga bau pentilnya berbeda dengan para bidadari lainnya.
Lalat itu berkata pada Jafar Sadek : “Perhatikan baik-baik, aku akan mengelilingi putri-putri itu dan yang saya singgahi adalah istrimu“. Dengan demikian Jafar Sadek berhasil menunjuk istrinya, sehingga penguasa kayangan itu sendiri yang mengawinkan mereka.
Di kayangan lahirlah putra keempat yang paling bungsu yang bemama Masyhur-ma-lamo (yang paling masyhur), yang berbeda dengan ketiga saudaranya, lahir dari perkawinan yang sah. Setelah beberapa lama berdiam di kayangan, Jafar Sadek ingin kembali ke bumi dengan istri dan anaknya itu.
Penguasa kayangan setuju, namun sebelum mereka turun ke bumi Masyur-ma-lamo tidak berhenti menangis. Penguasa kayangan itu lalu berkata : “Mungkin ia menginginkan kopiahku.” Ketika kopiah ltu dipakaikan pada anak itu, ia berhenti menangis.
Dengan demikian mereka kembali ke bumi, dengan Masyhur-ma-lamo memakai kopiah kakeknya dari kayangan. Ketika Jafar Sadek dan Nurus Safa tiba kembali di bumi dan berjumpa kembali dengan ketiga putra mereka yang ditinggalkan itu, maka Nurus Safa memberi tempat duduk kepada setiap putra itu.
Putra sulung, Buka, mendapat batang kayu (age) sebagai tempat duduknya. Ia berangkat ke Makian dan menjadi cikal-bakal dari raja-raja Bacan. Putra kedua mendapat kayu apung (ginoti) sebagai tempat duduknya. Ia bertolak ke Moti dan menjadi cikal-bakal dari raja-raja Jailolo.
Putra ketiga, Sahadat, mendapat batu (mari.) sebagai tempat duduknya. Ia bertolak ke Tidore dan menjadi cikal-bakal dari raja-raja Tidore. Putra keempat yang bungsu, Masyur-ma-lamo, mendapat kursi sebagai tempat duduk dan menjadi cikal-bakal raja-raja Ternate. Kopiah dari Kakeknya di langit menjadi mahkotanya.
Mitos yang terjalin dalam Hikayat dari Naidah itu mengacu pada beberapa hal yang memang merupakan kenyataan, sekalipun kronologinya tidak ditegaskan. Memang diketahui dari sumber-sumber Portugis, bahwa sejak abad ke-15 telah terdapat empat kerajaan di Maluku, masing-masing di sebuah pulau dengan nama yang sama. (Van Fraassen 1987, II:19-21).
Namun baik sumber-sumber Portugis, maupun sumber-sumber Belanda tidak membentangkan sistem status yang berlaku di antara kerajaan-kerajaan Maluku itu. Hal ini justru menjadi pokok masalah dalam Hikayat Ternate. (Penekanan mengenai hal ini mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam abad ke-19 masalah sistem status itu telah banyak dilupakan orang).
Selain memiliki tempat duduk (dodego) masing-masing, menurut Hikayat Ternate, keempat raja pertama di Maluku itu juga memiliki gelar (ronga) masing-masing. Buka, raja Bacan, bergelar Dehe ma-kolano (Raja Ujung Tanjung; kolano = raja), putra kedua, Darajat, bergelar Jiko ma-kolano (Raja Teluk), putra ketiga, Sahadat, bergelar Kie ma-kolano (Raja Gunung), dan yang keempat, Masyur-ma-lamo, bergelar Alam ma-kolano (Raja Alam).
Asal-usul yang sama itu, sekalipun derajat berbeda, menunjukkan bahwa antara keempat kerajaan itu terdapat semacam federasi. Dalam Hikayat Ternate dikisahkan bahwa pada saat-saat tertentu keempat raja itu berkumpul di suatu tempat (biasanya Pulau Moti), untuk menentukan struktur kekuasaan federasi itu.
Salah satu diantara mereka dipilih menjadi primus inter paris yang berhak memakai umbul-umbul ketiga raja lain yang masing-masing memiliki warna sendiri, disamping umbul-umbulnya sendiri sehingga melambangkan federasi itu.
Salah satu pertemuan itu terjadi sekitar pertengahan abad ke-14. Pada saat itulah Ternate mendapat kehormatan menjadi primus inter paris. Nampaknya mitos Maluku Kie Raha yang dikemukakan Naidah tersebut di atas menunjuk pada peristiwa itu. Kedudukan Ternate itu nampaknya berlangsung hingga abad ke-1 7, karena seperti dikemukakan di atas, ketika Belanda tiba di sana Sultan Ternate menyandang gelar Kolano Maluku.
Sekalipun pandangan dunia Maluku Kie Raha tersebut di atas telah menjadi pegangan yang menentukan dalam pergaulan antara kerajaan-kerajaan di Maluku sejak abad ke18, dan dengan demikian sesungguhnya telah menjadi sebuah mitos seperti yang diungkapkan dalam Hikayat Ternate.
Namun pengaturan masyarakat pada taraf yang lebih rendah tetap mengikuti pandangan itu. Hal ini dibuktikan oleh Dr. Chris van Fraassen yang telah dikutip beberapa kali di atas.
Dalam disertasinya yang khusus membicarakan Pulau Ternate dimana prinsip organisasi sosial yang didasarkan pada prinsip genealogis-teritorial yang disebut soa (= bagian) itu dikatakan bahwa “organisasi soa berkaitan erat dengan organisasi sosiopolitik dari kesultanan”. Keadaan ini juga terdapat di pulau Tidore. (Leirissa, 1996).
***