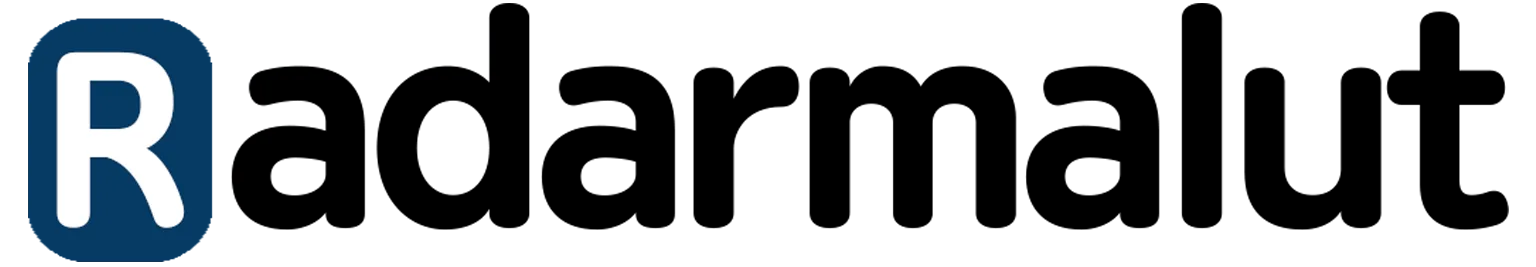Tulisan Bang asghar (Asghar Saleh) berjudul “Tidore dan Titik Nol” adalah karya yang memadukan narasi sejarah, kritik politik, dan pembelaan identitas lokal dengan penuh gaya dan emosi.
Ia menyuguhkan catatan panjang tentang proses pemekaran Maluku Utara, terpilihnya Sofifi sebagai ibu kota, serta relasi timpang antara Tidore dan negara. Secara pribadi saya jatuh cinta pada kekuatan naratif tulisan bang asghar.
Terlebih lagi, yang kuat dalam tulisan ini ialah:–pertama, menyuarakan suara lokal yang kerap terabaikan. Kedua, Menawarkan narasi sejarah alternatif dari sudut pandang subjek lokal yaitu Tidore.
Ketiga, menggambarkan betapa kompleksnya proses pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap identitas, politik, dan sejarah.
Namun, sebagaimana karya yang sarat emosi dan memori, tulisan ini menyimpan sejumlah celah logika dan problem argumen yang layak dikritisi secara jernih tanpa niat setitik pun untuk tidak menghormati penulisnya. Just about logic!
Bang Asghar memulai dengan sentuhan sastrawi, membandingkan riuh debat Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan ledakan rudal di Timur Tengah. Analogi itu mengisyaratkan bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan juga arena perang kepentingan.
Sayangnya, sejak awal narasi ini terjebak dalam logika emosional yang menempatkan Tidore sebagai korban abadi dari keputusan negara yang dianggap manipulatif. Pusat argumentasi Bang Asghar bahwa Tidore, dengan warisan sejarah dan kebesaran politiknya, layak mendapatkan perlakuan istimewa.
Ia menyebut bahwa Tidore telah menyerahkan kedaulatannya kepada republik tanpa syarat, dan sebagai balasannya, ia kini dimiskinkan secara sengaja. Tidore digambarkan sebagai “ibu” yang terus diamputasi, baik dari sisi wilayah, fiskal, maupun kehormatan sejarah.
Kalimat semacam ini menyentuh hati, tapi dalam logika kebijakan, ini disebut argumentum ad misericordiam–logika yang meminta pembenaran karena penderitaan masa lalu, bukan karena argumen rasional.
Kesalahan logika lain tampak dalam narasi tentang proses terpilihnya Sofifi sebagai ibu kota. Penulis menyebut bahwa nama Sofifi dimasukkan secara tiba-tiba lewat lobi elite yang ditopang dana besar dari PT Antam.
Ini seolah membatalkan legitimasi pemilihan Sofifi, padahal proses legislasi memang kerap melibatkan dinamika politik, negosiasi, dan lobi. Menyederhanakan itu sebagai manipulasi adalah bentuk post hoc ergo propter hoc (post hoc fallacy), yaitu menyimpulkan hubungan sebab-akibat hanya karena dua peristiwa terjadi berurutan.
Penulis juga menampilkan pendapat sejumlah akademisi dan lembaga yang menolak kelayakan Sofifi sebagai ibu kota–mulai dari Unhas, ITB, hingga UGM. Namun semua kutipan ini mendukung narasi penolakan, tanpa satupun data atau pandangan yang seimbang.
Ini adalah cherry picking, yakni memilih data yang hanya memperkuat argumen sendiri dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Padahal, tak ada wilayah yang ideal secara absolut.
Kota-kota besar seperti Palangka Raya pun pernah dikritik karena tanah gambutnya, namun tetap bisa tumbuh melalui rekayasa tata ruang dan komitmen pembangunan jangka panjang.
Bang Asghar membangun narasi bahwa Sofifi hanyalah nama tanpa entitas, tidak layak secara teknis, dan bahkan “imajinasi politik”:– “Sofifi, nama kelurahan dengan 3000an penduduk diglorifikasikan sebagai sebuah kota. Semua hanya imajinasi politik.”
Ini adalah bentuk Strawman argument terhadap Sofifi, karena mengabaikan kenyataan bahwa UU telah menetapkan Sofifi sebagai ibukota sejak 1999. Penilaian kelayakan administratif tidak cukup hanya berdasarkan jumlah penduduk atau bentuk kelurahan, tapi juga potensi pengembangan dan penataan ruang jangka panjang.
Menyebutnya “imajinasi” menihilkan semua tahapan perencanaan dan realisasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Yang paling problematik adalah klaim bahwa pemekaran Sofifi akan “membunuh” Tidore.
Ini adalah slippery slope fallacy–yakni menyimpulkan bahwa satu keputusan akan membawa pada kehancuran total tanpa bukti kausal yang kuat. Tidak ada simulasi fiskal atau skenario teknis yang menunjukkan bahwa pendapatan Tidore akan kolaps jika empat kecamatannya dimekarkan.
Justru ini bisa menjadi peluang untuk desain fiskal baru yang berbasis subsidi silang, kompensasi pusat, atau penguatan Badan Layanan Umum Daerah. Di akhir tulisan, Bang Asghar menyodorkan alternatif: menjadikan Sofifi sebagai “Daerah Khusus Ibu Kota” atau membentuk Badan Otorita.
Gagasan ini menarik, namun ia tidak menguraikan dasar hukumnya, presedennya. Tanpa argumen kelembagaan yang kuat, usulan ini hanya menjadi seruan moral yang tidak operasional.
Jika betul ingin memperjuangkan solusi, maka pendekatan teknokratik harus berjalan bersama semangat historis, tidak cukup hanya mengandalkan glorifikasi masa lalu. Hal yang juga tak kalah penting adalah cara penulis menarasikan sejarah Tidore sebagai pembenar posisi tawar politik.
Ia menyebut perlawanan Sultan Nuku, peran Sultan Zainal Abidin dalam integrasi Irian Barat, serta status Tidore sebagai kekuatan maritim yang tak pernah terjajah. Narasi ini valid secara sejarah, namun perlu disadari bahwa kebijakan pemerintahan modern tidaklah bertumpu pada silsilah kerajaan atau simbol kejayaan masa lalu.
Negara Indonesia lahir dari kesepakatan politik yang memisahkan identitas adat dan struktur administrasi. Menuntut hak fiskal dan wilayah atas dasar memori kejayaan adalah bentuk anachronism–memaksakan masa lalu ke dalam logika masa kini.
Bang Asghar memang berhasil menyusun narasi yang menggugah, namun justru karena itulah tulisan ini perlu dibaca ulang dengan skeptisisme sehat. Sejarah memang penting sebagai cermin, tetapi kebijakan publik harus ditentukan oleh keadilan prosedural, efektivitas teknis, dan visi ke depan.
Bukan oleh luka kolektif yang terus diulang. Tidore tidak sedang menuju titik nol. Ia sedang berjuang merebut tempatnya dalam lanskap baru Indonesia, bukan dengan air mata masa lalu, tetapi dengan keberanian menata masa depan bersama.
Terakhir, tulisan ini menurut saya bernilai secara sosiologis dan emosional, tetapi lemah secara logika dan metodologi kebijakan publik. Ia condong menjadi narasi advokatif ketimbang evaluasi objektif atas pilihan pemekaran dan tata ruang.
***
—