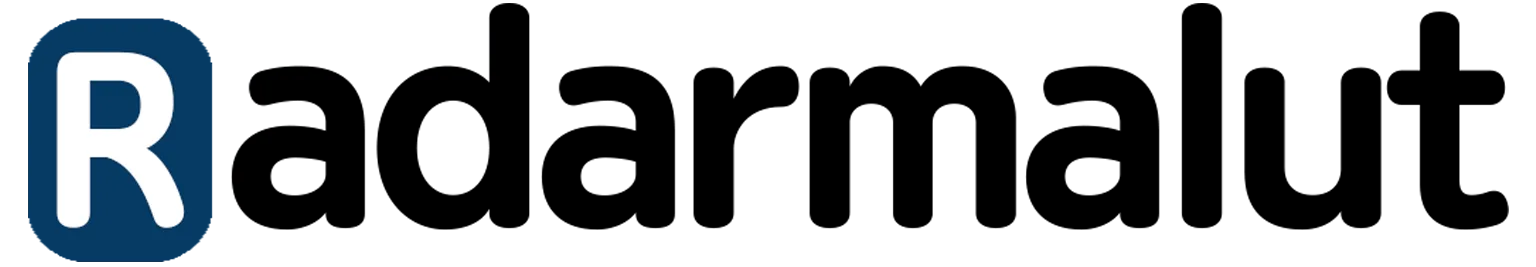Sofifi malam itu tampak berbeda. Gemerlap lampu panggung menyorot ke langit, memantul di wajah ribuan warga yang berkumpul di lapangan luas–dulu katanya padang rumput dan rawa.
Sekarang, di bawah langit yang masih menyisakan aroma hujan, seorang perempuan berdiri di atas panggung megah, tersenyum, lalu berkata dengan logat khas Maluku Utara.
“Sofifi so terang belum? So rame belum? So model kota belum? mudah-mudahan ini menjadi langkah awal.”
Itulah Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, dalam sambutan perayaan HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara. Ucapan pembukanya sederhana, tetapi sarat makna.
Ia sedang berbicara bukan hanya soal kota yang mulai terang, tetapi juga tentang semangat baru untuk menyalakan cahaya di wilayah timur Indonesia–cahaya pembangunan, keadilan, dan kemanusiaan.
Bu Sherly menyadari, panggung megah malam itu ‘belum maksimal’. Ia mengaku hujan tiga minggu berturut-turut membuat banyak persiapan tidak berjalan sempurna.
Tapi di balik pengakuan jujur itu, tersimpan filosofi penting: bahwa pembangunan bukan sulapan, tapi proses yang berpeluh. Bahwa membangun Sofifi bukan soal bimsalabim, melainkan kesabaran dan kerja yang berkelanjutan.
“Ini kan tadinya padang rumput, rawa, benar tidak? bimsalabim, jadilah panggung seperti ini. Bagus ka tarada?” ujarnya disambut tawa dan tepuk tangan warga.
Sofifi dan simbol harapan baru
Sofifi sejak lama menjadi paradoks: ibu kota provinsi yang belum seperti ibu kota. Dalam banyak tahun, Sofifi lebih mirip desa besar daripada kota administratif yang menggambarkan wajah kemajuan.
Minimnya infrastruktur, sulitnya akses transportasi, fasilitas publik yang terbatas, hingga lemahnya daya dukung ekonomi menjadikan Sofifi lambang keterlambatan pembangunan kawasan timur.
Namun, Bu Sherly tampak paham bahwa untuk menyalakan kembali semangat pembangunan, ia perlu memulainya dengan simbol-simbol perubahan. Panggung besar, taman kota, jalan untuk olahraga pagi dan sore, gedung kesenian, dan bahkan miniatur empat kesultanan: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.
Bukan sekadar proyek estetika. Itu adalah penanda psikologis bagi masyarakat Maluku Utara bahwa pusat pemerintahan mereka sedang bergerak menuju peradaban yang lebih baik.
“Sofifi akan menjadi kota sebagaimana ibu kota seharusnya. Dan akan menjadi pariwisata, budaya, dan akan ada acara seperti ini setiap bulan… Kita akan bikin pesta pora alam Indonesia Timur, ya. Bertahap, tapi kita bergerak ke depan,” katanya penuh semangat.
Di balik kata ‘bertahap tapi bergerak ke depan’, ada filosofi penting: Bu Sherly tidak menjanjikan keajaiban, tapi mengajak bergerak bersama. Ia membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengundang semua pihak berkontribusi.
Gaya kepemimpinan seperti ini–partisipatif, terbuka, dan berbasis kolaborasi, menjadi nafas baru di tengah kultur politik lokal yang seringkali hirarkis dan elitis.
Bu Sherly Tjoanda bukan figur politik biasa. Ia seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, dan seorang minoritas di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Namun, keberaniannya berdiri di panggung tertinggi Maluku Utara membuktikan bahwa politik bisa menjadi ruang penyembuhan, bukan sekadar perebutan kekuasaan.
Dalam pidatonya, Bu Sherly mengenang mendiang suaminya, Beny Laos, yang meninggal dalam kecelakaan perahu cepat di Pulau Taliabu pada Oktober 2024. Kisah itu menyentuh publik.
Ia menceritakan bagaimana mereka kesulitan mendapatkan pertolongan medis karena fasilitas kesehatan minim, sinyal telekomunikasi buruk, dan listrik tak tersedia.
“Mereka berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Nyawa seakan-akan pergi karena fasilitas kesehatan yang kurang baik.”
Dari tragedi pribadi itulah ia menemukan panggilan untuk memimpin dengan hati. “Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Tidak ada apa pun yang terjadi di muka bumi tanpa seizinmu. Berikanlah saya hikmah untuk menegerti.”
Kutipan ini menggetarkan, bukan hanya karena kejujuran spiritualnya, tapi karena ia menyadari penderitaan pribadi sebagai cermin penderitaan rakyatnya. Ia kehilangan orang yang dicintainya di tempat yang sama di mana banyak warga kehilangan harapan karena ketimpangan pembangunan.
Dari situ, kepemimpinannya menjadi sangat eksistensial: ia tidak sekadar bekerja untuk proyek, tetapi untuk menebus kehilangan dan menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakatnya.
Dalam satu bagian pidatonya, Bu Sherly menegaskan kesadarannya yang mendalam akan keterbatasan manusia. “Sehebat apa pun, sekuat apa pun, setinggi apa pun jabatannya, ketika waktunya checkout dia akan checkout. Ketika tugasnya dia di dunia telah selesai, dia akan selesai.”
Pernyataan itu sederhana tapi penuh kesadaran spiritual. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah sementara. Dalam konteks politik lokal yang sering diwarnai patronase, konflik elit, dan kepentingan pribadi, kalimat ini seperti tamparan lembut. Ia menolak politik balas dendam.
“Saya tidak mau melakukan politik balas dendam, saya merangkul semua.” Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai politik dari hati–sebuah cara memimpin yang mengutamakan rasa, nilai kemanusiaan, dan kolaborasi.
Tema “Kita membangun dengan hati, inovasi, dan kolaborasi” yang diusung dalam HUT ke-26 Maluku Utara, sejatinya merepresentasikan filosofi kepemimpinan semacam ini: pembangunan sejati lahir dari hati yang bersih, pikiran yang terbuka, dan niat untuk menyejahterakan rakyat.
Dalam delapan bulan kepemimpinannya, Bu Sherly menunjukkan hasil konkret. Ia menggratiskan layanan kesehatan dan pendidikan, membantu renovasi rumah warga, serta menata Sofifi agar lebih terang dan hidup.
Program-program ini, meskipun sederhana, memiliki efek sosial yang besar. Di tengah angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 32%. Tertinggi di Indonesia, ketimpangan masih tinggi.
Sektor pertambangan, terutama nikel, menyumbang angka besar tetapi tidak banyak menetes ke masyarakat bawah. Bu Sherly tampaknya memahami paradoks ini. Ia tidak terjebak pada angka pertumbuhan, tapi berbicara tentang makna kesejahteraan yang sesungguhnya.
“Tanah ini sangat kaya, tanah raja-raja. tapi, kita belum kaya.” Kalimat itu menohok. Ia sadar bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat.
Di Maluku Utara, perusahaan besar datang dan pergi, tapi desa-desa di sekitar tambang tetap miskin. Jalan rusak, air bersih sulit, sekolah masih kurang, rumah banyak yang berdinding kayu dan beratap rumbia.
“Tidak ada boleh lagi negara yang kaya ini rumahnya masih kayu, atapnya masih rumbai, air tidak ada, anak tidak bisa sekolah, itu tidak boleh lagi terjadi.”
Bu Sherly menempatkan pembangunan sebagai proyek moral, bukan sekadar target ekonomi. Ia ingin mengembalikan makna pembangunan kepada rakyat. Bahwa kesejahteraan tidak hanya tentang uang, tapi juga martabat, akses, dan kesempatan untuk hidup layak.
Dalam banyak kesempatan, Bu Sherly menyebut bahwa ia hanya melanjutkan mimpi mendiang suaminya, Beny Laos. Seorang pengusaha dan politisi yang dikenal visioner dalam membangun Maluku Utara.
“Saya di sini adalah wujud, bentuk nyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, dari mimpi putra terbaik Maluku Utara yang bernama Beny Laos… mimpinya ditaruh di hati saya melanjutkan mimpi seorang Beny Laos.”
Di sini tampak bagaimana politik menjadi ruang transendental bagi Bu Sherly. Ia menjadikan kehilangan sebagai energi. Ia menjadikan cinta sebagai visi pembangunan. Gaya kepemimpinan seperti ini langkah di tengah politik Indonesia yang sering pragmatis dan transaksional.
Bu Sherly tak hanya mengandalkan wibawa formal sebagai gubernur, tetapi juga menghidupkan politik empati. Politik yang mengakui luka rakyat, mengajarkan pentingnya saling percaya, dan membangun optimisme bersama.
Ia sadar, masa jabatannya hanya lima tahun. Tapi ia ingin memastikan mimpi Maluku Utara yang kuat, cerdas, sejahtera, dan bahagia akan terus hidup di hati warganya.
Bu Sherly menyebut ASN sebagai ‘mesin’ pembangunan, bukan alat politik. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu, tanpa sekat partai, agama, atau latar belakang sosial. Kepemimpinan semacam ini mengingatkan pada prinsip governance through togetherness, memerintah dengan kebersamaan.
Dalam konteks Indonesia Timur yang sering dicap tertinggal, pendekatan seperti ini sangat penting. Pembangunan di kawasan timur selalu menghadapi persoalan klasik: infrastruktur yang minim, biaya logistik tinggi, dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia.
Namun, akar masalah sesungguhnya sering ada pada ketidakseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dengan hati. Kebijakan pembangunan sering top-down, berbasis proyek jangka pendek, dan gagal membaca kebutuhan sosial yang sesungguhnya.
Padahal, seperti yang ditunjukkan Bu Sherly, pembangunan bisa dimulai dari hal sederhana: menata kota agar terang, menyediakan ruang publik untuk interaksi warga, memberi panggung bagi seniman lokal, dan memastikan layanan dasar bisa dinikmati tanpa diskriminasi.
“Saya tidak suka cerita, saya akan cerita nanti kalau itu terjadi,” ucapnya dengan nada merendah. Kalimat ini menggambarkan gaya kerja yang realistis dan anti-pencitraan.
Sofifi dan mimpi Indonesia Timur
Sofifi mungkin kecil di peta Indonesia, tapi ia kini menjadi simbol harapan bagi kawasan timur. Di tengah ketimpangan pembangunan nasional–di mana Jawa selalu dominan. Sofifi menjadi pernyataan bahwa daerah pun bisa maju ketika dipimpin dengan visi dan hati.
Bu Sherly memahami betul makna simbolik itu. Ia tak ingin Sofifi sekadar administratif, tetapi menjadi etalase kemajuan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif Maluku Utara. Ia ingin ada perputaran uang dari event lokal, ruang bagi UMKM, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Dari megahnya perayaan HUT Maluku Utara yang ke-26 tidak hanya sebagai formalitas, tapi bagaimana ekonomi juga ikut tumbuh, UMKM jalan, ada perputaran uang, ada ruang bagi pelaku industri kreatif.”
Di situ, ia memperlihatkan pemahaman modern tentang ekonomi daerah. Pembangunan tak bisa hanya bergantung pada tambang dan infrastruktur, namun juga pada industri kreatif dan partisipasi warga.
Tema HUT Maluku Utara tahun ini ‘Membangun dengan hati, inovasi, dan kolaborasi’. Tak sekadar slogan, ia menjadi refleksi politik yang kuat di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemimpin. Dalam konteks nasional, tema ini terasa kontras dengan politik yang makin transaksional menjelang Pemilu.
Kepemimpinan dari hati bukan berarti lembek, tapi berani mengambil keputusan yang manusiawi. Inovasi tak hanya teknologi, tapi cara baru dalam mendengar dan melibatkan rakyat. Kolaborasi bukan sekadar jargon, tapi praktik menyatukan perbedaan untuk tujuan yang sama: kesejahteraan bersama.
Di tangan Bu Sherly, tiga kata ini–hati, inovasi, kolaborasi, telah menjadi fondasi gaya memimpin baru di timur Indonesia. Ia menunjukkan pembangunan tak akan berarti tanpa hati yang terlibat di dalamnya.
“Doakan saya amanah, satukan hati, percaya bahwa niat saya hanya satu, memastikan Maluku Utara sejahtera dalam arti yang sesungguhnya.”
Malam semakin larut, Sofifi masih terang. Lampu-lampu dari panggung memantul di wajah warga yang belum ingin pulang. Mereka menyaksikan bukan hanya pesta ulang tahun provinsi, tetapi juga lahirnya semangat baru.
Sofifi kini punya cerita. Tentang seorang perempuan yang menyalakan terang dari luka. Tentang Maluku Utara yang belajar membangun dengan hati. Tentang Indonesia Timur yang sedang bangkit, perlahan tapi pasti, menuju terang.
Karena seperti yang diyakini Bu Sherly,”Bertahap, tapi kita bergerak ke depan.” Dan mungkin, di situlah letak sejati dari pembangunan yang manusiawi: ia tumbuh bukan dari ambisi, tetapi dari cinta.
***
—
Abdur Rahmad Alumnus Pesantren Nurul Jadid Paiton, Pelayan Kader