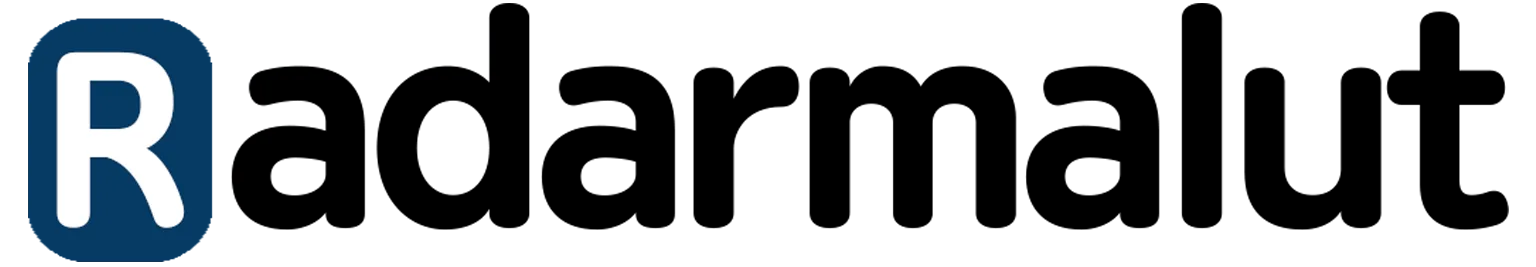Sejarah filsafat adalah tentang pertarungan gagasan. Di setiap zaman, selalu muncul dua kutub–mereka yang menganggap filsafat sebagai jalan menuju kebenaran dan integritas, serta mereka yang menggunakannya untuk kepentingan praktis, bahkan politis.
Di Yunani Kuno, ketegangan itu hadir antara Socrates dan Gorgias, sedangkan di abad pencerahan, perseteruan intelektual mengkristal dalam tokoh Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Keempatnya, meskipun berbeda zaman, berbagi gelanggang yang sama.
Perebutan makna filsafat, apakah ia harus menjadi suara hati nurani, ataukah sekadar alat canggih retorika untuk mengendalikan khalayak. Socrates, sang filsuf yang hidup dalam kesederhanaan, tidak menulis bukunya sendiri; semua yang kita ketahui darinya terwariskan lewat murid-muridnya, terutama Plato.
Baginya, filsafat adalah jalan menuju keutamaan (arete). Ia percaya bahwa kebenaran bukan untuk dijual, melainkan untuk ditemukan bersama melalui dialog. Sebaliknya, Gorgias, seorang sofis terkenal, mengajarkan retorika sebagai seni membujuk, bukan seni mencari kebenaran.
Dalam karyanya Encomium of Helen, Gorgias menulis–“Speech is a powerful lord, which by means of the finest and most invisible body effects the divinest works.” Bagi Gorgias, kata-kata adalah senjata untuk menang, bukan sarana untuk mencari integritas.
Pertentangan ini terasa hidup dalam dialog Gorgias karya Plato, ketika Socrates menantang sang sofis. Ia berkata, “For the rhetorician does not need to know the truth about things; he only needs to discover some way of persuading the ignorant that he knows more than the experts.” (Plato, Gorgias).
Kritik Socrates sangat tajam: retorika tanpa kebenaran hanyalah topeng, sedangkan filsafat sejati menuntut keberanian menanggung konsekuensi dari kebenaran. Kontras ini menjadi semakin menarik dengan satu kisah jenaka yang melegenda.
Bahwa, Gorgias pernah membanggakan dirinya bisa membujuk siapa saja dengan pidatonya. Seorang muridnya berkata: “Guru, ajarkan saya agar bisa membujuk hakim membebaskan saya.” Gorgias menjawab: “Aku bisa mengajarkanmu, tetapi jika engkau berhasil membujuk hakim membebaskanmu dari pembayaran biaya sekolah, maka engkau tak perlu bayar. Jika engkau gagal, maka engkau harus membayar.”
“Jadi, bagaimanapun, aku tetap menang.” Cerita ini beredar sebagai ironi: Gorgias cerdik dalam retorika, tetapi juga licin dalam mencari keuntungan. Socrates, sebaliknya, menolak dibayar untuk pengajarannya. Ia percaya bahwa filsafat adalah jalan menuju jiwa yang baik.
Dalam Apology, ia berkata: “The unexamined life is not worth living.” Kalimat ini menjadi salah satu fondasi etika barat, menunjukkan integritas diri lebih penting daripada retorika untuk memenangkan perkara. Bagi Socrates, kematian pun lebih mulia daripada hidup tanpa kebenaran.
Lompatan sejarah membawa kita ke abad pencerahan. Di sini kita melihat perdebatan antara Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire, dua filsuf besar Prancis yang sama-sama hidup di abad ke-18, namun membawa arah pemikiran yang sangat berlawanan.
Rousseau, dalam The Social Contract (1762), dengan tegas menyatakan: “Man is born free, and everywhere he is in chains.” Bagi Rousseau, masyarakat harus dibangun atas dasar kemerdekaan kolektif, dengan mengutamakan kehendak umum (volonte generale).
Voltaire, sebaliknya, lebih condong pada pragmatisme politik dan kritik sosial. Ia terkenal karena kecerdasannya yang tajam, juga karena sikapnya yang skeptis terhadap utopia sosial Rousseau. Dalam suratnya kepada Rousseau, Voltaire pernah menulis dengan sinis setelah membaca Discourse on the Origin of Inequality.
“One longs, in reading your book, to walk on all fours.” Voltaire menyindir Rousseau yang dianggapnya terlalu mengidealkan ‘kembali ke alam’ dan menolak peradaban. Perseteruan intelektual mereka mencerminkan dua wajah pencerahan. Rousseau membawa idealisme yang memicu revolusi sosial–masyarakat yang adil, egaliter dan bebas dari tirani.
Sementara Voltaire, menggunakan kecerdasan satir dan pena tajam untuk melawan dogma agama, intoleransi dan kebodohan politik. Dalam Candide, Voltaire menuliskan kalimat yang sering dikutip: “We must cultivate our garden.” Sebuah sindiran agar manusia lebih realistis ketimbang mengejar utopia.
Rousseau dan Voltaire tidak hanya berbeda gagasan, tetapi juga gaya hidup. Rousseau hidup miskin, sering terasing dan ditolak oleh kalangan elite. Voltaire, sebaliknya, lebih dekat dengan penguasa dan aristokrat, menggunakan hubungan itu untuk melindungi dirinya sekaligus menyebarkan kritiknya.
Ini mengingatkan kita pada kontras Socrates dan Gorgias: yang satu teguh pada integritas, yang lain menggunakan kedekatan dengan kekuasaan sebagai alat perjuangan. Namun, baik Rousseau maupun Voltaire sama-sama melahirkan warisan intelektual yang tak ternilai.
Rousseau menjadi inspirasi bagi Revolusi Prancis, bahkan semboyan Liberte, Egalite, Fraternite berutang banyak pada gagasannya. Voltaire, di sisi lain, mengilhami semangat kebebasan berpendapat, toleransi beragama dan sikap kritis terhadap dogma.
Socrates dan Rousseau tampaknya berada di sisi yang sama: filsafat sebagai integritas dan keberanian melawan arus. Socrates meneguk racun demi mempertahankan kebenaran, Rousseau menanggung pengasingan demi memelihara idealismenya.
Sementara itu, Gorgias dan Voltaire menampilkan wajah yang berbeda: retorika, kecerdasan, bahkan kompromi dengan kekuasaan demi menyebarkan gagasan. Kita dapat membayangkan percakapan imajiner antara mereka berempat.
Socrates bertanya kepada Gorgias: “Apakah engkau mengajar kebenaran atau sekadar memenangkan perdebatan?” Gorgias menjawab: “Apalah arti kebenaran jika kalah di pengadilan?” Rousseau menoleh kepada Voltaire: “Apakah engkau percaya rakyat harus bebas menentukan nasibnya?”
Voltaire tersenyum getir: “Rakyat sering kali butuh pencerahan, bukan sekadar kebebasan.” Dialog semacam ini mencerminkan bahwa filsafat bukanlah jawaban final, melainkan arena abadi pertarungan. Satu cerita jenaka lain yang mewarnai perseteruan Rousseau dan Voltaire terjadi ketika Rousseau mengirimkan buku The Social Contract kepada Voltaire.
Konon, Voltaire membaca sekilas lalu menulis balik: “Aku sudah menerima bukumu yang menentang umat manusia dan kuterima dengan rasa syukur. Tak seorang pun pernah menggunakan begitu banyak akal untuk membuat kita semua jadi binatang.” Kisah ini menggelitik, tetapi sekaligus menunjukkan perbedaan visi yang tajam.
Dari perbandingan ini, tampak jelas pola berulang dalam sejarah filsafat: antara mereka yang mengutamakan kejujuran intelektual dan integritas moral, dengan mereka yang mengutamakan retorika, efektivitas, atau kompromi demi realitas. Sejarah tidak pernah berdiri di satu kutub; selalu ada tarikan antara idealisme dan pragmatisme.
Apakah retorika itu buruk? Tidak selalu. Tanpa retorika, gagasan luhur sering terjebak dalam ruang sempit akademia. Namun, tanpa integritas, retorika bisa menjelma manipulasi. Socrates dan Rousseau menjadi simbol tegaknya integritas, sementara Gorgias dan Voltaire adalah pengingat kecerdasan bisa tergelincir menjadi permainan kata.
Lebih jauh, kita belajar filsafat bukan hanya soal ide, tetapi juga soal hidup yang dijalani. Socrates berani mati demi gagasan. Rousseau berani miskin demi idealisme. Gorgias hidup dari popularitas dan retorika. Voltaire hidup dari kecerdasan dan keluwesan dalam berkompromi. Semua pilihan ini memperlihatkan wajah-wajah filsafat yang berbeda.
Dalam dunia modern, ketegangan serupa masih berlangsung. Kita melihat intelektual yang setia pada kebenaran meski harus terpinggirkan dan intelektual yang lihai berkompromi dengan kekuasaan demi tetap punya panggung. Sejarah Socrates, Gorgias, Rousseau dan Voltaire memberi kita cermin untuk menimbang: di manakah kita berdiri?
Sebagai refleksi, keempat tokoh ini sesungguhnya saling melengkapi. Tanpa Gorgias, kita mungkin takkan memahami betapa berbahayanya retorika tanpa kebenaran. Tanpa Voltaire, kita mungkin kehilangan humor dan kejernihan untuk melawan dogma. Tanpa Socrates, kita kehilangan teladan integritas. Tanpa Rousseau, kita kehilangan idealisme revolusioner. Pertarungan mereka adalah warisan, bukan sekadar perbedaan.
Dengan demikian, filsafat tidaklah statis. Ia hidup di antara perdebatan, ejekan, bahkan tragedi. Socrates mati dengan racun, Rousseau mati dalam kesepian, Gorgias wafat dalam kejayaan retorika, Voltaire meninggal dalam kehormatan.
Masing-masing kisah adalah pelajaran bahwa cara kita menghidupi filsafat sama pentingnya dengan gagasan yang kita wariskan. Akhirnya, sejarah ini menegaskan–filsafat adalah cermin diri kita sendiri. Apakah kita memilih jalan Socrates dan Rousseau yang penuh duri demi integritas, ataukah jalan Gorgias dan Voltaire yang penuh kelicinan retorika?
Jawabannya akan selalu ditentukan oleh keberanian kita untuk hidup sesuai kata hati. Seperti kata Socrates dalam Apology: “No evil can happen to a good man, either in life or after death.” Tidak ada keburukan yang sungguh-sungguh bisa menimpa orang baik, saat ia masih hidup maupun setelah ia meninggal.
Bagi Socrates, yang disebut ‘keburukan’ bukanlah sakit, kemiskinan, penderitaan, atau kematian. Itu hanya nasib duniawi. Keburukan sejati adalah kerusakan jiwa, seperti ketidakadilan, kebohongan, dan perbuatan jahat.
Karena orang baik menjaga jiwanya dengan adil dan setia pada kebenaran, maka tidak ada sesuatu pun di luar dirinya yang bisa merusaknya. Kematian bukanlah keburukan, melainkan pintu menuju kehidupan berikutnya yang tidak perlu ditakuti.
***