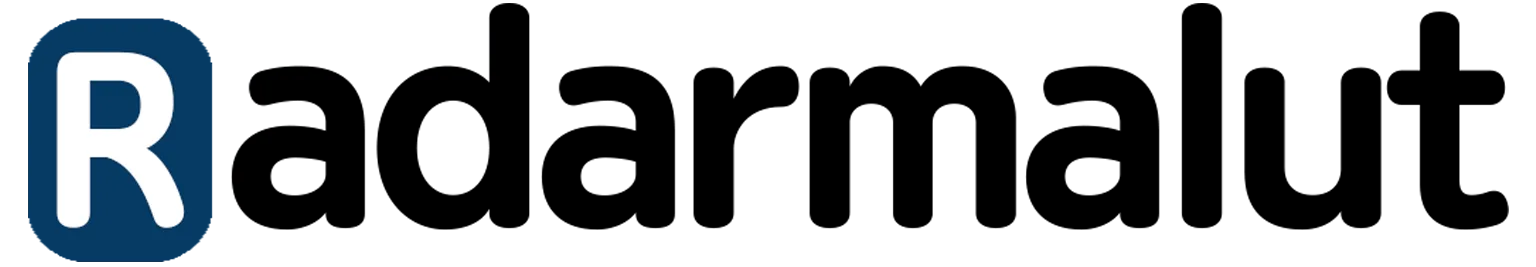Di balik riuh suara dan spanduk yang menutup jalan, demokrasi lokal di Maluku Utara berjalan seperti perahu nelayan yang disusun dari papan-papan harapan: kukuh menghadapi riak, namun berderak ketika badai politik menerjang.
Pilkada di sini bukan sekadar acara lima tahunan; ia adalah puncak drama sosial yang memanggil semua warga, dari nelayan di pulau terluar hingga pedagang di pasar kota, untuk mengambil peran. Pada momen ini, sejarah keluarga, dendam lama, persahabatan masa kecil, bahkan gosip ringan di warung kopi, semua bercampur menjadi arus deras yang menggerakkan pilihan.
Pilkada bukanlah ritual administratif belaka. Ia menyerupai upacara adat yang memadukan kegembiraan dan ketegangan: menyalakan api unggun harapan di satu sisi, dan mengobarkan bara kecurigaan di sisi lain. Masyarakat berkumpul, bercerita, menilai, bahkan menguji integritas kandidat dengan caranya sendiri.
Tak jarang, keputusan memilih lahir bukan dari diskusi panjang tentang visi pembangunan, melainkan dari siapa yang datang melayat ketika duka, atau siapa yang mau membantu biaya sekolah anak.
Penelitian tentang politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa di banyak daerah, termasuk Maluku Utara, proses formal pemilihan dari daftar pemilih, TPS, hingga rekap suara berjalan paralel dengan mekanisme informal yang lebih menentukan hasil akhir.
Clientelism, atau hubungan politik transaksional, menjadi jembatan yang menghubungkan kandidat dengan pemilih, di mana janji dan bantuan menjadi bahasa bersama yang lebih efektif daripada visi yang tertulis di manifesto.
Di desa-desa kecil, keputusan politik sering kali dipandu oleh jaringan kekerabatan, utang budi, dan pertukaran material yang tersembunyi di balik senyum ramah kandidat. Bentuk-bentuk pertukaran ini memberi kesan demokrasi tetap berjalan, padahal substansinya terkadang menyempit menjadi tawar-menawar kepentingan.
Dalam konteks ini, kemenangan bukan sekadar hasil kerja keras kampanye, tetapi juga cerminan dari keberhasilan membangun, atau memanfaatkan, jejaring patronase. Namun demikian, Pilkada tetap membuka peluang bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan untuk muncul.
Ada ruang bagi pemuda desa yang kritis, perempuan yang berani menantang stereotip, atau tokoh minoritas yang mampu memikat simpati luas. Tetapi ruang ini tidak selalu steril dari praktik lama; ia seringkali harus bernegosiasi dengan pola-pola lama yang sulit dihapuskan.
Pengalaman Pilkada di Maluku Utara menuntut kita membaca lebih dari sekadar angka yang tercetak di lembar hasil. Bahasa nonverbal kampanye seperti ritual makan bersama, pembagian bantuan simbolis, atau kehadiran tokoh adat menjadi penanda kuat tentang siapa yang sebenarnya sedang membangun kepercayaan publik.
Dalam masyarakat kepulauan yang masih memegang erat nilai adat, legitimasi sering kali lebih kuat ketika disahkan oleh tetua adat daripada oleh pengumuman resmi KPU. Geografi kepulauan dan sejarah panjang interaksi antarpulau membentuk wajah demokrasi di Maluku Utara.
Tradisi memimpin yang diwariskan dari masa kesultanan tidak serta-merta hilang ketika modernitas administratif hadir. Pilkada menjadi pertemuan unik antara warisan masa lalu dan prosedur demokrasi modern, di mana tokoh karismatik masih dapat mengalahkan kampanye teknologi tinggi. Ia hanya bisa dikalahkan ketika tokoh adat lain bersebrangan dibalik layar.
Ketika seorang kandidat menang atau kalah, yang berubah bukan hanya kursi jabatan. Akses terhadap sumber daya, peluang proyek, dan jaringan patronase ikut bergeser. Dalam beberapa kasus, kemenangan berarti membuka jalan bagi kelompok pendukung untuk menikmati prioritas pembangunan.
Sementara kekalahan bisa berarti terpinggirkannya kelompok tertentu dari pusaran distribusi manfaat. Tetapi dinamika ini tidak selalu berjalan linier. Ada saatnya yang kalah justru mampu menikmati kemenangan dalam bentuk lain dengan lihai membolak-balik fakta, menciptakan narasi yang membuat publik meragukan legitimasi lawan.
Sementara yang menang, terkadang tersungkur di tengah jalan hanya karena fitnah dari rekan-rekan sesama pemenang. Kemenangan pun bisa berakhir sebagai kekecewaan dan dusta, baik bagi kandidat maupun rakyat yang memilih.
Bahkan, rakyat yang memenangkan jagonya tak jarang merasa terabaikan ketika euforia usai. Sedangkan yang kalah, walau termarjinalkan, seharusnya tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam pelayanan publik.
Penilaian publik terhadap pemenang seringkali berfokus pada hasil konkret: jalan yang diperbaiki, dermaga yang dibangun, atau bantuan yang disalurkan. Politik pembangunan menjadi mata uang utama legitimasi pemerintah daerah.
Tetapi mata uang ini rawan inflasi moral: program-program populis yang hanya bertahan selama masa kampanye, tanpa keberlanjutan yang jelas. Logika kepentingan sesaat ini dapat memerangkap demokrasi dalam siklus pendek janji, eksekusi cepat, dan lupa. Pembangunan struktural yang mahal dan memakan waktu lama sering kali ditunda demi program instan yang mudah dilihat publik.
Ancaman lain yang tak kalah serius adalah ujaran kebencian dan disinformasi, yang menyusup melalui media sosial dan memperkeruh atmosfer politik. Sentimen sektarian, etnis, atau agama dapat dimanipulasi menjadi alat kampanye negatif, menciptakan polarisasi tajam yang menggerogoti kohesi sosial.
Dalam situasi ini, literasi politik menjadi kebutuhan mendesak. Bukan hanya kemampuan memilih, tetapi juga kecakapan memilah sumber informasi, memahami kepentingan di balik janji, serta menimbang konsekuensi jangka panjang dari pilihan politik.
Para tokoh lokal, baik birokrat, aktivis, maupun pemimpin adat, memikul tanggung jawab ganda: menjaga harmoni sosial yang diwariskan leluhur sekaligus menegakkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi demokrasi modern.
Robert A. Dahl, dalam bukunya On Democracy, mengingatkan: “Demokrasi, tampaknya, memang agak penuh risiko. Namun peluangnya juga sangat bergantung pada apa yang kita lakukan sendiri.” Kutipan ini relevan di Maluku Utara, di mana masa depan demokrasi lokal sangat bergantung pada kesediaan warganya untuk terus terlibat, mengawasi, dan mengoreksi jalannya pemerintahan.
Edward Aspinall dan Ward Berenschot, dalam Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia, menegaskan bahwa patronase dan broker politik bukanlah sekadar “penyimpangan”, melainkan mekanisme adaptif dalam sistem politik yang memberi insentif pada pendekatan transaksional.
Inilah tantangan terbesar demokrasi lokal: bagaimana mengubah insentif itu agar selaras dengan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan elite. Menang atau kalah dalam Pilkada seharusnya tidak menjadi akhir cerita. Justru setelah euforia kemenangan atau pil pahit kekalahan itulah, ujian moral dan kapasitas pemerintahan sesungguhnya dimulai.
Demokrasi sehat memerlukan dua syarat utama: ketegasan prosedural yang menjamin keterbukaan proses, dan kekuatan masyarakat sipil yang mampu menjadi pengimbang kekuasaan. Tanpa keduanya, demokrasi hanya akan menjadi hiasan yang mudah retak.
Pendidikan politik yang terintegrasi, yang mengajarkan hak dan tanggung jawab warga, keterampilan mengevaluasi janji politik, dan mekanisme pengawasan, harus menjadi investasi jangka panjang di seluruh wilayah Maluku Utara.
Pada akhirnya, demokrasi adalah kerja kolektif yang tak pernah selesai. Ia memerlukan kesabaran nelayan menunggu musim ikan, ketekunan petani menjaga tanamannya dari hama, dan keberanian warga untuk berkata benar walau itu tak populer.
Demokrasi adalah cermin: jika kita mengisinya dengan kesadaran, ia akan memantulkan wajah kita yang terbaik– jika kita mengisinya dengan kepentingan sesaat, ia akan memantulkan wajah yang tak kita kenali.
***