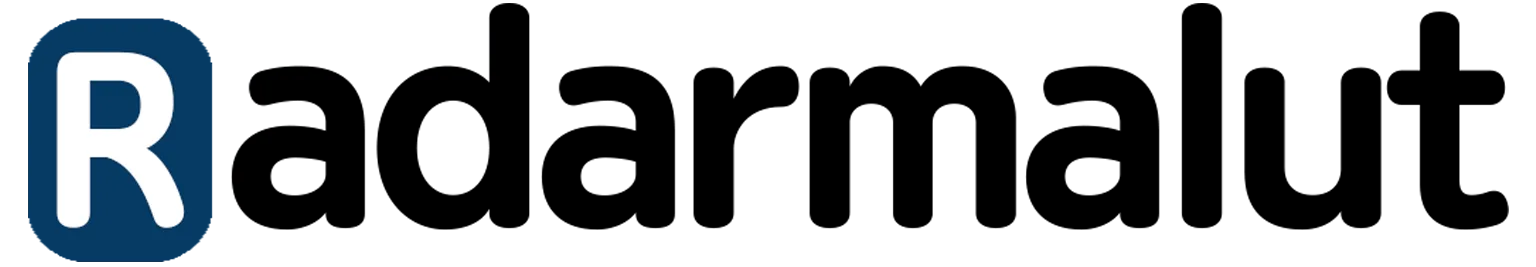Hasil riset Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako menemukan pencemaran logam berat merkuri dan arsenik pada sampel ikan di area penambangan dan pengolahan nikel Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sebanyak 47 persen sampel darah warga yang diteliti juga mengandung merkuri dan 32 persen arsenik melebihi batas aman.
Pengumpulan data yang dilakukan sejak Juli 2024 itu berfokus pada sedimentasi di Sungai Sagea dan Ake Jira. Kemudian ikan hasil tangkapan nelayan di sekitar Teluk Weda, serta darah penduduk Desa Gemaf dan Lelilef. Dua desa ini paling dekat dengan kawasan industri pengolahan nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Hasil risetnya kemudian dirilis pada 26 Mei 2025 di Jakarta dan dipublikasi sejumlah media massa. Alih-alih menindaklanjuti laporan itu, pemerintah justru merespons sebaliknya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara berencana menghentikan aktivitas nelayan di wilayah Teluk Weda. Bukan berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk menyetop aktivitas perusahaan sebagai biang kerok. Meskipun itu masih dipertimbangkan, tapi ini menandakan DKP sendiri tidak punya rencana, apalagi nyali.
Sementara, Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah justru meragukan hasil riset itu dengan berbagai dalih yang sulit untuk kita pegang. Di sini, DLH sebaiknya perlu ditekankan agar tidak menganggap remeh laporan riset itu. Sebab, dampak negatif logam berat dapat menyebabkan terjadinya bioakumulasi di dalam tubuh manusia.
Sependek pengetahuan saya, kontaminasi logam berat dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui bahan pangan, hewan sungai maupun laut, air minum, udara yang dihirup dari lingkungan yang sarat polusi, atau paparan langsung di lingkungan kerja seperti pada tungku-tungku pembakaran.
Rantai kontaminasi dari logam berat biasanya mengikuti urutan siklus, yaitu dari industri ke atmosfer. Kemudian menyatu ke dalam tanah melalui hujan dan air sungai, lalu ke rantai makanan yang dikonsumsi manusia.
Beberapa jenis logam berat seperti kadmium, timbal, mangan, dan arsenik, masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pencernaan. Sedangkan logam berat lainnya masuk melalui saluran pernapasan dan sebagian lagi lewat absorbsi kulit.
Logam berat yang masuk ke tubuh manusia kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan melalui darah. Sementara, Merkuri adalah logam berat yang bisa merusak saraf, sistem pencernaan, dan gangguan organ. Sedangkan akumulasi dari arsenik dapat meningkatkan gangguan jantung, hormon, kecerdasan anak, hingga neuron.
Laporan tentang ikan tercemar di perairan Halmahera yang menjadi titik konsentrasi industri pengolahan nikel bukan baru kali ini. Di akhir 2023, akademisi dari Fakultas Perikanan Universitas Khairun Ternate juga merilis laporan yang sama. Ikan di perairan Teluk Weda dan Teluk Buli, Halmahera Timur, terindikasi logam berat.
Sampel yang diambil adalah air laut dan ikan putih (demersal) hasil tangkapan nelayan di kedua teluk itu. Struktur sel dan jaringan ikan kemudian diuji di Laboratorium Kesehatan Ikan IPB University. Dari hasil penelitian histologi pada hati, ginjal, dan daging, terlihat sel dan jaringan ikan sudah rusak.
Kandungan krom heksavalen (Cr), nikel (Ni), dan tembaga (Cu) telah melebihi ambang baku mutu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peneliti menyimpulkan, laju distribusi kematian dalam rantai makanan laut di kedua teluk itu sudah mencapai 60 persen.
Kekuatiran dari dampak itu adalah populasi ikan di kedua teluk tersebut suatu saat akan punah. Sebab, kerusakan pada organ ikan dapat mengindikasikan masalah serius dalam proses reproduksi. Padahal lokasi itu merupakan tempat pemijahan hingga pembesaran ikan, sekaligus jalur migrasi tuna.
Sebagai gambaran, luas daratan Halmahera Tengah 2.276,86 kilometer persegi. Sedangkan lautnya 6.104,65 kilometer atau 73 persen dari luas daratan. Dari 70 lebih desa, kurang lebih 95 persen adalah desa pesisir. Itu berarti, hampir semua aktivitas masyarakat bergantung pada hasil laut.
Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Tengah mencatat jumlah nelayan yang tersebar sekitar 3.500-an. Setiap desa terdapat 20 kepala keluarga (KK), 30 KK, 50 KK, 100 KK, hingga 200 KK yang berprofesi sebagai nelayan.
Namun, keberadaan IWIP di wilayah Teluk Weda saat ini telah ditetapkan sebagai Proyek Prioritas Nasional lewat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
IWIP juga masuk sebagai Obyek Vital Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Kemudian Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dipaksa bertahan
Secara aturan, nelayan lokal diperbolehkan melaut hingga 12 mil. Tapi rata-rata perahu nelayan di Teluk Weda berbobot 2,5 sampai 3 gross tonage (GT). Itu berarti, butuh biaya besar untuk melaut dengan jarak di atas itu. Jika 12-20 mil dengan waktu tempuh sekitar 1 jam, maka dibutuhkan 10 liter BBM. Itu pun tidak menjamin hasil tangkapan yang banyak.
Persoalan lain kemungkinan hasil tangkap nelayan tradisional sulit menembus pasar ekspor, jika area tangkapnya berada dalam zona industri pertambangan. Tentu nelayan tidak bisa memanipulasi hasil tangkapnya sepanjang daftar ground fishing kapal tertera di mana titik area penangkapan. Jika di kawasan industri tambang, sulit untuk diterima.
Dalam laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Tengah akhir 2022, ikan yang beredar di pasaran Teluk Weda umumnya dipasok dari wilayah luar, seiring meningkatnya jumlah penduduk. Tapi hasil riset Nexus3 memberi sisi lain: kandungan logam berat pada penduduk lokal lebih tinggi dari pekerja di IWIP.
Itu artinya, ikan-ikan yang disuplay dari luar Teluk Weda hanya untuk memenuhi kebutuhan industri. Di lingkungan industri, selain mengutamakan savety, menu makanan yang dikonsumsi pekerja lebih variatif. Berbeda dengan warga pesisir yang rata-rata mengkonsumsi hasil laut antara 2-3 kali sehari.
Padahal dalam Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2014 – 2023 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), Teluk Weda ditetapkan sebagai zona perikanan tangkap pelagis dan demersal, serta zona potensial wisata alam bawah laut. Tapi semua itu seakan tak berlaku lagi.
Ragam dampak yang dialami warga tersebut baru dihitung dalam skala ruang yang ditempati IWIP di atas lahan seluas 4,27 hektare. Apa jadinya jika telah diperluas 13,784 hektare, yang telah disahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Halmahera Tengah di tahun 2024 kemarin.
Sementara, demi mendorong kebutuhan operasional industri, IWIP pun tengah memperluas areal pelabuhan untuk menaikkan kapasitas bongkar muat sebesar 550.000 DWT dari yang sudah ada sebesar 1.100.000 DWT, untuk mencapai kapasitas 1.650.000 DWT. Selain dermaga, IWIP juga memperluas area bandara sepanjang 2.500 meter.
Dan hampir semua material reklamasinya menggunakan limbah slag peleburan nikel dan Bottom Ash, atau limbah padat hasil pembakaran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan sumber emisi merkuri, dengan total area seluas 30 hektare. Itu berarti, semua bahan urukan ini berkontribusi pada pencemaran di perairan sekitar. Ini bertolak belakang dengan alasan percepatan industri baterai dan mobil listrik untuk mendorong ekonomi rendah karbon.
Karena seluruh mata rantai operasi IWIP membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar (proses peleburan dengan suhu tinggi), maka IWIP kemudian menambah kapasitas PLTU sebesar 760 MW dari 6.560 MW yang sudah eksisting, dengan total kapasitas yang dioperasikan mencapai 7.320 MW.
Kebanggaan palsu
Indonesia boleh berbangga sebagai negara maritim. Kerap juga disebut sebagai bangsa bahari. Tentu penyebutan ini mengisyaratkan identitas geografis Indonesia yang memiliki luas lautan 70 persen, 30 persen daratan, dan 17.000 pulau dengan garis pantai mencapai 99.000 kilometer. Itu berarti dua pertiga kawasan negara ini adalah lautan.
Makanya, setiap 2 Juli selalu kita peringati Hari Kelautan Nasional dan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Tapi kesadaran kita tentang ruang laut kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Nyaris tak ada diskursus tentang itu.
Bahkan, pilar kedua dari konsep poros maritim dunia yang digagas bekas Presiden Joko Widodo, adalah menjaga dan mengelola sumber daya laut yang berfokus pada pembangunan kedaulatan pangan laut. Hal ini dilakukan melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Tapi semua itu bertolak belakang dengan kondisi yang dialami nelayan-nelayan di Pulau Halmahera. Mulai dari Teluk Kao di Halmahera Utara, Teluk Buli di Halmahera Timur, Teluk Weda di Halmahera Tengah, hingga pesisir Desa Kawasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, yang saat ini ruang lautnya kian terjepit setelah Harita datang.
Pemerintah justru memberikan karpet merah untuk agenda penaklukan atau kolonialisasi modern yang dikemas dengan istilah palsu bernama “transisi energi.” Padahal, transisi energi idealnya merupakan peralihan sistematis atas konsumsi energi berbasis fosil menuju sumber-sumber energi baru yang berkelanjutan.
Tapi pada praktiknya, kehadiran industri ekstraktif ini justru melanggar prinsip-prinsip utama dari transisi energi: menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengutamakan kelestarian lingkungan hidup, dan mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.
Pada akhirnya, elektrifikasi kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai solusi dalam menekan emisi karbon, justru memperluas daya rusak. Tidak hanya ruang hidup warga, tapi juga meracuni rantai makanan yang tersaji di atas meja makan.
***