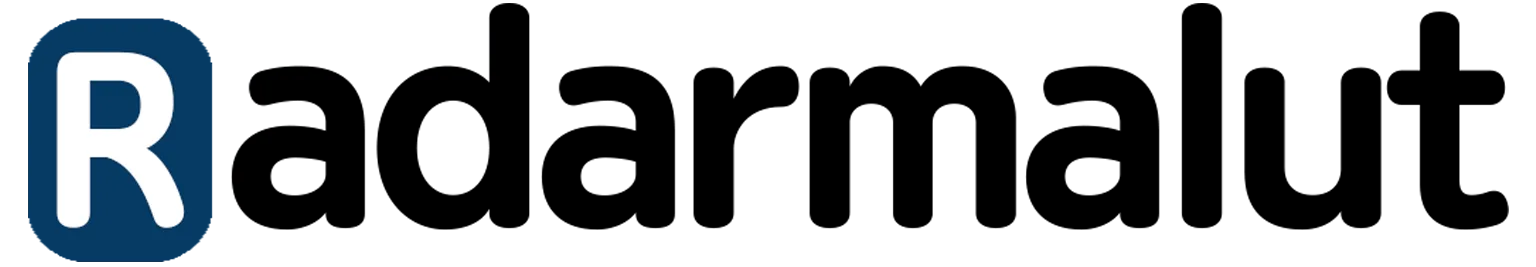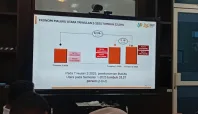Kawan, cari posisi duduk yang nyaman. Buatkan kopi, hirup aromanya. Setelah itu, mari kita pergi ke sudut Asia Tenggara, di wilayah di mana bendera berkibar tinggi, tapi suara sejarah masih menyimpan bara.
Ini tentang Thailand versus Kamboja, dua negara yang bertetangga, tetapi kadang seolah dipisahkan oleh luka lama yang tak sempat diobati dengan baik. Di tengah dunia yang terus berubah, eskalasi antara Thailand dan Kamboja kembali menyita perhatian.
Bukan semata soal sengketa perbatasan, bukan hanya tentang siapa yang lebih dulu mengibarkan bendera di sebuah kuil purba, tapi tentang trauma kolonial, ego nasionalisme, dan minimnya ruang dialog yang sehat.
Konflik dua negara ini menggambarkan bagaimana sejarah yang belum selesai bisa menjelma ranjau dalam relasi antarbangsa. Thailand dan Kamboja telah lama memiliki hubungan yang penuh liku. Sengketa Kuil Preah Vihear misalnya, bukan sekadar masalah tapal batas, melainkan simbol identitas dan kebanggaan nasional.
Mahkamah Internasional pada 1962 memang memutuskan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja. Tapi bayang-bayang perpecahan tetap bergelayut karena perbatasan di sekitar wilayah itu tak kunjung disepakati secara final.
Seperti yang diungkap oleh Benedict Anderson, nasionalisme kerap dibangun dari “komunitas-komunitas imajiner” yang merasa memiliki satu kesatuan sejarah. Tapi ketika imajinasi itu berhadapan dengan klaim konkret peta, tembok, dan senjata, maka nasionalisme bisa menjelma jadi bahan bakar konflik yang nyata.
Dalam beberapa tahun terakhir, tensi meningkat bukan hanya karena klaim kedaulatan, tetapi juga pengaruh kekuatan global yang ikut bermain di belakang layar. Infrastruktur militer diperkuat, latihan perang diperbanyak, dan narasi di media nasional makin provokatif.
Akibatnya, warga sipil di perbatasan menjadi korban diam-diam dari permainan geopolitik yang jauh lebih besar. Konflik ini juga memperlihatkan ketimpangan diplomasi ASEAN, di mana mekanisme penyelesaian konflik regional kerap pasif dan lambat.
Meski ada Piagam ASEAN yang menjunjung prinsip “tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota”, justru prinsip inilah yang membuat banyak konflik internal dan bilateral dibiarkan membara dalam diam.
Tak ada jalan instan menuju perdamaian, tapi ada langkah-langkah konkret yang bisa dirintis yaitu pertama, Pembentukan Komisi Bersama Sejarah dan Budaya–melibatkan para sejarawan dan budayawan dari kedua negara untuk menulis ulang narasi sejarah secara adil dan inklusif, agar generasi muda tak mewarisi kebencian.
Kedua, Zona Ekonomi dan Pendidikan Bersama di Wilayah Sengketa–jadikan daerah perebutan itu sebagai pusat kerjasama budaya, pariwisata dan inovasi pendidikan.
Ketiga, Melibatkan Masyarakat Sipil dan Pemuda: Anak muda adalah agen perdamaian yang paling segar. Diplomasi tidak hanya milik elit negara, tapi juga bisa digerakkan dari akar rumput.
“Perdamaian bukanlah ketiadaan konflik, tetapi kehadiran keadilan,” kata Martin Luther King Jr. Karenanya Indonesia mesti bergerak. Sebagai negara besar di Asia Tenggara dan pendiri utama ASEAN, Indonesia memegang peran strategis.
Dengan pengalaman mendamaikan konflik Aceh dan keterlibatan aktif di berbagai forum PBB, Indonesia bisa;– menjadi mediator aktif dan netral, misalnya melalui misi khusus diplomatik untuk Thailand-Kamboja.
Menginisiasi forum tahunan “ASEAN Peace Table” yang mempertemukan tokoh agama, sejarawan, aktivis damai, dan akademisi dari negara-negara anggota–mengajak media dan seniman lintas negara untuk membangun narasi damai dan sejarah bersama melalui film, sastra, dan seni pertunjukan.
Perang bukan takdir, ia hanyalah hasil dari kegagalan memahami satu sama lain. Jika sejarah pernah membuat Thailand dan Kamboja bertikai, maka narasi baru bisa membuat mereka berdamai. ASEAN tidak boleh menjadi forum basa-basi, tapi wadah aksi nyata.
Dan Indonesia, yang pernah menjadi rumah para pemikir dan revolusioner Asia, punya tanggung jawab moral untuk hadir di tengah konflik bukan sebagai hakim, tapi sebagai jembatan.
Mari kita terus percaya bahwa dialog lebih tajam dari peluru, dan secangkir kopi bisa lebih kuat dari diplomasi kaku, jika disertai niat baik, keberanian memaafkan dan imajinasi akan masa depan bersama.
“Perang bukan takdir, ia hanyalah hasil dari kegagalan memahami satu sama lain.”
***