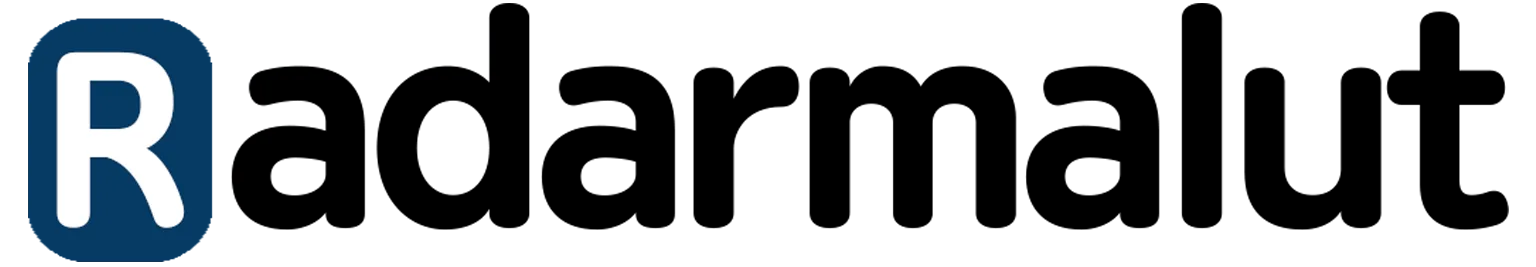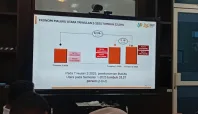“Demokrasi bukan hanya tentang suara mayoritas, tapi tentang integritas narasi dan kejujuran niat.”–Fareed Zakaria.
KAWAN, mari kita ngopi sambil berdiskusi tentang demokrasi dan Monarki Yang Tersisa. Iya, tema-nya agak menggelegar. Sebab, tulisan ini sengaja untuk mengoreksi kebohongan elite dan penerapan demokrasi ala Monarchy.
Padahal, mereka lupa kalau pikiran anak muda dan masyarakat Maluku Utara telah maju dan memahami tentang demokrasi. Seperti kata beberapa filsuf di Eropa era pencerahan, misal Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, hingga John Locke.
Yang percaya bahwa kebebasan dan pikiran adalah dua sayap utama manusia dalam meraih kemajuan demokrasi dan peradaban. Tapi apa jadinya jika demokrasi kita justru dibajak oleh kebisingan, doktrinasi, dogmatisasi dan kebohongan yang terlihat sakti? Sebelum lanjut, pesan dulu kopinya, kawan.
Di atas tanah yang dahulu disapa Oba dan dihormati para leluhur dalam ritual sunyi, ia sebetulnya mendambakan elite politik dengan ciri khas Umar bin Khattab di Madinah, atau Umar bin Abdul Aziz di Mesir atau Baldwin si bijak dari Romawi.
Namun hari ini sepertinya tak terlihat, yang ada hanyalah suara-suara mulai berderak. Sofifi, yang sejak ditunjuk menjadi ibu kota provinsi Maluku Utara dua dekade silam, tak kunjung mendapat tubuh administratifnya yang utuh.
Tetapi yang ramai bukan lagi tentang peta jalan otonomi, melainkan perihal dua barisan yang saling menepuk genderang, yakni satu berisi harapan, satunya penuh kecurigaan. Di tengahnya, suara rakyat nyaris tenggelam dalam sorak drum kosong.
Barisan pertama membawa agenda pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Sofifi dengan argumentasi kemajuan– pelayanan publik yang lebih dekat, akses yang lebih terbuka dan pembangunan yang terdistribusi.
Mereka berdemonstrasi dengan tenang, membawa poster dan diskusi terbuka, menyajikan data, menyampaikan aspirasi dengan gaya yang tertata.
Barisan kedua justru tampak berteriak sembarangan, melempar tuduhan, marah-marah tanpa arah, seolah lupa bahwa kita tidak sedang hidup di era monarki absolut di mana suara rakyat bisa dibungkam dengan nada tinggi dan wajah tegang.
Mereka yang menolak DOB mungkin tidak sadar bahwa generasi saat ini sudah tak bisa dibodohi dengan gaya-gaya feodal, doktrinasi, dogmatisasi dan intimidasi emosional. Demokrasi telah mengajari anak muda dan rakyat untuk membaca, berpikir kritis, menimbang dan menyuarakan.
Lalu, apakah suara mereka akan terus dikerdilkan hanya karena mereka tidak patuh terhadap tradisi Monarchy?Lucunya, ada elite yang dulu saat menjadi calon pemimpin, berdiri di podium rakyat sambil berteriak, “Saya pendukung DOB Sofifi!”.
Tapi begitu kalah atau menang dalam kontestasi, narasinya berubah total–“Saya menolak! Demi menjaga warisan leluhur dan stabilitas budaya.” Seolah suara leluhur hanya turun kepada yang menang dan tidak kepada yang sedang berjuang dengan bersih. Seolah tradisi itu bisa dijual dengan diskon lima tahunan Pemilu.
Narasi ini semakin menggugah ketika sebagian elit mencoba menciptakan ilusi bahwa perjuangan DOB hanyalah siasat penguasa semata. Klausa yang dijejali adalah praduga tanpa data, seolah demokrasi boleh dipenuhi asumsi, asal menguntungkan posisi.
Sesungguhnya, seperti ditegaskan oleh Amartya Sen, peraih Nobel bidang Ekonomi. “Kebebasan adalah sekaligus sarana dan tujuan pembangunan. Tanpa otonomi politik dan institusional, tak akan pernah lahir pembangunan yang adil.”
Semangat DOB Sofifi bukan milik seorang gubernur, bukan pula soal satu atau dua orang elite yang tengah berkuasa. Ini adalah perjuangan panjang rakyat Maluku Utara yang mendambakan satu ruang baru yang lebih gesit, lebih dekat dan lebih berpihak.
Daripada vakum selama 25 tahun yang kita lewati. Sofifi bukan sekadar lokasi geografis. Ia adalah simbol janji negara yang belum lunas. Maka, siapa pun yang menolak hanya karena antipati pada satu individu, atau ego etnisitas, sejatinya mereka telah mereduksi makna otonomi menjadi sekadar drama personal dan komunitas.
Ada pula suara sumbang yang menyebut “DOB ini pengalihan isu tambang.” Padahal tidak ada pertarungan ide yang utuh yang saling menegasikan. Bicaralah tentang tambang, jika memang peduli lingkungan. Tapi jangan mengerdilkan aspirasi DOB hanya karena khawatir sorotan publik terbagi.
Keduanya, penguatan kelembagaan daerah dan penyelamatan sumber daya alam, adalah dua pilar berbeda yang sama penting dan genting dalam tubuh demokrasi yang sehat. Yang dibutuhkan sekarang adalah kedewasaan demokrasi–memisahkan mana aspirasi struktural dan mana dugaan personal.
Janganlah kita menabur racun prasangka di ladang argumentasi publik. Rakyat tidak sedang bicara tentang siapa gubernurnya, siapa elitnya. Rakyat bicara tentang akses jalan, tentang pelayanan kesehatan, tentang sekolah yang layak, tentang status kota yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Itulah substansi DOB.
Kita semua pernah menjadi pemilih. Kita pernah mengeluh jalan berlubang, sekolah rusak, listrik padam dan laut terkontaminasi. Tapi saat ruang otonomi ditawarkan, kita malah saling curiga, saling jegal dan berpura-pura sedang menjaga warisan.
Sebenarnya drum yang dipukul nyaring itu, isinya kosong. Hanya gema ego dan balutan oportunisme serta doktrinasi. Kini, mari kita uji keberanian dan kejujuran–beranikah kita berdiri di sisi rakyat, bukan di bawah bayang-bayang dendam kekuasaan?
Sofifi tak butuh drum kosong. Ia butuh suara nyata. Butuh niat bersih. Butuh keberpihakan yang matang. Sebab yang sedang diperjuangkan bukan segelintir nama, tapi masa depan anak-anak kita yang akan bertanya–mengapa ibu kota provinsinya tak bisa menjadi kota?
“Mereka datang dengan membunyikan tiang listrik, seolah revolusi sedang digenggam. Tapi pulang dengan basah kuyup, berenang untuk naik perahu, sebab narasi yang mereka bawa terlalu ringan untuk menyeberang gelombang akal sehat.”
***