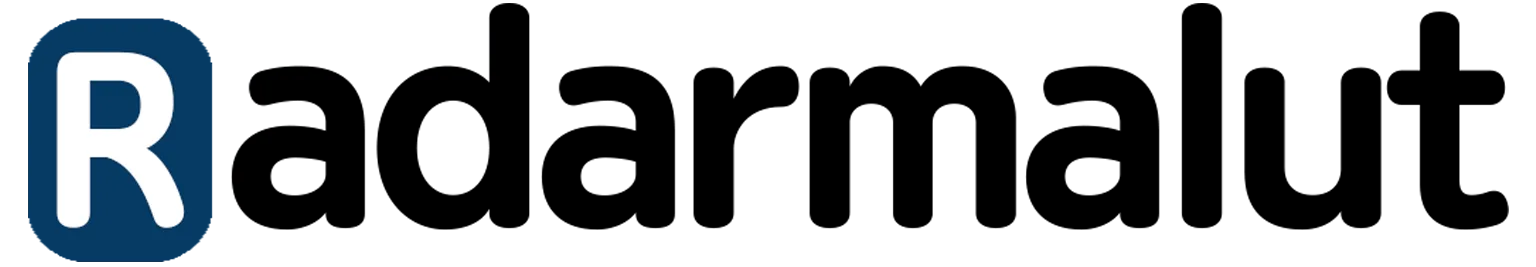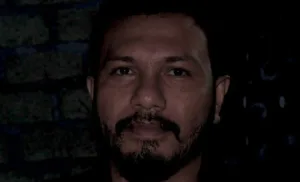Hedonisme, apatisme dan pragmatisme tumbuh diam-diam di kampus seperti tanaman liar yang subur oleh waktu. Ia tidak datang sebagai ide besar, melainkan sebagai kebiasaan kecil yang berulang; memilih nyaman daripada benar, memilih aman daripada bermakna, memilih cepat selesai daripada berproses.
Dalam keseharian itulah watak mahasiswa diuji, tanpa spanduk, tanpa teriakan. Ia melihatnya pertama kali di lorong fakultas, ketika diskusi tentang kebijakan kampus kalah oleh obrolan promo akhir pekan. Bukan karena mahasiswa tidak cerdas, melainkan karena kenyamanan menawarkan pelarian yang halus.
Hedonisme tidak selalu tentang kemewahan; ia sering hadir sebagai keinginan untuk hidup tanpa kepekaan sosial. Di kafe-kafe sekitar kampus, hedonisme menemukan rumahnya. Gelas-gelas dingin berembun, tawa yang meledak tanpa sebab, dan musik yang menenggelamkan percakapan serius.
Tidak ada yang salah dengan penampilan dan kemewahan, tetapi bahaya muncul ketika kemewahan dijadikan alasan untuk menunda kepedulian. Apatisme menyusul sebagai saudara kandung hedonisme. Ia berbisik lembut: urusan itu bukan milikmu, suaramu tidak akan mengubah apa-apa.
Apatisme jarang berteriak; ia bekerja dengan meyakinkan orang bahwa cuek atau diam adalah pilihan paling rasional. Di ruang kelas, apatisme sering menyamar sebagai profesionalisme. Mahasiswa belajar mengerjakan tugas, mengumpulkan nilai dan menutup mata dari ketimpangan di sekelilingnya.
Mereka merasa telah menjalankan peran, tanpa bertanya untuk siapa pengetahuan itu digunakan. Pragmatisme datang dengan wajah paling masuk akal. Ia menawarkan efisiensi, hasil cepat dan manfaat personal.
Dalam organisasi kampus, pragmatisme sering tampil sebagai strategi: jangan terlalu keras, jangan terlalu lama, yang penting nilai aman dan beres. Pada titik tertentu, pragmatisme tampak bijak. Tidak semua pertarungan harus diambil, tidak semua isu harus dihadapi.
Namun ketika pragmatisme kehilangan nilai, ia berubah menjadi kalkulasi dingin yang mengorbankan prinsip. Hedonisme, apatisme dan pragmatisme membentuk segitiga yang kuat. Hedonisme memberi alasan untuk menikmati, apatisme memberi pembenaran untuk diam, dan pragmatisme memberi justifikasi untuk berkompromi.
Dari segitiga itulah aktivisme sering terdesak. Ia ingat rapat organisasi yang sunyi. Bukan karena tak ada masalah, tetapi karena semua sepakat untuk tidak membicarakannya. Diam menjadi kesepakatan tak tertulis dan ketenangan palsu dianggap kemenangan.
Hedonisme membuat perjuangan terasa melelahkan. Mengapa harus rapat panjang jika ada hiburan instan? Mengapa harus membaca kebijakan jika ada konten singkat yang lebih menghibur? Pertanyaan-pertanyaan itu merayap tanpa disadari.
Apatisme kemudian menguat. Ketika satu suara diabaikan, suara lain memilih tidak bersuara. Bukan karena setuju, melainkan karena lelah. Apatisme adalah kelelahan yang dinormalisasi. Pragmatisme menutup lingkaran. Ia berkata, ambil yang mungkin saja. Jangan bermimpi terlalu tinggi.
Realistis adalah kata kunci yang terdengar dewasa, meski sering menyingkirkan keberanian. Namun kampus sejatinya dibangun untuk melawan ketiganya. Kampus adalah ruang untuk bertanya, bukan sekadar menikmati.
Ruang untuk peduli, bukan sekadar menyelesaikan. Ruang untuk berpikir jangka panjang, bukan sekadar menghitung untung-rugi. Dalam sejarah gerakan mahasiswa, setiap perubahan lahir dari keberanian menentang arus nyaman. Mereka yang bergerak sering dituduh naif, tidak realistis, atau mengganggu ketertiban.
Namun tanpa mereka, kampus akan menjadi pabrik ijazah tanpa nurani. Hedonisme merampas waktu, apatisme merampas empati, dan pragmatisme merampas nilai. Aktivisme hadir untuk merebut kembali ketiganya, meski dengan harga lelah dan risiko disalahpahami.
Ia menyadari bahwa melawan ketiganya tidak harus dengan teriakan. Terkadang, melawan hedonisme berarti memilih diskusi daripada pesta. Melawan apatisme berarti bertanya ketika yang lain diam. Melawan pragmatisme berarti menolak kompromi yang melukai prinsip.
Di organisasi kampus; intra dan ekstra, pertarungan ini terasa nyata. Setiap keputusan menguji keberpihakan: apakah ini untuk kemudahan atau untuk kebenaran? Apakah ini untuk sekarang atau untuk dampak jangka panjang?.
Mahasiswa belajar bahwa tidak semua yang efisien itu etis. Tidak semua yang menyenangkan itu membebaskan. Tidak semua yang realistis itu benar. Pelajaran ini tidak tertulis di modul, tetapi terasa di setiap pilihan.
Hedonisme menawarkan kesenangan tanpa makna, apatisme menawarkan ketenangan tanpa tanggung jawab, dan pragmatisme menawarkan hasil tanpa proses. Aktivisme, sebaliknya, menawarkan makna dengan risiko.
Ia melihat kawan-kawan yang memilih jalan sunyi. Mereka menolak arus tanpa membuat keributan, bekerja konsisten tanpa panggung. Dalam diam mereka, aktivisme menemukan bentuk lain yang tidak kalah penting.
Namun ia juga melihat mereka yang terseret arus. Bukan karena niat buruk, melainkan karena arus itu kuat dan tampak wajar. Kampus mengajarkan bahwa kesadaran harus dirawat, atau ia akan layu.
Melawan hedonisme, apatisme dan pragmatisme bukan berarti menolak kebahagiaan, ketenangan, atau strategi. Yang ditolak adalah ketika ketiganya menjadi alasan untuk mengabaikan nilai. Aktivisme kampus tidak menuntut semua orang menjadi orator.
Ia hanya meminta kejujuran: pada diri sendiri, pada situasi, dan pada nilai yang diyakini. Dari kejujuran itu, keberanian sering menyusul. Di akhir masa studi, mahasiswa menoleh ke belakang. Mereka bertanya, apa yang dipilih saat diuji oleh kenyamanan, kelelahan, dan kepentingan?.
Jawaban atas pertanyaan itu membentuk watak jauh setelah kampus ditinggalkan. Hedonisme, apatisme dan pragmatisme mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Namun aktivisme mengajarkan cara mengendalikannya, agar manusia tidak dikendalikan olehnya.
Dan selama kampus masih memberi ruang berpikir bebas, pertarungan ini akan terus berlangsung. Di sanalah mahasiswa belajar menjadi manusia yang tidak sekadar hidup, tetapi sadar mengapa dan untuk siapa ia hidup.
***