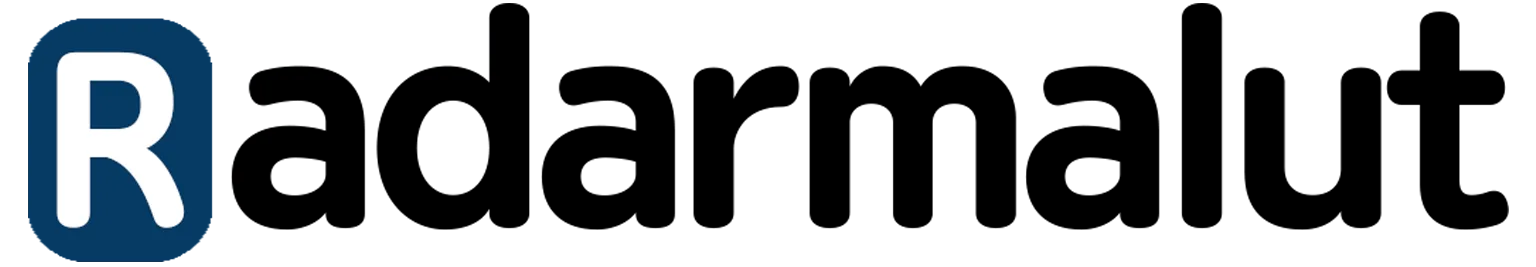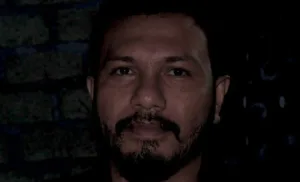Di kampus itu, ada aturan tak tertulis yang selalu melekat: seorang aktivis tidak boleh takut dan tidak boleh sakit. Tidak sakit secara fisik, tidak sakit secara mental, bahkan tidak boleh digoyahkan oleh keraguan. Aktivis harus selalu hadir, harus selalu siap, harus selalu terdengar.
Seolah takut dan sakit adalah kelemahan yang bisa merusak semangat perjuangan. Ia mengingat malam-malam ketika demam menyerang, tetapi rapat tetap dipaksakan. Kopi pahit dan obat seadanya menjadi teman setia. Tubuh yang gemetar dan kepala yang berdenyut tidak bisa menjadi alasan untuk absen.
Ada janji yang lebih besar daripada rasa sakit dan ketakutan: sebuah kewajiban terhadap kawan-kawan seperjuangan dan terhadap idealisme yang mereka sebut ‘perjuangan’. Sakit menjadi paradoks. Di satu sisi, tubuh menuntut istirahat, di sisi lain, hati menolak diam.
Aktivis belajar membaca tubuhnya sendiri, menahan nyeri, menyembunyikan luka, sambil tetap tersenyum ketika berbicara di depan rapat. Takut pun dipendam, karena keberanian harus selalu tampak utuh. Mereka menjadi ahli dalam menutupi kelemahan, seolah kekuatan fisik dan mental adalah syarat mutlak keberanian.
Tapi sakit dan takut bukan hanya soal fisik. Ia hadir dalam bentuk lelah yang tak tertahankan, frustrasi terhadap ketidakadilan yang tak pernah selesai, kecewa karena idealisme sering tersingkirkan oleh kepentingan. Mental yang rapuh pun dianggap tidak layak. Aktivis harus menolak rasa sakit dan ketakutan itu, walau sesekali hati ingin menyerah.
Setiap kali demam datang atau rasa cemas menyeruak, ia memaksakan diri hadir di ruang organisasi. Setiap rasa letih, ia bungkam agar tidak mengganggu agenda. Setiap ketakutan, ia simpan agar tidak menular. Aktivis dilarang sakit dan takut, karena kehadiran mereka menjadi simbol kontinuitas gerakan, simbol bahwa perjuangan tidak berhenti.
Di lapangan aksi, sakit dan takut terasa paling nyata. Tubuh yang kelelahan harus tetap berdiri di tengah hujan, berteriak dengan suara yang mulai serak, mengangkat spanduk yang basah kuyup. Semua itu dilakukan tanpa mengeluh dan tanpa mundur, karena mundur dianggap pengkhianatan terhadap diri sendiri dan kawan-kawan.
Teman-teman yang melihat sering diam. Mereka tahu, sakit dan takut adalah hal paling manusiawi, tetapi dalam dunia aktivis, kemanusiaan sering kali dikorbankan demi prinsip. Mereka belajar menelan rasa sakit dan ketakutan sendiri, sambil tetap mendorong satu sama lain untuk tidak tergelincir.
Sakit mental muncul lebih halus, tetapi lebih menggerogoti. Ketika kritik disalahpahami, ketika keputusan rapat melawan hati nurani, ketika idealisme harus menunduk pada kompromi, semua itu terasa sebagai penyakit yang sulit disembuhkan.
Aktivis belajar bertahan dalam kesepian psikologis, menemukan keberanian di dalam diri sendiri. Ada malam-malam ketika ia menangis diam-diam di kos. Tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun melihat. Keesokan harinya, ia tetap hadir di rapat, tersenyum, memberikan argumen, menuliskan catatan.
Sakit dan takut itu tidak boleh muncul di depan publik, karena reputasi dan citra gerakan harus tetap utuh. Bahkan dalam sakit dan takut, tubuh dan pikiran harus tetap produktif. Aktivis dilarang berhenti menulis, berdiskusi, atau mengorganisasi.
Semua hal itu menjadi ritual keberanian, latihan ekstrem untuk menekan manusiawi agar sesuai dengan ideologi dan tanggung jawab kolektif. Namun, di balik penolakan terhadap sakit dan takut, tersimpan pelajaran tersamar: kesadaran akan batas manusia.
Aktivis yang terlalu keras pada tubuh dan jiwa sering kali menemukan dirinya jatuh lebih dalam ketika akhirnya menyerah. Sakit dan takut, meski dilarang, selalu kembali. Ia menyadari bahwa dilarang sakit dan takut bukan berarti tidak merasakannya.
Itu hanya berarti bahwa rasa sakit dan ketakutan harus dihadapi, disembunyikan dan disalurkan. Seperti api, energi itu menjadi bahan bakar untuk melanjutkan perjuangan, meski api itu kadang membakar diri sendiri.
Dalam rapat malam yang panjang, ketika tubuh menolak dan mata sulit terbuka, ia menemukan bahwa kesetiaan terhadap gerakan bukan soal mengalahkan rasa sakit atau takut, tetapi mengelolanya. Aktivis belajar berdamai dengan rasa sakit dan ketakutan, tanpa membiarkannya menahan langkah.
Di setiap aksi jalanan, tubuh yang letih tetap bergerak, mental yang rapuh tetap bertahan. Mereka tahu bahwa di luar kampus, dunia tidak menunggu. Aktivis dilatih untuk selalu siap, meski tubuh memberi peringatan dan ketakutan muncul sebagai bayangan.
Ada keindahan tersendiri dalam keberanian menghadapi sakit dan takut. Ia mengajarkan ketekunan, mengasah ketahanan dan membentuk karakter yang kuat. Aktivis yang mampu bertahan memiliki kedalaman yang tidak dimiliki mereka yang selalu nyaman.
Teman-teman yang dilarang sakit dan takut belajar memahami satu sama lain lebih baik. Empati muncul bukan dari kata-kata, tetapi dari pengamatan terhadap wajah yang pucat, langkah yang lambat, atau suara yang serak. Solidaritas menjadi obat tak terlihat.
Sakit dan takut mengajarkan batas, tetapi juga membangun hubungan. Aktivis yang terbiasa menghadapi rasa sakit dan ketakutan bersama kawan-kawan, menyadari bahwa gerakan adalah kolektif. Tidak seorang pun boleh runtuh sendiri, karena setiap jatuh bisa menyeret yang lain.
Mereka belajar bahwa perjuangan adalah kombinasi antara keberanian dan kerentanan. Aktivis dilarang sakit dan takut, tetapi memahami rasa itu membuat mereka manusiawi, realistis dan lebih siap menghadapi kenyataan.
Ketika masa kuliah berakhir, semua ingatan tentang sakit dan takut yang dipaksakan menjadi kenangan pahit-manis. Tubuh lelah, mental teruji, tetapi jiwa lebih kuat. Aktivis yang pernah dilarang sakit dan takut membawa pengalaman itu ke dunia nyata, ke masyarakat, dan ke jalan kehidupan yang lebih luas.
Karenanya, “dilarang sakit dan takut” bukan perintah sewenang-wenang. Ia adalah pelajaran tersamar tentang tanggung jawab, tentang bagaimana menyeimbangkan keberanian, kesadaran diri dan solidaritas.
Aktivis belajar bahwa meski sakit dan takut selalu datang, bagaimana mereka menghadapi keduanya, untuk menentukan kualitas perjuangan mereka.
***