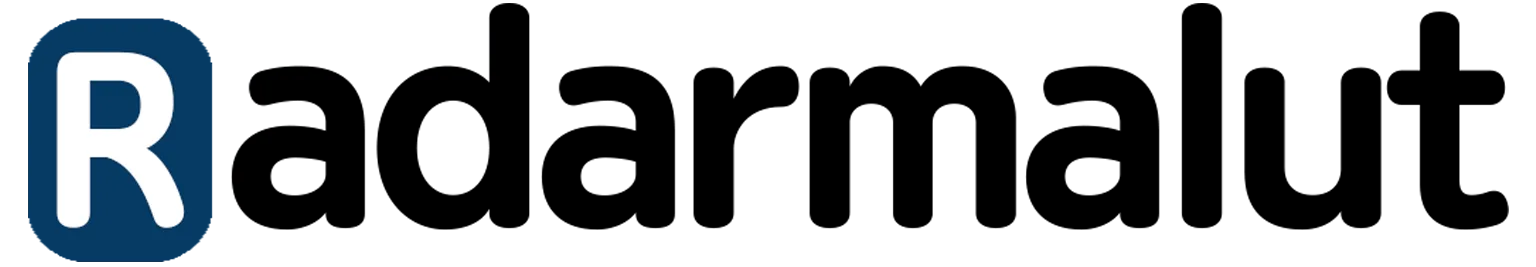Radarmalut.com – Istilah Maluku pada mulanya menunjuk pada keempat pusat kerajaan atau kedaton di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi yang kemungkinan besar muncul dalam abad ke-14, disebut Maloko Kie Raha atau empat gunung Maluku.
Sekalipun kemudian keempat kerajaan itu berekspansi sehingga mencakup seluruh Maluku Utara (sekarang) dan sebagian dari Sulawesi dan Irian Jaya, namun wilayah ekspansi itu tidak tercakup dalam istilah Maluku yang hanya menunjuk pada pusat-pusat kerajaan tersebut di atas.
Dengan sendirinya wilayah kepulauan Ambon (yang kini dinamakan Provinsi Maluku) dan sebagian wilayah kepulauan Banda (yang kini dinamakan Maluku Tenggara) dalam masa itu sama sekali tidak tercakup dalam pengertian asli dari istilah Maluku itu.
Dari segi etimologi arti dari kata Maluku memang tidak terlalu jelas, sehingga menjadi bahan spekulasi dari berbagai kalangan dan ahli. Pada suatu ketika banyak diterima umum bahwa istilah itu berasal dari bahasa Arab dengan bentuk aslinya diperkirakan sebagai Jaziratul Muluk, yang berarti wilayah banyak raja (muluk adalah bentuk jamak dari malik yang berarti raja).
Kenyataan bahwa di Maluku Utara terdapat empat raja sebagai kelaziman politik agaknya menjadi ilham bagi pemberian arti dari kata Malulru tersebut. Namun kalau diingat bahwa istilah Maluku itu telah digunakan sebelum masuknya agama Islam di wilayah itu dalam abad ke-15, maka keterangan tersebut masih diperlukan kajian yang lebih teliti.
Pendapat dari seorang Antropolog Belanda, Dr. Ch. F. Van Fraassen, patut dikemukakan di sini sebagai pertimbangan pula. Van Fraassen mengadakan penelitian mengenai sistem pemerintahan tradisional dan pola pengaturan masyarakatnya dan mengenal pola budaya dan bahasa setempat.
Ia berargumentasi, bahwa ada kemungkinan kata Maluku seperti digunakan di Malulru Utara dalam masa-masa sebelum abad ke-18 mengandung arti dunia, yang hampir sama dengan kata bhumi atau bhuwana dalam tradisi politik Jawa. (Van Fraassen 1987, II: 16-27).
Arti kata ma memang tidak menimbulkan masalah karena cukup umum di Maluku Utara, khususnya bahasa-bahasa non-Austronesia. Kata itu berfungsi sebagai kata penghubung, antara lain, sebagai kata ganti empunya persona ke-3 jenis netral, seperti kata-kata ma ba’ba yang berarti ayah saya, atau ma nau’u yang berarti suami saya, dsb. (Visser & Voorhoeve 1987 : 136,37).
Masalah timbul pada arti kata loko yang tidak bisa dijelaskan, sehingga Van Fraassen mendapat kebebasan untuk membuat suatu interpretasi yang cukup menarik. Ia menemukan, bahwa dalam salah satu bahasa di Halmahera Utara, arti kata loko mengacu pada gunung. Gunung sebagai lambang kerajaan adalah suatu hal yang lumrah pula di masa lampau, terutama di Jawa dan Sumatera (Syailendra, umpamanya).
Bahkan kedaton bisa dilambangkan sebagai gunung, sehingga kedaton Ternate disebut pula sebagai Ternate ma-loko, dan kedaton Tidore disebut Tidore ma-loko, dsb. Selanjutnya Van Fraassen meluaskan interpretasinya dengan mengemukakan bahwa mungkin istilah loko di Maluku Utara itu mengandung makna yang sama dengan kata loka di Jawa.
Mungkin berakar pada kata Sansekerta itu, yang berarti tempat atau bumi. Kalau argumentasi itu benar, maka ma-loko bisa dikatakan mengandung arti yang sama dengan arti yang diberikan dalam tradisi kekuasaan di Jawa. Maka dengan demikian Maloko atau Maluku berarti penguasa dunia.
Karena setiap raja di Maluku, baik Ternate, Tidore, Bacan, maupun Jailolo, menggunakan istilah maloko sebagai bagian dart gelar kebesarannya, maka dengan sendirinya ini berarti bahwa setiap raja atau sultan tersebut adalah ‘penguasa dunia’.
Namun berbeda dengan di Jawa, kehadiran empat penguasa dunia di Maluku Utara justru merupakan kelaziman. Interaksi antara mereka diatur sedemikian rupa sehingga konflik-konflik yang menghancurkan bisa dihindari. Inilah makna pokok dart ideologi Maloko Kie Raha (Maluku Empat Gunung) yang membenarkan adanya konfederasi tersebut.
Argumentasi dari Van Fraassen memang menarik, kecuali satu hal. Belum ada seorang ahli linguistik yang mempelajari bahasa-bahasa di Maluku Utara berkesimpulan bahwa dalam bahasa-bahasa di wilayah itu terdapat pengaruh bahasa Sansekerta.
Sebab itu agak sulit kita membuat loncatan pemikiran dengan mengatakan bahwa loko mengandung arti yang sama atau hampir sama dengan loka. Namun tekanan pada Maloko Kie Raha sebagai ideologi yang mempersatukan kerajaan-kerajaan di Maluku Utara, terutama sebelum VOC menjadi dominan dalam abad ke-17, adalah suatu kesimpulan yang didukung oleh banyak fakta.
Penelitian lebih lanjut mengenai kebahasaan barangkali bisa membuka jalan ke arah penjelasan mengenai arti kata Maluku itu. Kamus bahasa Sahu yang disusun oleh Visser dan Voorhoeve, tidak mencantumkan kata loko. (Visser & Voorhoeve : 1987).
Wilayah Maluku yang sekarang ini luasnya kurang lebih 900 km2 , umumnya terdiri atas pulau-pulau vulkanis atau pulau-pulau karang yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung, sehingga tidak terdapat dataran rendah yang luas seperti di Sulawesi atau di Pulau Jawa.
Bagaimana kondisi wilayah ini pada beberapa abad yang lalu terutama pada masa-masa Emporium sampai masa Imperium, belum ada penelitian yang mendalam dan akurat. Akan tetapi dengan adanya beberapa penulisan dari abad ke 16–18 dapat disimpulkan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi atas topografi kepulauan ini.
Kalau pun ada perubahan itu tidak berarti. Di pulau-pulau yang dapat dikatakan besar seperti Halmahera, Morotai, Obi, Taliabu, Seram, Buru, Aru dan Tanimbar ada juga dataran-dataran rendah yang relatif cukup luas. Sedang pulau-pulau yang tidak terlalu luas berfungsi sebagai pelabuhan-pelabuhan transit, bahkan pernah berjaya sebagai bandar kecil maupun bandar dagang yang ramai di masa lalu.
Pulau-pulau Ternate, Tidore, Bacan, Makian, Sula, Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, Banda, Kei, Luang, Babar, Wetar, dan Damar pemah tercatat sebagai pulau-pulau yang menghasilkan komoditi tertentu yang dibutuhkan manusia sampai di Eropa.
***
—