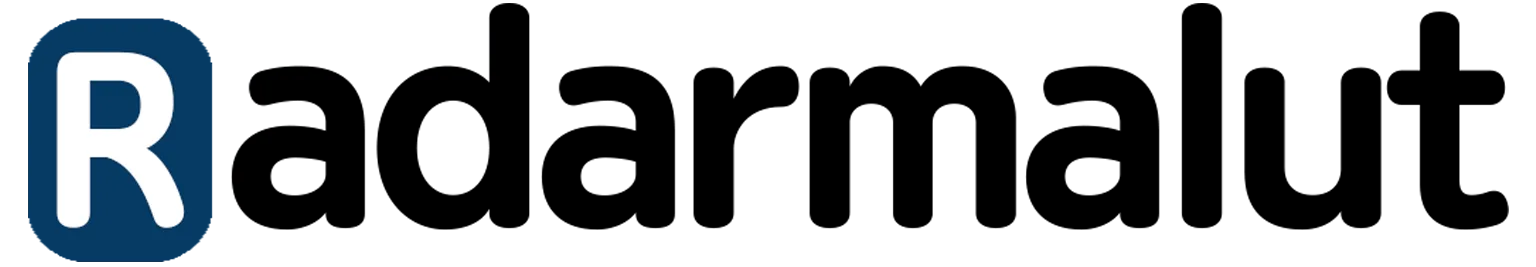Di Morotai, banyak anak sudah bisa “membaca bunyi”, tetapi memahami isi bacaan dan memecahkan soal yang sedikit lebih rumit masih menantang. Di saat yang sama, sekolah-sekolah bergerak menata kelas yang inklusif, aman dari kekerasan, dan relevan dengan kehidupan pesisir.
Inilah mengapa praktik baik integrasi literasi–numerasi dengan mainstreaming Gedsi, iklim, dan perlindungan anak terasa pas dan siklus “full cycle” (pelatihan, pendampingan, penganggaran, monitoring) menjadi mesin yang membuatnya menyala terus, bukan sekadar proyek musiman.
Mengapa integrasi ini penting?
Anak belajar paling kuat ketika tiga hal bertemu: materi yang dekat dengan keseharian, kelas yang aman dan ramah, serta guru yang mengecek pemahaman secara sederhana tetapi rutin. Di Morotai, konteks pesisir-ikan, pasar, cuaca, mangrove, memberi bahan baku kaya untuk teks bacaan bermakna dan soal numerasi kontekstual.
Saat anak diajak menghitung selisih hasil tangkapan atau membaca teks pendek tentang menjaga pantai, literasi dan numerasi bukan lagi mata pelajaran yang “terpisah”, melainkan cara memecahkan persoalan yang mereka kenal.
Integrasi ini juga memastikan tidak ada anak yang tertinggal: pendekatan pembelajaran yang responsif gender dan disabilitas (Gedsi) membuat kelas punya banyak “pintu masuk”; dengan gambar, benda konkret dan teks sederhana.
Kemudian, kompleks, dan kesempatan menjawab lewat lisan, tulisan, atau karya. Ditambah mekanisme perlindungan anak yang jelas, anak merasa aman untuk mencoba, salah, lalu mencoba lagi.
Dari pendampingan di lapangan, kemampuan dekoding dan beberapa fondasi numerasi telah menguat. Guru makin rapi menulis tujuan belajar, mengelola kelas, dan menggunakan perangkat ajar KREASI. Di sisi lain, pemahaman bacaan dan operasi hitung yang lebih kompleks masih perlu dorongan.
Asesmen formatif singkat (exit ticket 3-5 menit) belum menjadi kebiasaan harian, media lokal belum diproduksi massif, sementara kelembagaan perlindungan anak, seperti struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kanal aduan aman, di sebagian sekolah masih tahap awal. Di sinilah full cycle memainkan peran kunci.
Bayangkan sebuah siklus 6-8 minggu. Di minggu pertama, guru melakukan asesmen diagnostik ringan untuk memetakan kemampuan. Kepala sekolah dan guru menyepakati tujuan sederhana, misalnya semua siswa mampu memahami paragraf 57 kata dan menyelesaikan soal selisih dengan bilangan dua digit.
Minggu-minggu berikutnya, guru menerapkan pembelajaran terdiferensiasi: kelompok yang sudah lancar diarahkan ke tugas menantang; yang masih kesulitan mendapat dukungan berbasis UDL (Universal Design for Learning) lebih banyak gambar, benda nyata, bacaan singkat berulang.
Setiap pertemuan ditutup cek pemahaman cepat. Setiap dua minggu, tim bertemu dalam Professional Learning Community (PLC)/Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk membahas data kelas dan menukar bahan ajar kontekstual.
Di akhir siklus, capaian dirangkum dan diintegrasikan ke Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS): membeli bahan bacaan lokal, membuat kartu bilangan bertema pesisir, atau membiayai pelatihan mikro.
Monitoring tidak berhenti pada nilai ujian; sekolah memiliki dashboard sederhana berisi tiga indikator: keterbacaan teks, ketepatan operasi hitung, dan kehadiran/keamanan kelas. Dengan pola ini, praktik baik literasi-numerasi + Gedsi/iklim/perlindungan anak, bukan poster di dinding.
Ia hidup karena ada ritme: diagnostik, aksi, cek, refleksi, penganggaran, imbas. Setiap putaran membuat sekolah lebih terampil, dan anak-anak lebih percaya diri.
Benang merah di antara dua praktik baik
Pertama, tujuan keduanya sama, meski perannya berbeda. Integrasi literasi–numerasi dengan isu lintas adalah “isi” yang menghidupkan pembelajaran di kelas, sementara full cycle adalah “wadah” yang memastikan isi itu berjalan konsisten, terukur, dan dibiayai.
Kedua, keduanya bertumpu pada data sebagai kompas. Integrasi membutuhkan bukti untuk memilih strategi, misalnya fokus pada pemahaman, bukan sekadar kelancaran, sedangkan full cycle memastikan Rapor Pendidikan dan asesmen kelas benar-benar dibaca, dibahas, dan diterjemahkan menjadi keputusan harian.
Ketiga, keduanya meletakkan keamanan dan inklusi sebagai prasyarat belajar. Integrasi menuntut ruang aman agar semua anak berani mencoba; full cycle menempatkan TPPK, SOP, dan kanal aduan ke dalam rutinitas sekolah sehingga perlindungan bukan aksesori, melainkan bagian dari manajemen mutu.
Keempat, keduanya menghadirkan imbas yang terstruktur. Integrasi melahirkan contoh pengajaran yang efektif; full cycle memastikan contoh itu menyebar melalui KKG/KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan menjadi kebiasaan lintas sekolah, bukan sekadar praktik bagus di satu titik.
Dari sisi Dinas Pendidikan, kunci pertama adalah menstandardkan siklus 6-8 minggu sebagai pola pembinaan sekolah. Rapat data bulanan yang ringkas namun fokus perlu menjadi rutinitas, dengan dukungan anggaran BOS/BOP (Bantuan Operasional Sekolah-Bantuan Operasional Satuan Pendidikan).
Untuk bahan ajar lokal serta pelatihan mikro yang tepat sasaran. Di saat bersamaan, Dinas perlu memastikan TPPK di semua sekolah bekerja nyata; struktur jelas, alur rujukan tertulis, dan kanal aduan aman yang terlihat.
Dari sisi kepala sekolah, keberhasilan sangat ditentukan oleh kepemimpinan harian: menjadwalkan coaching mikro mingguan selama 15 menit dengan fokus pada tujuan, strategi diferensiasi, dan exit ticket; membuat kontrak belajar 6-8 minggu dengan guru yang memuat target spesifik, bukti sederhana, dan perayaan kecil saat tercapai; serta mengelola PLC/KKG yang berbasis data nyata, bukan asumsi.
Dari sisi guru, inti perubahan ada pada kelas. Konteks Morotai; ikan, perahu, pasar, hujan, ombak, perlu menjadi panggung belajar yang konkret dalam bahan bacaan dan soal numerasi. Kebiasaan asesmen formatif ringan di akhir pelajaran harus dijaga agar rencana esok hari selalu ditopang informasi segar.
Dan yang tak kalah penting, variasikan cara menjelaskan dan cara siswa menunjukkan pemahaman-lisan, tulisan, gambar, agar setiap anak punya jalan masuk.
Dari sisi orang tua dan komunitas, dukungan sederhana tetapi berpengaruh besar: menyumbang cerita lokal untuk bacaan kelas, mengajak anak berhitung dari aktivitas harian, serta turut menjaga lingkungan belajar yang aman dengan mengenali dan menggunakan kanal aduan jika ada potensi kekerasan.
Dari sisi mitra atau organisasi, kontribusi paling terasa adalah membantu produksi bahan ajar kontekstual dan menyelenggarakan pelatihan mikro yang adaptif, termasuk mendukung model Unit Layanan Disabilitas (ULD) bergerak untuk sekolah-sekolah terpencil.
Mengapa ini layak diperluas?
Karena pendekatannya sederhana sekaligus sistematis. Ia tidak bergantung pada pelatihan besar yang cepat terlupa, melainkan kebiasaan kecil yang diulang. Ia inklusif karena ruangnya luas: anak dengan disabilitas, anak dengan bahasa ibu yang berbeda, anak yang perlu waktu lebih semuanya mendapat tempat.
Ia relevan karena berpijak pada laut, pasar, dan budaya setempat. Dan yang paling penting, ia terukur; setiap siklus membawa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. “Pendidikan inklusif adalah cara paling efektif untuk memberi semua anak kesempatan adil bersekolah dan belajar.”: (UNICEF).
Morotai sudah memulai. Tugas kita sekarang adalah menjaga ritme dan memperluas jangkauan. Ambil satu sekolah yang tertinggal jadikan prioritas putaran pertama. Siapkan bahan ajar lokal sederhana.
Jalankan exit ticket setiap hari. Adakan rapat data 30 menit tiap bulan. Buka kanal aduan yang ramah anak. Ulangi. Sebulan kemudian, pindah ke sekolah berikutnya.
Jika setiap pemangku kepentingan mengambil satu bagian kecil dari siklus ini, kita akan melihat peta yang berubah: lebih banyak sekolah aman, lebih banyak anak paham, lebih banyak guru percaya diri. Dari Morotai untuk Indonesia; kelas aman, anak hebat bukan slogan, melainkan kebiasaan yang direplikasi. Mari mulai hari ini.
***
—
Welhelmus Poek Konsultan Monitoring Dampak Program KREASI