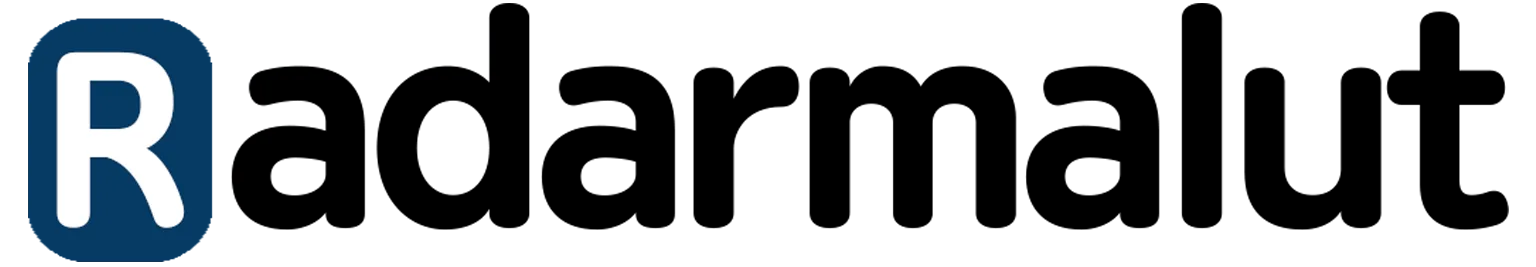Bocornya data Harita Group yang sempat diakses dan dipublikasi oleh sejumlah media luar negeri pada April 2025, ternyata tidak hanya membuka lapisan baru dari persoalan tambang di Maluku Utara.
Selain dokumen-dokumen terkait dampak lingkungan, data yang bocor juga mencakup proposal kerja sama antara Harita dan sejumlah institusi perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Khairun (Unkhair) Ternate–yang tampak paling banyak mengajukan proposal kerja sama sepanjang 2019-2022 di bidang riset, pengembangan sumber daya manusia, hingga sosial ekonomi.
Keterlibatan Unkhair dengan Harita lewat lembaran-lembaran dokumen yang bocor itu, memperlihatkan betapa intensnya komunikasi antarkedua entitas yang berbeda itu. Bahkan, sejumlah organisasi mahasiswa yang terlibat, baik formal maupun informal, memperlihatkan kesan ketergantungan yang cukup signifikan terhadap perusahaan yang merelokasi satu perkampungan (dari Kawasi ke Ecovillage) itu.
Di Halmahera Tengah, warga Desa Sagea sempat mencegat tim yang diutus oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada awal Juli 2024. Tim itu terdiri dari mahasiswa dan dosen.
Mereka berasal dari beberapa perguruan tinggi di Kota Ternate. Kabarnya, mereka ditugaskan mensosialisasikan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), terkait rencana perluasan kawasan industri.
Tentu penolakan warga bukan karena mereka anti-akademik. Tapi mereka tahu, bahwa kampus sedang dipakai sebagai alat legitimasi–seolah-olah partisipasi warga bisa dibeli dengan presentasi dan absensi.
Keterlibatan kampus dalam proses AMDAL jelas bukan hal netral. Ia adalah bagian dari strategi korporasi untuk membungkam resistensi dan menciptakan kesan, bahwa proyek tambang telah mendapat restu ilmiah.
Mahasiswa dan dosen yang seharusnya berpihak pada kebenaran dan keadilan ekologis, justru dijadikan alat komunikasi perusahaan. Ini adalah bentuk kolonisasi ruang akademik oleh kepentingan modal.
Warga Sagea menolak karena mereka tahu, bahwa sosialisasi tanpa pemulihan adalah pengkhianatan. Mereka tidak butuh penjelasan teknis tentang dampak tambang, sebab mereka sudah merasakan.
Jelas fenomena ini bukan sekadar soal “kemitraan.” Ia adalah cerminan dari bagaimana kampus–yang seharusnya menjadi ruang kritis dan independen–perlahan-lahan digiring menjadi mitra legitimasi industri ekstraktif.
Di tengah konflik agraria, kriminalisasi warga, dan krisis ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, kerja sama semacam ini justru memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara ilmu pengetahuan dan kepentingan modal.
Ketika kekuasaan bisa ikut menekan integritas di ruang-ruang akademik, kampus kemudian menghadapi dilema serius: berisiko menciptakan konflik kepentingan yang merusak independensi akademik.
Sebab, bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan melakukan riset dampak lingkungan secara objektif, jika dananya berasal dari perusahaan yang sedang dikaji? Bagaimana mungkin mahasiswa bisa bebas menyuarakan kritik, jika kampus atau organisasinya menjalin relasi atau menjadi mitra korporasi yang sedang ditentang masyarakat?
Atas nama riset, pengabdian masyarakat, atau peningkatan kapasitas, institusi pendidikan tinggi, riset-riset lingkungan bisa kehilangan objektivitas, forum-forum ilmiah bisa berubah menjadi panggung promosi korporasi, dan mahasiswa bisa kehilangan ruang aman untuk bersuara.
Kontrak kerja sama antara kampus dan perusahaan tambang tidak bisa dilihat sekadar urusan administratif. Ia adalah pernyataan politik. Sebab, di banyak wilayah, termasuk Maluku Utara–tambang bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah soal kekerasan, penggusuran, kriminalisasi, perampasan, dan kehancuran ekologis.
Ketika kampus memilih diam atau bahkan ikut serta dalam proyek-proyek tambang, ia sedang mengkhianati mandatnya sebagai ruang produksi pengetahuan yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Karena kampus bukan biro konsultan atau perpanjangan tangan korporasi.
Kampus adalah ruang publik, yang semestinya menjaga nalar kritis dan keberpihakan pada keadilan ekologis. Ketika kampus mulai menukar integritasnya dengan dana CSR atau proposal kerja sama, maka ia sedang menggali lubang bagi kehancurannya sendiri.
Dalam situasi ini, jika kampus tidak segera mengambil sikap tegas, maka ia berisiko kehilangan kepercayaan publik, kehilangan independensi ilmiah, dan kehilangan fungsinya sebagai benteng terakhir akal sehat.
***