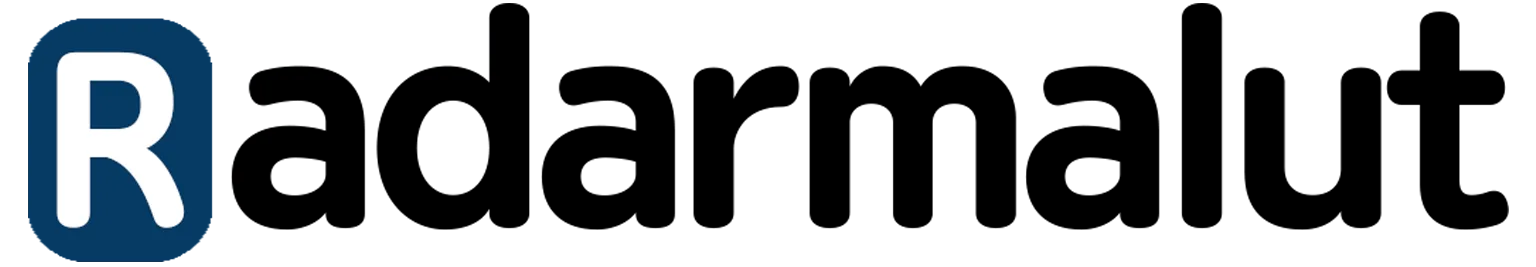Air di Aceh dan Sumatera Utara beberapa tahun ini tidak lagi sekadar hujan; ia menjadi kabar duka yang turun dari langit. Sungai-sungai yang dulu menjadi wajah tenang kampung, kini berubah menjadi lorong lumpur yang menggeret batang-batang pohon raksasa.
Pohon yang selama puluhan tahun berdiri sebagai rumah bagi burung, embun, dan harimau. Kini mereka hanyut seperti mayat sejarah, terseret deras tanpa bisa protes.
Ia adalah cermin dari kerakusan manusia: kerakusan yang berdandan sebagai pembangunan, disahkan oleh tanda tangan para elite dan dipuji dalam laporan investasi yang jauh dari wajah rakyat yang tinggal di hulu dan tepian sungai.
Jika air memiliki ingatan, maka banjir kali ini adalah arsip kemarahan yang menumpuk tahun demi tahun ketika batang-batang pohon raksasa ditebang, bukit dibelah dan hutan diperlakukan seperti tambang uang yang bisa digadaikan kapan saja. Bencana itu, dilahirkan oleh Keputusan di Ruang Ber-AC.
Dalam Political Ecology: A Critical Introduction (Paul Robbins, 2012), terdapat tesis yang tak bisa kita tolak: bencana ekologis adalah produk keputusan politik dan ekonomi yang timpang. Banjir tidak jatuh dari langit tanpa sebab.
Ia lahir dari struktur kuasa yang memberi izin tambang pada mereka yang tak pernah menjejakkan kaki di desa yang terdampak, yang tak pernah tidur di rumah kayu di pinggir sungai dan yang tak pernah mendengar suara tanah retak setelah hujan.
“Ketika hutan ditebang atas nama pendapatan, maka banjir bukanlah bencana alam. Ia adalah laporan keuangan dari kerakusan manusia.”
Kerusakan hutan di Aceh dan Sumut tidak terjadi karena ketidaktahuan. Ia terjadi karena kehendak, karena pilihan sadar untuk memberi ruang pada modal tanpa memberi ruang pada rakyat.
Pendapatan daerah dijadikan alasan, tapi angka-angka itu tak pernah menetes menjadi kesejahteraan. Justru masyarakat kecil yang menanggung utang ekologis paling besar: rumah hanyut, ladang hilang dan masa depan anak-anak mereka diseret oleh arus yang seharusnya bisa dicegah.
Keuntungan segelintir, kerugian publik
Di balik deforestasi yang membabi buta, selalu ada garis yang jelas: keuntungan terkonsentrasi pada segelintir orang, kerugian didistribusikan pada rakyat banyak. Inilah paradoks pembangunan di banyak wilayah Indonesia: laba mengalir ke kota, bencana mengalir ke desa.
Di Aceh, IUP (izin usaha pertambangan) tumbuh lebih cepat daripada pohon yang ditebang. Di Sumatera Utara, perkebunan dan perusahaan kayu menjadi pilar ekonomi yang dibanggakan, tapi rakyat di sepanjang DAS justru menjadi penjaga terakhir ketika banjir datang.
Parahnya, mereka yang paling menderita bukanlah mereka yang menerima keuntungan dari rusaknya hutan, melainkan mereka yang sejak awal tidak pernah dimintai pendapat. Negara, dalam konsep idealnya, adalah penjaga hutan dan air.
Tapi dalam praktiknya, negara justru berubah menjadi pengizinnya. Atas nama pendapatan, legalitas dijual kepada yang mampu membayar dan pengawasan dilemahkan oleh alasan birokrasi: kurang anggaran, kurang personel, atau alasan klasik “masih dalam evaluasi”.
Padahal kegagalan itu bukan teknis, ia struktural. Negara tidak buta. Ia hanya memilih untuk melihat ke arah lain. Ketika kejahatan ekologis berlindung di balik laporan PAD, keberanian politik untuk membela lingkungan sering kali hilang begitu saja.
Dan pada akhirnya, rakyat kecil yang memikul konsekuensinya, sementara elite tetap berdebat di meja rapat yang bersih dari lumpur, jauh dari banjir dan tidur nyenyak di rumah mewah di Jakarta saat hujan deras.
Dalam bayang-bayang Maluku Utara: Apa yang terjadi di Aceh dan Sumut bukan tragedi lokal. Ia adalah gambaran masa depan bagi daerah-daerah lain yang sedang meniru model ekonomi yang sama, termasuk Maluku Utara.
Di pulau-pulau kecil yang rapuh secara ekologis, dari Halmahera Utara hingga Obi, dari Halmahera Timur hingga Weda, deforestasi dan penambangan nikel berjalan dengan kecepatan yang menyaingi kerakusan. Sungai-sungai mulai keruh, sedimentasi meningkat, dan wilayah pesisir menerima limpahan lumpur dari bukit yang digunduli.
Jika model yang sama terus dipertahankan, mengorbankan hutan demi investasi, lapangan kerja dan pendapatan: maka Maluku Utara hanya menunggu giliran. Bukan apakah banjir besar akan datang, tetapi kapan ia datang. Jadi mencintai hutan bukan tindakan romantik kaum idealis.
Ia adalah tindakan realistis untuk menjaga masa depan. Hutan adalah bendungan alami, pelindung tanah, penyaring air, penyangga kehidupan. Ketika ia dirusak, negara tak punya infrastruktur yang sekuat akar, tak punya teknologi seandai humus dan tak punya mekanisme yang setangguh ekosistem alami.
Aceh dan Sumut telah memperlihatkan harga dari ketamakan. Kita hanya perlu bertanya: Apakah Maluku Utara ingin membayar harga yang sama?
Atau kita akan kembali berlindung di balik retorika pendapatan dan investasi, hingga satu hari nanti, air datang menyapu desa dan kita terlambat untuk belajar bahwa hutan adalah satu-satunya tabungan ekologis yang tidak bisa kita ganti ketika sudah hilang.
***