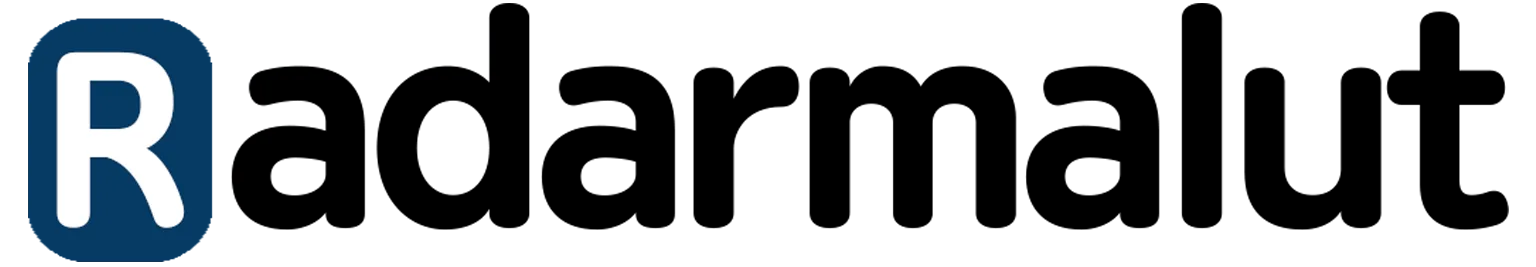Dalam setiap perjalanan sejarah, selalu ada momen ketika sebuah simbol terancam kehilangan makna, kemudian dihidupkan kembali oleh tangan-tangan yang peduli. Stadion Gelora Kie Raha adalah simbol itu. Ia tidak hanya sekadar lapangan hijau, tetapi ruang perjumpaan, medan identitas dan altar kebanggaan masyarakat Maluku Utara.
Namun, siapa yang bisa membantah bahwa bertahun-tahun stadion ini dibiarkan terbengkalai? Rumput mengering, tribun dipeluk semak belukar, bahkan fasilitas yang dibangun negara pun menjadi saksi bisu dari abainya kita menjaga rumah sendiri.
Kisah ini berubah ketika Malut United FC klub hasil akuisisi Putera Delta Sidoarjo, membawa pulang asa ke Ternate. Kehadiran klub itu ibarat gelombang baru yang menggoyang pantai lama, membangunkan kesadaran bahwa sepak bola bukan sekadar pertandingan, melainkan suatu kebanggaan dan narasi kebudayaan.
Maka, renovasi Gelora Kie Raha tidak bisa dipandang semata proyek fisik, tetapi rekonstruksi harga diri kolektif. Dengan dana pribadi atau perusahaan dan tekad kuat, tribun dibersihkan, rumput diperbaiki, lampu stadion dipasang dan akhirnya Gelora Kie Raha berdiri kembali, memenuhi syarat sebagai salah satu venue resmi Liga I.
Namun, sejarah selalu penuh ironi. Justru ketika stadion ini kembali bernyawa, polemik muncul. Saling klaim kepemilikan menggema, tudingan pelanggaran hukum dihembuskan dan ruang publik kembali dipenuhi pertengkaran. Pertanyaan mendasar yang diajukan Wakil Manajer Malut United FC Asghar Saleh menjadi relevan.
“Di mana para pihak yang berpolemik saat Gelora Kie Raha bertahun-tahun tak terurus.” Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan gugatan moral yang menyentuh inti keberpihakan.
Polemik semacam ini sesungguhnya mengungkap wajah lama birokrasi olahraga di negeri ini. Kita terlalu sering sibuk dengan formalitas administratif, tetapi lalai menjaga substansi. Padahal, publik sebetulnya hanya ingin menyaksikan sepak bola di rumah sendiri.
Kemudian, bersorak di tribun dan merasa bahwa Ternate bukan kota penonton, melainkan tuan rumah yang dihormati. Sepak bola adalah milik rakyat, bukan sekadar milik pihak yang mencatat namanya di atas kertas.
Dalam literatur politik olahraga, Simon Chadwick menyebut bahwa sepak bola selalu lebih besar dari sekadar olahraga; ia adalah ‘a soft power in motion’ kekuatan lunak yang bergerak, mengikat emosi, ekonomi, bahkan identitas sebuah bangsa atau daerah.
Renovasi Gelora Kie Raha adalah bentuk soft power itu–mengangkat Maluku Utara ke peta nasional, menghadirkan kebanggaan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Bahkan, jika ditarik ke belakang, sepak bola selalu menjadi simbol kebangkitan masyarakat di banyak tempat.
Di Amerika Latin, klub-klub sepak bola lahir dari komunitas kelas pekerja yang ingin diakui. Di Eropa Timur, stadion menjadi ruang artikulasi perlawanan terhadap rezim otoriter.
Maka, ketika Malut United pulang ke Ternate dan menghidupkan kembali Gelora Kie Raha, sesungguhnya ia mengulang sejarah universal: olahraga sebagai bahasa perlawanan terhadap keterbelakangan dan abainya pemerintah setempat dan negara.
Namun di balik semua ini, ada mimpi yang jauh lebih besar dari sekadar renovasi stadion. Ada mimpi bahwa dari Gelora Kie Raha akan lahir sepak bola Maluku Utara yang berkelas nasional dan dunia. Mimpi menjadikan Maluku Utara sebagai episentrum baru sepak bola Indonesia, tempat di mana gairah rakyat dan profesionalisme bertemu dalam satu tarikan napas.
Mimpi itu melahirkan visi tentang sebuah akademi sepak bola yang modern dan berstandar internasional. Akademi yang suatu hari akan mengorbitkan anak-anak pesisir Tobelo, Morotai, Ternate, Tidore, Halmahera hingga Taliabu menjadi bintang yang bersinar.
Seperti bagaimana Inggris membangun fondasi lewat football academy system, atau bagaimana Brasil, Argentina dan Jerman melahirkan generasi emas lewat pembinaan yang terstruktur. Gelora Kie Raha bisa menjadi jendela masa depan itu.
Di titik ini, mari kita jujur: pembangunan sepak bola bukan pekerjaan sehari dua. Ia butuh visi panjang, konsistensi, dan dukungan penuh masyarakat. Tetapi bukankah sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani bermimpi?
Maka, mari kita berpihak pada mereka yang peduli, mereka yang tidak hanya datang membawa modal, tetapi juga membawa visi tentang harga diri dan peradaban sepak bola Maluku Utara. Kita harus ingat bahwa sepak bola bukan sekadar hiburan, melainkan ruang pendidikan karakter.
Stadion yang terawat bukan hanya tempat orang berlari dan berteriak, tetapi juga tempat anak-anak belajar arti disiplin, sportivitas, kerja sama, dan mimpi. Gelora Kie Raha yang direnovasi dengan cinta dan tekad besar adalah sekolah kehidupan, di mana rakyat belajar tentang arti memiliki rumah bersama.
Antonio Gramsci pernah mengingatkan, hegemoni lahir bukan hanya dari kekuatan politik, melainkan dari keberhasilan menciptakan makna yang diterima masyarakat. Gelora Kie Raha yang direnovasi, dirawat, dan dijadikan rumah Laskar Kie Raha adalah wujud hegemoni baru itu.
Hegemoni kebanggaan, yang menyatukan rakyat Maluku Utara dari Morotai hingga Taliabu, dari Halmahera Timur hingga Barat. Maka, judul ‘Pulang ke Kie Raha, Pulang untuk Kebanggaan Maluku Utara’ tidak sekadar rangkaian kata yang manis, melainkan pernyataan sikap.
Ia mengingatkan kita bahwa yang dipertaruhkan tak hanya lapangan dan tribun, melainkan martabat sebuah daerah. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan pernah membiarkan Gelora Kie Raha kembali terbenam dalam semak-semak lupa.
“Rumput yang hijau tak pernah menanyakan siapa pemiliknya, ia hanya ingin tumbuh agar manusia bisa berlari dan merayakan mimpi di atasnya.”
***