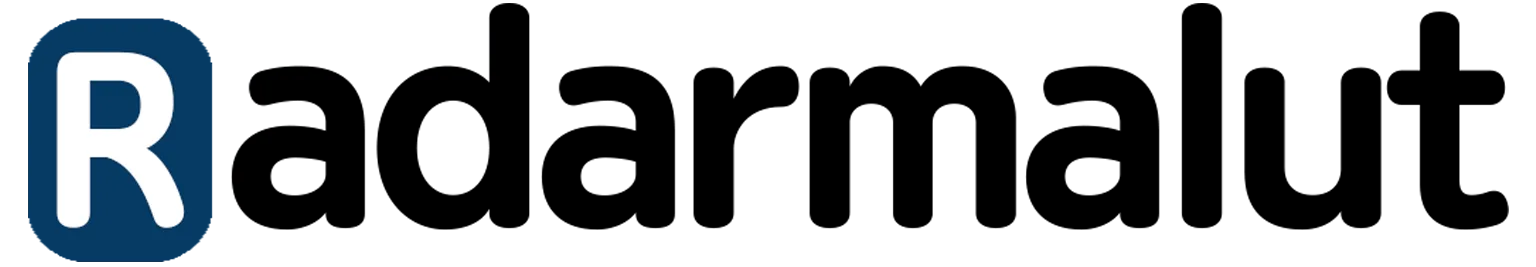“Sebuah ibu kota bukan sekadar sebuah tempat, ia adalah cermin jiwa suatu bangsa.” Saskia Sassen, ahli tata ruang global, Columbia University.
Bukankah Sofifi adalah milik kita bersama. Sebuah tanah yang menyimpan ingatan sejarah dan sekaligus harapan masa depan? Penolakan terhadap pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi tak berdasar jika dilihat dari sisi legitimasi wilayah, kepentingan rakyat, maupun sejarah penetapannya sebagai ibu kota Maluku Utara.
Kita mendambakan Sofifi segera menjadi kota madya, namun dengan cara yang berakar pada nilai kebudayaan dan adat setempat. Justru itulah alasan kenapa kesultanan dan pemerintah provinsi harus duduk bersama, bukan saling menolak.
Ketika kesultanan secara terburu-buru menyatakan sikap “menolak”, maka itu bukanlah pantulan kebijaksanaan adat, melainkan sebuah langkah keliru yang menjauh dari semangat rekonsiliasi. Ibu kota provinsi tidak seharusnya bergantung pada keinginan politik sesaat dari kabupaten induk.
Ketika Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota, maka secara otomatis ia telah melepaskan dirinya dari subordinasi administratif. Mengapa kemudian pemekarannya harus kembali meminta izin seperti seorang anak yang ketakutan?
Ini bukan soal legalitas semata, tetapi soal keberanian kita untuk mengakui bahwa Sofifi sudah menjadi pusat gravitasi pemerintahan yang sah. Menolak pemekaran justru mencederai logika otonomi dan semangat pemerataan pembangunan.
Seperti yang dikatakan Prof. Ryaas Rasyid, arsitek otonomi daerah Indonesia:-“otonomi bukan pemberian belas kasihan, tapi pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengelola dirinya sendiri.”
Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa harus takut jika Sofifi tumbuh dan mandiri? Bukankah kota madya yang dibangun atas dasar budaya akan lebih tahan uji dibanding yang dibangun atas dasar kompromi politik sempit?
Sofifi bukan milik segelintir birokrat, bukan pula simbol kekuasaan kabupaten tertentu. Ia adalah milik seluruh rakyat Maluku Utara. Menolaknya berarti menolak tumbuhnya kesadaran baru dalam tubuh provinsi ini;–kesadaran bahwa masa depan harus dirajut bersama, bukan dikuasai oleh narasi sempit.
Jika kita menengok sejarah, kota-kota besar di Indonesia seperti Palangka Raya, Jayapura, hingga Ambon pernah melalui fase-fase penyangkalan serupa.
Namun sejarah selalu memihak pada tempat yang berani menentukan nasibnya sendiri. Menjadikan Sofifi sebagai kota madya adalah bagian dari koreksi sejarah, dan juga bentuk tanggung jawab kita terhadap masa depan.
Kota ini tidak boleh terus menjadi “ibu kota bayangan”, hidup tanpa struktur, tanpa arah dan pengakuan yang semestinya. Lagi pula, pembangunan tidak bisa digantungkan terus-menerus pada niat baik pemerintah provinsi semata. Ia butuh kemandirian dan legalitas.
Lucunya, pernah ada seorang wisatawan asing tujuannya ke Morotai, ia melintasi Halmahera–pertama kali melihat Sofifi dan bertanya pada sopir “Ini betul ibu kota provinsi Maluku Utara? Kok saya rasa seperti ibu kota yang belum nikah.”
Pak sopir dan beberapa penumpang tertawa. Tapi sebenarnya itu tawa getir. Ia tidak sepenuhnya salah. Sofifi selama ini seperti jodoh yang dijanjikan tapi tak kunjung dinikahi. Sudah dibawa ke rumah orang tua (pemerintah pusat), sudah dikenalkan ke tetangga (masyarakat), tapi belum juga dibuatkan surat sah secara administratif.
Tanpa otoritas kewilayahan yang sah, Sofifi akan terus berada dalam wilayah abu-abu. Terlalu penting untuk diabaikan, tetapi terlalu kompleks untuk disentuh.
Menjadikannya kota madya adalah cara untuk memberi rumah hukum, struktur birokrasi dan arah perencanaan yang lebih jelas bagi seluruh warganya. Ini bukan kehendak satu dua orang, tapi desakan kolektif yang datang dari akar rumput hingga ruang akademik.
Ahli Demokrasi, Prof. Robert Dahl menjelaskan demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi yang merata dan otonomi yang diakui. Jadi, penolakan terhadap pemekaran Sofifi bukan hanya mengekang potensi administratif, tetapi juga memadamkan semangat partisipatif masyarakat yang ingin membangun kotanya dengan tangan sendiri.
Dalam konteks Maluku Utara, ini berarti mengubur energi generasi muda, kaum adat, tokoh agama dan masyarakat sipil yang telah lama merindukan arah yang jelas bagi kota ini. Jika narasi pembangunan hanya diisi oleh ketakutan akan kehilangan kuasa, maka kita sedang membangun tembok, bukan jembatan.
Kita tidak membutuhkan ibu kota yang diam dan menunggu nasib. Kita membutuhkan Sofifi yang hidup, yang memiliki pemerintahan sendiri, yang mendengar denyut nadi rakyatnya. Sebab, kota bukan sekadar ruang administratif, tetapi panggung kultural dan rumah bersama.
“Sebuah ibu kota adalah denyut jantung peradaban. Bila ia dibiarkan menggigil dalam ketidakpastian, maka seluruh tubuh akan ikut menggigil.”
***