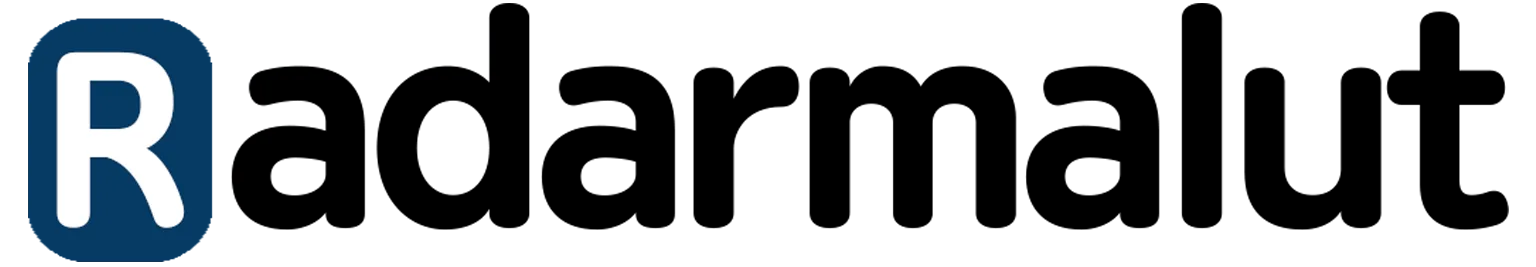“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia,” kata Nelson Mandela
Di timur negeri ini, ada gugusan pulau yang kaya tapi sering dilupakan. Maluku Utara, tanah di bibir Pasifik adalah rumah bagi kekayaan alam yang tak terbantahkan–lautnya melimpah ruah ikan, buminya mengandung nikel, emas, besi dan ragam mineral lainnya.
Tapi, di tengah kelimpahan itu, wajah rakyatnya menyimpan ironi yang pedih; kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan gelombang penggusuran atas nama pembangunan.
Negeri ini seolah dikepung oleh ironi yang dalam. Di satu sisi, laut yang luas itu bukan hanya sumber kehidupan, namun juga panggung perampokan yang sah–pencurian ikan oleh kapal asing, reklamasi yang membungkam kampung pesisir dan hilangnya hak nelayan kecil untuk melaut dengan tenang.
Di sisi lain, tambang-tambang besar menjanjikan hilirisasi, tapi justru melahirkan peminggiran–petani kehilangan tanah, anak-anak kehilangan sekolah dan kampung-kampung kehilangan masa depan.
Di tengah pusaran itu, pendidikan seharusnya menjadi jangkar. Tapi jangkar itu tampak longgar dan hampir putus. Di banyak pulau, anak-anak harus menyeberang laut demi sekolah, atau bahkan berhenti di tengah jalan karena guru tak datang, bangku belajar rusak atau biaya sekolah jadi beban keluarga.
Ironi pendidikan di Maluku Utara bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal kebijakan yang tak berpijak pada realitas geografis dan sosial yang dihadapi warga.
Menurut Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, “Kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, tapi ketiadaan kesempatan untuk hidup layak dan mengembangkan potensi.” Maka, tak heran jika di daerah kaya sumber daya seperti Maluku Utara, angka putus sekolah tinggi.
Karena meskipun tanah ini kaya, kesempatan tidak dibagi secara adil. Kekayaan justru menjadi dinding pemisah antara pusat kuasa dan pinggiran rakyat.
Kekayaan laut kita sering kali lebih banyak memberi makan dunia daripada memberi makan warga pesisir sendiri. Ikan-ikan kita dijual ke luar, tapi gizi anak-anak di pulau-pulau terpencil tetap rendah.
Program hilirisasi tambang dijual sebagai narasi kemajuan, tapi justru menghancurkan mata air, sawah dan ruang hidup masyarakat adat. Di sinilah urgensi mendesain ulang masa depan, bukan hanya dengan data statistik, tapi dengan hati dan akal sehat.
Sejarah panjang kolonialisme pernah menjadikan wilayah ini sebagai pusat rempah dunia. Namun kini, bentuk kolonialisme baru datang dalam rupa investasi yang tak berpihak. Tanah dijual murah, laut dibiarkan dan generasi muda diposisikan sebagai buruh kasar, bukan sebagai perancang masa depan.
Di mana pemerintah daerah saat kapal asing datang menyedot ikan? Di mana suara DPRD kabupaten dan provinsi ketika jalan-jalan tambang merobek tanah rakyat?
Konsep pembangunan nasional terlalu sering mengabaikan keunikan kawasan timur. Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau, seharusnya mendapat model pendidikan kepulauan dengan guru yang diberdayakan lokal, digitalisasi yang merata, dan sekolah berbasis laut dan tanah.
Tapi yang terjadi, dana BOS dan beasiswa justru dipotong, sementara proyek-proyek besar terus digelontorkan tanpa pelibatan warga.
Menurut Edward Said, “Imperialisme modern tidak selalu datang dengan senjata, tapi dengan kebijakan dan dokumen-dokumen.” Maka kita harus bertanya ulang;–siapa yang menulis dokumen-dokumen pembangunan itu?.
Apakah ia ditulis dari dalam dusun nelayan, dari kaki gunung, dari kampung adat yang terancam? Atau ditulis dari ruang-ruang dingin di Jakarta tanpa mendengar suara rakyat Halmahera Timur, Weda, Bacan, Obi atau Malifut dan Kao?.
Di tengah krisis ini, anak muda Maluku Utara harus menjadi bagian dari jawaban, bukan sekadar korban atau penonton. Gerakan literasi harus bersanding dengan advokasi.
Mahasiswa tak cukup hanya demonstrasi, tapi harus masuk ke ruang kebijakan, menjadi perancang undang-undang dan pelindung tanah leluhur. Jika pendidikan tak mengubah cara kita memandang masa depan, maka kita sedang gagal belajar dari sejarah.
Jika tambang hari ini hanya menjadi sumber kerusakan dan pemiskinan, maka tak ada pilihan lain–hentikan dan tiadakan saja tambang itu. Biarkan rakyat yang mengelolanya sendiri melalui tambang rakyat yang terorganisir, berkeadilan dan ramah lingkungan.
Karena emas dan nikel itu milik rakyat, bukan hanya korporasi. Kita bisa fokus membangun masa depan melalui industri pertanian lestari, yang menjaga tanah dan memberi makan anak negeri dengan layak dan mandiri.
Salah satu jalan keluar adalah menciptakan “Akademi Maritim dan Pertambangan Rakyat” sebuah sekolah tinggi berbasis lokal, yang menggabungkan ilmu kelautan, tambang berkelanjutan, dan keterampilan wirausaha yang berpihak pada anak-anak desa.
Pemerintah daerah juga perlu menyusun Peta Jalan Pendidikan Kepulauan, dengan distribusi guru berkualitas, beasiswa afirmatif dan digitalisasi merata yang menjangkau desa-desa pulau terluar.
Solusi lainnya adalah membentuk “Dewan Tanah dan Laut” di tingkat provinsi sebuah forum independen yang melibatkan tokoh adat, aktivis, akademisi dan nelayan untuk mengawasi setiap proyek yang menyentuh ruang hidup rakyat.
Jangan biarkan pembangunan bergerak tanpa panduan etika dan keadilan. Maluku Utara tak kekurangan sumber daya yang kurang hanya keberanian untuk menata ulang masa depan dengan cara yang bermartabat.
***