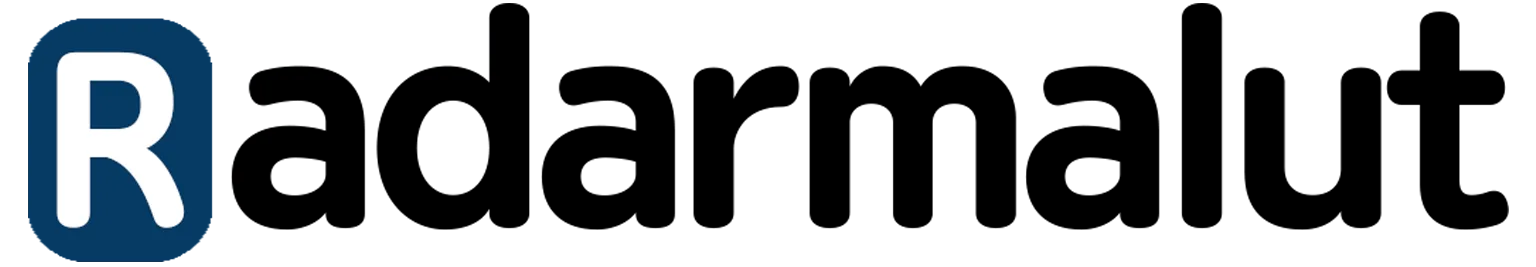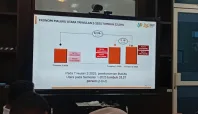“Tidak ada masyarakat yang statis. Pemekaran, perpindahan, dan pergeseran adalah bagian dari denyut sejarah manusia yang mencoba menemukan bentuknya yang paling adil.”–Anthony Giddens
Di atas tanah yang dahulu dibisiki angin Oba dan disapa gelombang Teluk, Sofifi berdiri seperti bayi yang tumbuh cepat, tetapi dibebani beban tua. Di satu sisi ia digadang sebagai ibukota provinsi, pusat administratif yang hendak menatap masa depan.
Di sisi lain, ia menjadi objek tarik-ulur kepentingan politik, wacana pembangunan dan identitas sosial yang rapuh. Pemekaran Sofifi dari Tidore tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif, tetapi menyimpan lapisan sosiologis, historis, dan politis yang rumit.
Para penolak pemekaran memiliki narasi yang kukuh dan bersandar pada sejarah panjang Tidore. Namun dari sisi lain, suara yang mendukung pemekaran Sofifi tak kalah kuat jika dilihat dalam kacamata sosiologis modern.
Sebuah wilayah yang ditunjuk sebagai ibukota pantas diberi kemandirian administratif agar mampu memaksimalkan pelayanan, pembangunan dan efisiensi pemerintahan. “Ketika wilayah tak memiliki kekuasaan memerintah atas dirinya sendiri, ia hanya menjadi semacam ‘posko besar’ tanpa otoritas,” tulis Manuel Castells dalam kajian tentang identitas dan kota.
Sofifi, meski telah berdiri dalam tubuh Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, masih menggantung dalam status yang remang-remang. Ia adalah ibukota provinsi yang ditumpangkan kepada wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Posisinya ibarat seorang anak yang diminta dewasa sebelum waktunya, namun tak diberi ruang untuk menentukan langkah sendiri. Perencanaan kota, penataan ruang, pengendalian sumber daya, hingga urusan paling dasar seperti pelayanan publik, semuanya masih diurus oleh ibu kandungnya, yakni Tidore.
Melihat dari sisi ini, pemekaran Sofifi sejatinya adalah bentuk koreksi atas kekosongan hukum dan ambiguitas kelembagaan yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Bila daerah ini tetap berada di bawah Tidore, maka setiap agenda pembangunan akan selalu mengalami friksi administratif.
Sementara roda pemerintahan provinsi terus berputar, realitas strukturalnya tetap tersandera. Dalam buku Democracy and the Global Order, David Held mengingatkan: “Demokrasi harus bekerja tidak hanya melalui prosedur, tetapi juga melalui efisiensi kelembagaan yang menjamin keadilan distributif dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.”
Maka pemekaran Sofifi–jika dipahami sebagai upaya memantapkan demokrasi lokal, harus dilihat sebagai bentuk ikhtiar untuk menciptakan tatanan kelembagaan yang lebih fungsional. Namun tentu, pemekaran bukanlah mantra mujarab yang otomatis menghadirkan kemajuan.
Ia ibarat membuka jalan baru ke gunung: menjanjikan puncak yang lebih dekat, tapi menghadirkan tanjakan yang terjal. Kita tidak sedang memperdebatkan perpisahan emosional antara Sofifi dan Tidore, melainkan bagaimana membangun struktur pemerintahan yang lebih mampu melayani rakyat secara langsung, adil dan efisien.
Tidore, dengan warisan sejarah dan kehormatan sebagai salah satu negeri adat tua di Nusantara, patut dihormati atas peran strategisnya dalam membidani lahirnya Sofifi. Tapi zaman bergerak. Cita-cita otonomi harus selalu diletakkan dalam kerangka keberfungsian negara dan kesejahteraan warga.
Bila mempertahankan status quo justru memperpanjang ketidakefisienan, maka kita harus jujur mengatakan bahwa perubahan adalah jalan rasional, bukan pengkhianatan sejarah.
Jika kita menarik pelajaran dari kota-kota administratif lain di Indonesia yang berhasil tumbuh karena kemandirian kelembagaan, seperti Palangkaraya, Mamuju atau Tanjung Selor, maka Sofifi bukan sedang menuntut hak istimewa, melainkan hak dasar: mengurus dirinya sendiri demi kebaikan yang lebih luas.
Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi Provinsi Maluku Utara yang membutuhkannya sebagai pusat gravitasi pelayanan publik. Wacana pemekaran harus menjauh dari trauma disintegrasi. Ia harus dibingkai sebagai upaya penyesuaian administratif terhadap realitas yang terus berubah.
Sebagaimana dikatakan Saskia Sassen: “Kota adalah ruang politik yang terus dinegosiasikan ulang oleh aktor-aktornya.” Maka, pemekaran Sofifi adalah bagian dari proses negosiasi panjang atas ruang, wewenang dan masa depan.
Apa yang harus dituntut hari ini bukan sekadar pemekaran sebagai keputusan elite, melainkan pembukaan ruang deliberatif yang luas bagi masyarakat. Suara warga, terutama yang bermukim di Sofifi dan sekitarnya, harus menjadi pusat dalam pusaran wacana ini.
Jangan sampai suara rakyat dibungkam oleh retorika romantik sejarah atau dibajak oleh elite politik yang hendak menjadikan Sofifi sebagai pion dalam catur kekuasaan. Akhirnya, pemekaran bukan soal menyenangkan atau melukai siapa, melainkan bagaimana menjawab kebutuhan publik secara tepat.
Kita perlu keberanian untuk keluar dari zona nyaman sejarah dan menghadap ke masa depan dengan pikiran terbuka. “Masa depan selalu lahir dari keberanian untuk menata ulang struktur yang tak lagi relevan.”
Tantangan terbesar dalam pemekaran Sofifi bukan sekadar memisahkan garis administratif, melainkan membentuk kepercayaan publik bahwa perubahan itu membawa dampak nyata. Sofifi tidak boleh menjadi contoh dari sekian banyak daerah otonomi baru yang lahir dalam euforia politik tapi tumbuh tanpa arah.
Ia harus dibangun dengan kerangka kebijakan yang kuat, desain kota yang visioner, serta kepemimpinan yang transformatif, bukan sekadar penggandaan struktur pemerintahan tanpa visi jangka panjang.
Di tengah kebutuhan itu, penting untuk membangun narasi kolektif yang mencakup semua pihak: Tidore, Sofifi, warga lokal, akademisi, dan pembuat kebijakan. Narasi yang tidak saling membatalkan, tetapi saling mengisi.
Narasi yang menyadari bahwa sejarah dan masa depan bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan, melainkan dua mata rantai yang harus disambung secara cermat dan adil.
Sofifi adalah anak zaman yang dilahirkan oleh cita-cita reformasi administratif, namun diasuh dalam kekacauan regulasi. Ia telah tumbuh sebagai wajah provinsi, tetapi belum sepenuhnya memiliki tubuhnya sendiri.
Selama dua dekade lebih, ia hanya menyandang gelar ibu kota tanpa perangkat penuh yang bisa mengatur dirinya. Bila ini dibiarkan, maka Sofifi akan terus menjadi paradoks: pusat kekuasaan yang kehilangan kendali atas dirinya.
Pemekaran, dalam konteks ini, bukan hanya soal desentralisasi kewenangan, tapi juga pengakuan atas identitas wilayah. Sofifi punya jejak tumbuhnya sendiri: perumahan ASN, fasilitas pemerintahan, bandara, pelabuhan, hingga ribuan penduduk yang telah menambatkan harapan di sana.
Tak mungkin lagi menganggapnya hanya sebagai “wilayah pinjaman” dari induk sejarah. Argumentasi yang menolak pemekaran seringkali jatuh dalam jebakan glorifikasi masa lalu. Padahal, sejarah yang baik adalah sejarah yang memberi arah, bukan membelenggu.
Bila Tidore pernah agung karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan geopolitik masa lalu, maka hari ini, kebesaran itu justru teruji dalam keberaniannya memberi ruang bagi lahirnya pusat baru yang lebih siap melayani rakyat.
Kita tidak bisa terus membiarkan Sofifi menjadi ibukota dengan status semi-ilegal. Pembangunan akan terus timpang, kepastian hukum menjadi abu-abu, dan warga terus berada dalam ketidakjelasan tata kelola. Apalagi di tengah tantangan iklim investasi, pelayanan publik, serta ketegangan antar-birokrasi yang menumpuk diam-diam.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya keputusan administratif, tapi keberanian politik. Keberanian untuk membentuk panitia kerja lintas institusi, menyusun rancangan undang-undang pemekaran yang adil dan melibatkan publik secara bermakna dalam setiap tahapannya.
Bukan pemekaran yang instan, tapi pemekaran yang terencana dan berakar pada aspirasi warga. Kita harus belajar dari daerah-daerah yang gagal karena terburu-buru melepaskan diri tanpa kesiapan fiskal, kelembagaan dan sosial.
Tapi kita juga tidak boleh terjebak dalam ketakutan berlebihan sehingga menunda hak konstitusional sebuah wilayah untuk mengatur dirinya sendiri. Sofifi harus menjadi model otonomi baru yang matang, bukan sekadar tambahan dalam statistik nasional.
Bila sejarah memberi kita peluang, maka tanggung jawab kita hari ini adalah memanfaatkannya dengan arif. Sebab dalam setiap keputusan pemekaran, tersembunyi pertaruhan antara masa lalu yang kita hormati, dan masa depan yang sedang menunggu dibentuk.
Sofifi bukan ancaman bagi siapa pun. Ia hanyalah wujud dari dinamika sejarah yang tengah mencari bentuk terbaiknya untuk melayani rakyat. Kota bukan hanya ruang geografis, melainkan janji yang ditagih oleh masa depan.
Dalam percakapan akademik dan seminar-seminar kebijakan, sejumlah pakar tata kelola wilayah dan pemerintahan daerah telah menyatakan bahwa Sofifi adalah salah satu contoh paling nyata dari kekosongan institusional yang dibiarkan terlalu lama.
Profesor Djohermansyah Djohan, pakar otonomi daerah, dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa “wilayah ibukota provinsi seharusnya tidak berada dalam ambiguitas hukum karena itu akan menggerogoti legitimasi kelembagaan negara di mata rakyat.”
Pernyataan ini sejalan dengan hasil kajian dari Kementerian Dalam Negeri yang mendorong penyempurnaan status ibukota sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya guna.
Dukungan terhadap pemekaran Sofifi juga datang dari internal Maluku Utara sendiri. DPRD Provinsi Maluku Utara melalui sejumlah fraksi telah menyatakan bahwa Sofifi perlu dimekarkan agar memiliki otoritas administratif yang penuh, terutama untuk menghindari tumpang tindih kebijakan antara provinsi dan Kota Tidore Kepulauan.
Gubernur Maluku Utara, dalam beberapa pidatonya, bahkan telah meminta agar Kemendagri dan Pemerintah Pusat menindaklanjuti aspirasi ini secara serius. Menurutnya, “Sofifi bukan soal pemisahan, tetapi soal penataan ulang agar ibukota kita punya jati diri yang utuh dan mandiri.”
Namun, keputusan sebesar ini tidak bisa hanya berbasis pada satu sisi. Karena itu, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di Maluku Utara. Tiga kesultanan besar selain Tidore yaitu Ternate, Bacan dan Jailolo–perlu menyampaikan pandangannya secara terbuka.
Bukan untuk mengintervensi, tetapi sebagai penjaga moral dan kebudayaan, para Sultan adalah simbol penyatu masyarakat lintas wilayah. Suara mereka sangat dibutuhkan untuk merawat harmoni di tengah transisi.
Demikian pula para kepala daerah. Setiap bupati dan walikota di Maluku Utara mesti diminta menyatakan sikapnya secara terbuka. Sebab Sofifi bukan hanya ibukota administratif, tetapi juga rumah bersama. Keberadaan Sofifi mempengaruhi sistem distribusi anggaran, pelayanan lintas kabupaten/kota, hingga konektivitas infrastruktur.
Maka tidak berlebihan jika kita meminta: bagaimana pendapat Bupati Halmahera Barat? Halmahera Selatan? Morotai? Kota Ternate? Semua harus diajak berdialog dalam satu meja, bukan hanya berdiri di balik meja.
Agar polemik ini tak menjadi wacana elitis semata, maka satu langkah demokratis harus diambil: menyelenggarakan uji publik atau survei independen. Biarlah rakyat Maluku Utara bersuara, apakah mereka mendukung pemekaran Sofifi atau tidak?
Apakah mereka merasa status quo lebih baik atau pemekaran lebih memberi harapan? Hasil survei ini harus terbuka, kredibel dan menjadi rujukan moral bagi para pembuat kebijakan. Di era demokrasi, kedaulatan rakyat tidak bisa lagi dibatasi oleh pagar administratif.
Tantangan terbesar dalam pemekaran Sofifi bukan sekadar memisahkan garis administratif, melainkan membentuk kepercayaan publik bahwa perubahan itu membawa dampak nyata. Sofifi tidak boleh menjadi contoh dari sekian banyak daerah otonomi baru yang lahir dalam euforia politik tapi tumbuh tanpa arah.
Ia harus dibangun dengan kerangka kebijakan yang kuat, desain kota yang visioner, serta kepemimpinan yang transformatif, bukan sekadar penggandaan struktur pemerintahan tanpa visi jangka panjang.
Di tengah kebutuhan itu, penting untuk membangun narasi kolektif yang mencakup semua pihak: Tidore, Sofifi, warga lokal, akademisi, dan pembuat kebijakan. Narasi yang tidak saling membatalkan, tetapi saling mengisi.
Narasi yang menyadari bahwa sejarah dan masa depan bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan, melainkan dua mata rantai yang harus disambung secara cermat dan adil.
Sofifi memang berdiri di tanah Oba, tapi darahnya mengalir dari seluruh penjuru Maluku Utara. Dari kapal yang berlayar dari Sanana, dari motor laut yang datang dari Makian, dari jalan poros yang dibuka dari Weda ke Patani, hingga suara para pelajar yang datang dari Morotai untuk menuntut ilmu di sana.
Maka tepat jika dikatakan: Sofifi adalah milik kita semua. Dan keputusan tentang masa depannya harus melibatkan kita semua. Sudah waktunya kita meninggalkan dikotomi “pro” dan “kontra” sebagai kubu yang saling menegasikan.
Yang harus kita jaga hari ini adalah etika deliberatif, semua pihak berhak menyampaikan pendapat, tetapi setiap suara harus ditimbang dengan nurani publik dan kepentingan jangka panjang. Jangan sampai kita terjebak pada pertarungan simbolik yang menjauh dari esensi: pelayanan dan keadilan struktural bagi warga.
Dalam tatanan hukum, ruang pemekaran daerah tetap terbuka. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi celah bagi pemekaran dengan syarat objektif dan administratif yang ketat.
Apalagi jika suatu wilayah berstatus ibukota provinsi, maka pemekaran bukan hanya sah secara regulatif, tapi juga diperlukan secara fungsional. Kini tinggal keberanian politik, koordinasi lintas aktor dan kemauan membuka diri pada aspirasi masyarakat yang menjadi kunci.
Jika akhirnya Sofifi dimekarkan, maka proses itu harus menjadi teladan: bagaimana sebuah wilayah lahir tidak dari pemaksaan, tapi dari hasil musyawarah luas, keterbukaan data, dan kejelasan arah pembangunan.
Dan, bila akhirnya tidak, maka keputusan itu pun harus diterima sebagai hasil kebijaksanaan kolektif, bukan sebagai kemenangan satu kelompok atas kelompok lain.
“Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana semua suara diberi ruang untuk didengar.”
***