Islam mengalami perubahan-perubahan besar dalam sejarahnya. Bukan ajarannya. Melainkan penampilan kesejarahan itu sendiri, meliputi kelembagaannya.
Mula-mula seorang nabi pembawa risalah (pesan agama, bertumpu pada tauhid) bernama Muhammad, memimpin masyarakat muslim pertama. Lalu empat pengganti (khalifah) meneruskan kepemimpinannya berturut-turut.
Pergolakan hebat akhirnya berujung pada sistem pemerintahan monarki. Begitu banyak perkembangan terjadi. Sekarang, ada sekian republik dan sekian kerajaan mengajukan klaim sebagai ‘negara Islam’.
Ironisnya, dengan ideologi politik yang bukan saja saling berbeda melainkan saling bertentangan dan masing-masing menyatakan diri sebagai ‘ideologi Islam’.
Kalau di bidang politik terjadi ‘pemekaran’ serba beragam, walau sangat sporadis, seperti itu, apalagi di bidang-bidang lain. Hukum agama masa awal Islam kemudian berkembang menjadi fiqh, yurisprudensi karya korps ulama pejabat pemerintah (qadi, mufti, dan hakim) dan ulama ‘non-korpri’.
Kekayaan sangat beragam itu lalu disistematisasikan ke dalam beberapa buah mazhab fiqh, masing-masing dengan metodologi dan pemikiran hukum (legal theory) tersendiri.
Terkemudian lagi muncul pula deretan pembaharuan yang radikal, menengah radikal, dan sama sekali tidak radikal. Pembaharuan demi pembaharauan dilancarkan, semuanya mengajukan klaim memperbaiki fiqh dan menegakkan ‘hukum agama yang sebenarnya’’, dinamai syari’ah.
Padahal, kaum pengikut fiqh dari berbagai mazhab itu juga menamai anutan mereka sebagai syari’ah. Kalau di bidang politik–termasuk doktrin kenegaraan–dan hukum saja sudah begitu balau keadaannya, apalagi di bidang-bidang lain: pendidikan, budaya, kemasyarakatan, dan seterusnya.
Tampak sepintas lalu bahwa kaum muslimin terlibat dalam sengketa di semua aspek kehidupan, tanpa terputus-putus. Dan ini lalu dijadikan kambing hitam atas melemahnya posisi dan kekuatan masyarakat Islam (ummah).
Dengan sendirinya lalu muncul kedambaan akan pemulihan posisi dan kekuatan, melalui pencarian paham yang menyatu dalam Islam, mengenai seluruh aspek kehidupan.
Dibantu oleh komunikasi semakin lancar antara bangsa-bangsa muslim semenjak abad yang lalu, dan kekuatan petrodollar negara-negara Arab kaya minyak, kebutuhan akan ‘penyatuan’ pandangan itu akhirnya menampilkan diri dalam kecenderungan sangat kuat untuk menyeragamkan pandangan.
Tampillah dengan demikian sosok tubuh baru: formalisme Islam. Masjid beratap genteng, yang sarat dengan simbolisasi lokalnya sendiri di negeri kita, dituntut untuk ‘dikubahkan’.
Budaya wali songo yang ‘serba Jawa’, Seudati Aceh, Tabut Pariaman, didesak ke pinggiran oleh qasidah berbahasa Arab dan juga MTQ yang berbahasa Arab. Bahkan ikat kepala lokal (udeng atau iket di Jawa) harus mengalah kepada sorban ‘merah putih’ model Yasser Arafat.
Begitu juga hukum agama, harus diseragamkan dan diformalkan: harus ada sumber pengambilan formalnya, Al Quran dan Hadist. Padahal, dahulu cukup dengan apa kata kiai.
Pandangan kenegaraan dan ideologi politik tidak kalah dituntut harus ‘universal’: yang benar hanyalah paham Sayyid Qutb, Abdul A’la Al-Maududi atau Khomeini. Pendapat lain, yang sarat dengan latar belakang lokal masing-masing, mutlak dinyatakan salah.
Lalu, dalam keadaan demikian, tidakkah kehidupan kaum muslimin tercerabut dari akar-akar budaya lokalnya? Tidakkah ia terlepas dari kerangka kesejarahan di masing-masing tempat? Di Mesir, Suriah, Irak, dan Aljazair, Islam ‘dibuat’ menentang nasionalisme Arab–yang juga masing-masing bersimpang-siur warna ideologisnya.
Di India menolak wewenang mayoritas penduduk yang beragama Hindu, untuk menentukan bentuk kenegaraan yang diambil. Di Arab Saudi bahkan menumpas keinginan membaca buku-buku filsafat dan melarang penyimakan literatur tentang Sosialisme.
Di negeri kita, sayup-sayup suara terdengar untuk menghadapkan Islam dengan Pancasila secara konfrontatif–yang sama bodohnya dengan upaya sementara pihak untuk menghadapkan Pancasila dengan Islam.
Anehkah kalau terbetik di hati adanya keinginan sederhana: bagaimana melestarikan akar-akar budaya lokal yang telah memiliki Islam di negeri ini? Ketika orang-orang Kristen meninggalkan pola gereja katedral ‘serba Gothik’ di kota-kota besar dan ‘gereja kota kecil’ model Eropa.
Dan mencoba menggali arsitektur asli kita sebagai pola baru bangunan gereja, layakkah kaum muslimin lalu ‘berkubah’ model Timur Tengah dan India? Ketika ekspresi kerohanian umat Hindu menemukan vitalitasnya pada gending tradisional Bali, dapatkah kaum muslimin ‘berkasidahan Arab’ dan melupakan ‘pujian’ berbahasa lokal tiap akan melakukan sembahyang?
Juga, mengapa harus menggunakan kata ‘salat’, kalau kata ‘sembahyang’ juga tidak kalah benarnya? Mengapakah harus ‘dimushallakan’, padahal toh cukup langgar atau surau? Belum lagi ulang tahun, yang baru terasa ‘sreg’ kalau dijadikan ‘milad’.
Dahulu tuan guru atau kiai, sekarang harus ustadz dan syekh, baru terasa berwibawa. Bukankah ini pertanda Islam tercerabut dari lokalitas yang semula mendukung kehadirannya di belahan bumi ini?
Kesemua kenyataan di atas membawakan tuntutan untuk membalik arus perjalanan Islam di negeri kita, dari formalisme berbentuk ‘Arabisasi total’ menjadi kesadaran akan perlunya dipupuk kembali akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejarahan kita sendiri.
Penulis menggunakan istilah ‘pribumisasi Islam’, karena kesulitan mencari kata lain. ‘Domestikasi Islam’ terasa berbau politik, yaitu penjinakan sikap dan pengebirian pendirian.
Yang ‘dipribumikan’ adalah manifestasi kehidupan Islam belaka. Bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya.
Tidak diperlukan ‘Quran Batak’ dan ‘Hadist Jawa’. Islam tetap Islam, di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan ‘bentuk luar’-nya. Salahkah kalau Islam ‘dipribumikan’ sebagai manifestasi kehidupan?
***
—-
Penulis: Abdurrahman Wahid
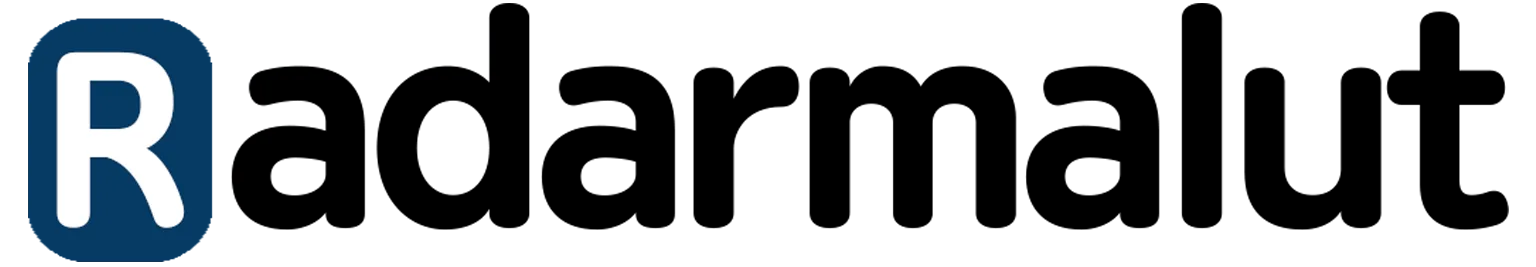


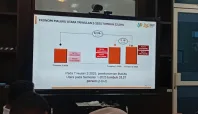




Tinggalkan Balasan